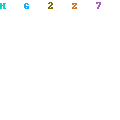Sebuah ide dari guyonan, bahkan cenderung gila, bisa menjadi masuk akal di tengah kebuntuan. Begitulah ide ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengenai “kebun koruptor” tampak masuk akal. Ia bisa menjadi ide cemerlang di tengah kefrustasian akan keadaan.
Korupsi memang satu soal besar di negara kita. Bahkan, begitu tidak berdayanya pemerintah, juga lembaga-lembaga anti-korupsi, dalam menghadapi perilaku korup membuat orang hampir putus-asa. Korupsi berjalan terus..dan terus!
Muncur pertanyaan: apakah ide membuat “kebun koruptor” bisa dipraktekkan dan seberapa efektif ide itu bisa mengurangi perilaku koruptif?
Ide “kebun koruptor” memang sangat mungkin dipraktekkan. Ide mempermalukan koruptor sendiri sudah banyak diusulkan; mulai dari usulan baju khusus untuk koruptor, penjara khusus untuk koruptor, dan lain sebagainya.
Di negara lain, khususnya Tiongkok, ide mempermalukan koruptor juga terkadang dipakai, disamping model hukuman yang keras: hukuman mati. Di sana, katanya, koruptor diborgol tangan dan kakinya, serta menjalani kerja paksa yang ditayangkan oleh televisi nasional.
Seberapa efektif ide mempermalukan koruptor di negara kita? Menurut kami, seorang koruptor adalah manusia yang sudah hilang rasa malunya. Mereka sanggup melakukan tindakan korupsi karena merasa tidak malu terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya. Bahkan, ketika seorang koruptor sudah menjalani penjara atau hukuman, ia tidak akan merasa malu ketika kembali ke masyarakat.
Hukuman berat juga belum tentu efektif di negara kita. Ini hanya soal memberi efek jera kepada koruptor dan calon koruptor. Difikirnya, dengan memberi efek jera seperti itu, orang akan berfikir dua kali untuk melakukan tindakan serupa.
Akan tetapi, bagi kami, hal semacam itu belum tentu efektif di Indonesia: negara yang sistim ekonomi dan politiknya sangat membuka celah bagi korupsi. Proses penegakan hukum di Indonesia juga sangat gampang “terbeli”. Jadi, metode mempermalukan dan menghukum berat koruptor belum tentu efektif.
Justru, bagi kami, pemberantasan korupsi di Indonesia mesti juga bersifat sistemik. Artinya, gerakan memberantas korupsi harus melekat dengan perjuangan untuk mengubah sistim ekonomi dan politik yang korup ini. Selama ekonomi nasional kita belum produktif, maka korupsi sebagai penyakit tentu akan terus-menerus tumbuh dan berkembang.
Sistim politik kita juga sangat rentan dengan korupsi. Selain terlalu birokratis, sistim politik kita juga sangat jauh dari kontrol dan partisipasi rakyat. Sistim politik kita memungkinkan kontrol terhadap sumber daya dan kekayaan publik tersentralisasi di tangan segelintir elit/pejabat politik. Hal itu menyebabkan jabatan politik menjadi ‘surga abadi” bagi para koruptor.
Untuk itu, jika hendak memerangi korupsi, maka sistim ekonomi dan politik ini perlu dirombak total. Ekonomi nasional yang tidak produktif, karena dikangkangi oleh imperialisme dan segelintir swasta nasional, menyebabkan konsentrasi kekayaan ke tangan segelintir orang. Ekonomi nasional yang tidak produktif ini juga tidak menyediakan basis akumulasi yang produktif pula.
Selain itu, sistim kapitalisme juga mengajarkan korupsi secara inheren: kapitalisme adalah sistim yang tumbuh karena pencurian nilai lebih, karena perampasan hasil kerja dan keringat manusia yang bekerja, dan perampasan kemakmuran bangsa lain. Kapitalisme juga mengajarkan fetitisme terhadap uang dan kekayaan.
Karena itu, bagi kami, hanya dengan menghapuskan imperialisme dan kapitalismelah yang membuka jalan untuk pemberantasan korupsi yang sejati. Dan, hanya dengan kekuasaan politik yang ditransfer ke rakyatlah yang membuat sistim politik makin sehat dan menjauh dari praktek korupsi.
Kalau proses politik dikontrol dan dijalankan langsung oleh rakyat, termasuk perumusan kebijakan dan penentuan alokasi sumber daya, maka korupsi bisa dikurangi hingga tingkat yang paling rendah.
Selengkapnya...
Efektifkah Kebun Koruptor..?
Kita Butuh Pemimpin Penggerak Rakyat
Indonesia masa kini sedang krisis kepemimpinan. Pemimpin sekarang punya banyak kelemahan: terlalu mengalah kepada kepentingan asing, tidak sanggup menjaga kepentingan nasional, tidak mampu menggerakkan rakyat, dan kurang cakap dalam mengelola pemerintahan.
Dulu, pada tahun 1950, Herbert Feith, penulis buku “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962)”, membagi dua tipe pemimpin Indonesia: administrator (ahli pemerintahan) dan solidarity maker (pemimpin massa).
Kategori administrator adalah orang yang memiliki kemampuan hukum, teknis pemerintahan, dan kecakapan bahasa asing yang diperlukan untuk menjalankan negara modern. Sedangkan tipe solidarity maker adalah mereka yang memiliki keahlian menghimpun dan membakar gelora massa.
Kita akan membahas tipe kedua, yaitu solidarity maker. Feith sendiri kurang setuju dengan tipe solidarity-maker ini, karena dianggapnya hanya pandai memberikan harapan yang muluk tentang masa depan Indonesia, tapi tidak memiliki kecakapan untuk mewujudkannya. Tetapi, bagi kami, tipe pemimpin solidarity-maker justru sangat dibutuhkan dalam situasi seperti saat ini: kita terkotak-kotak dalam berbagai partai yang berorientasi sempit; rakyat kita teratomisasi menjadi individu tanpa orientasi kolektif; sementara kita terjajah oleh imperialisme.
Kita membutuhkan pemimpin yang bisa menggerakkan rakyat. Bagi Bung Karno, seorang pemimpin harus bisa menggerakkan rakyatnya untuk mencapai cita-cita nasional yang sudah dirumuskan. Ini semacam “leistar” yang menggerakkan rakyat menuju cita-cita masyarakat masa depan.
Bung Karno sendiri menyebut tiga syarat yang mesti dipunyai seorang pemimpin agar bisa menggerakkan rakyat: pertama, pemimpin harus bisa melukiskan cita-citanya kepada rakyat banyak. Kedua, pemimpin harus bisa membangunkan (menyakinkan) rakyat bahwa mereka mampu. Ketiga, setelah membangkitkan rasa mampu dari rakyat, seorang pemimpin harus mengetahui cara mengorganisir rakyat itu.
SBY sendiri masuk kategori pemimpin salon. Ia tidak punya kemampuan untuk menggerakkan massa rakyat. Banyak seruan-seruannya tidak diikuti oleh rakyat, bahkan terkadang dilawan oleh rakyat. Pasalnya, banyak seruan-seruan politiknya bertentangan dengan keinginan rakyat.
Jangankan pandai melukiskan cita-cita kepada rakyat banyak, SBY justru mengalah kepada kepentingan asing dan membiarkan cita-cita nasional kita tenggelam akibat amukan badai neoliberalisme. SBY pun gagal memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan seluruh rakyat.
Banyak seruan-seruan SBY juga bertolak-belakang antara ucapan dan tindakan. Sebagai contoh, ketika sedang berkampanye besar-besaran melawan korupsi, ia justru tidak punya itikad politik untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan anggota partai dan menteri di dalam kabinetnya.
Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Dulu, ketika Republik baru berdiri, rakyat Indonesia rela berkorban jiwa dan raga untuk memperjuangkan cita-cita itu. Sekarang, seiring dengan seringnya para pemimpin melupakan dan menghianati rakyatnya, rakyat pun seperti kehilangan asa dan harapan.
Dalam situasi sekarang ini, dimana penjajahan telah begitu menghisap bangsa kita, seorang pemimpin bertipe penggerak massa rakyat sangat diperlukan. Kita butuh seorang pemimpin yang pandai melukiskan cita-cita masa depan. Tetapi bukan cita-cita yang muluk-muluk, melainkan cita-cita yang lahir dari analisa dan tuntutan sejarah perkembangan masyarakat. Sejumlah bangsa di Amerika Latin, seperti Venezuela dan Bolivia, sedang merintis jalan cita-cita semacam itu. Lalu, kalau rakyat Bolivia dan Venezuela bisa melakukanya, kenapa kita tidak!
Selengkapnya...
Turunnya Produksi Padi Kita
Produksi padi Indonesia untuk tahun 2011 diperkirakan akan menurun. Menurut Biro Pusat Statistik, produksi padi berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) III diperkirakan turun hingga 1,63 persen atau 1,08 juta ton. Penurunan juga terjadi pada produksi jagung dan kedelai.
Merespon produksi padi yang jeblok itu, pemerintah justru menyalahkan petani. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa produktivitas padi rendah karena petani tidak bisa menggunakan teknologi. “Problemanya adalah ketidakmampuan melaksanakan anjuran teknologi di tingkat usaha tani,” kata Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Udhoro Kasih Anggoro, seperti dikutip TEMPO.
Persoalannya tidaklah sesederhana itu. Jika ditinjau dengan seksama, penyebab penurunan produksi padi banyak disebabkan oleh “kesalahan pemerintah”. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah justru banyak memproduksi kebijakan yang merugikan kaum tani, seperti kebijakan impor beras, pencabutan subsidi pertanian, dan lain-lain.
Impor pangan menyebabkan petani kehilangan akses pasar mereka. Lemahnya daya dukung pemerintah dalam urusan permodalan dan teknologi menyebabkan petani tidak bisa bersaing secara bebas dengan produk impor. Akibatnya, karena ketidakmampuan bersaing itu, petani banyak yang bertransformasi menjadi kaum urban.
Atas anjuran IMF dan Bank Dunia, pemerintah juga sangat intensif memangkas subsidi atau anggaran untuk pertanian. Pemerintah juga gagal untuk menjamin ketersediaan pupuk murah dan massal bagi petani. Dalam banyak kasus, pemerintah hanya pura-pura tuli ketika petani di berbagai daerah menjerit akibat kelangkaan atau mahalnya harga pupuk.
Petani juga tidak bisa mengakses modal. Pemerintah tidak punya skenario pembiayaan pertanian yang efektif. Di negara lain, khususnya Venezuela, pemerintah membangun bank khusus untuk pertanian. Bank inilah yang berfungsi untuk menyalurkan kredit mikro kepada seluruh petani.
Penurunan produksi pertanian juga berkaitan dengan menyusutnya jumlah lahan pertanian. Banyak lahan pertanian yang berpindah tangan ke swasta dan beralih-fungsi menjadi perkebunan sawit, kawasan bisnis, dan lain sebagainya. Sementara banyak lahan menganggur tidak bisa diproduktifkan oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak konsisten menjalankan reformasi agraria sebagaimana diamanatkan UUPA 1960. Padahal, belum ada negara di dunia yang sukses membangun pertanian dan tumbuh menjadi industrialis tanpa melampaui reforma agraria.
Infrastruktur pertanian juga sangat buruk. Sedikitnya 3,21 juta hektare, atau 45% dari total jaringan irigasi di Indonesia, mengalami kerusakan. Kerusakan irigasi ini berkontribusi pada menurunnya produksi pertanian. Sementara itu, masih banyak juga lahan pertanian di Indonesia yang belum tersentuh sistim irigasi yang baik.
Infrastruktur lainnya, seperti waduk dan bendungan, juga tidak memadai. Pemerintah SBY-Budiono hampir tidak bisa melakukan apa-apa terhadap infrastruktur ini. Bahkan banyak waduk yang mengalami pengeringan. Infrastruktur lain yang turut bermasalah adalah jalan desa. Banyak jalan desa yang mengalami kerusakan parah dan sama sekali tidak tersentuh oleh program rehabilitasi pemerintah. Padahal, jalan desa sangat membantu petani dalam proses distribusi hasil pertanian.
Meski sering gembar-gembor soal swasembada pangan, pemerintahan SBY-Budiono sendiri tidak punya program konkret untuk membangun pertanian. Sebaliknya, SBY-Budiono justru menyerahkan sektor pertanian di bawah tekuk neoliberalisme.
Selengkapnya...
Sejumlah Paradoks di Negeri Kita
Sejarah memang membentangkan paradoks kepada kita. Terkadang paradoks itu cukup menggelikan. Tetapi itulah kenyataan yang mesti kita hadapi dan langkahi untuk melangkah maju kepada masa depan yang lebih baik.
Paradoks pertama, yang baru saja diumumkan kemarin (28/11), adalah fakta bahwa Departemen Agama menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Dari survey integritas yang diselenggarakan KPK, diketahui bahwa memiliki indeks integritas terendah, mencapai 5,37, disusul Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,44) dan Kementerian Koperasi dan Usahan Kecil dan Menengah (5,52).
Ini adalah paradoks: Lembaga yang paling banyak berhubungan dengan urusan moral justru ditempatkan sebagai lembaga terkorup. Ini sekaligus menjelaskan bahwa korupsi bukanlah sekedar urusan moral, tetapi sudah merupakan problem sistem. Kapitalisme, entah dengan wajah apapun, telah menjadi penyebab korupsi kian merajela.
Paradoks lainnya adalah soal pengelolaan kekayaan alam kita: kita punya garis pantai terpanjang di dunia, tetapi kita juga adalah pengimpor garam terbesar di dunia; kita memiliki lahan pertanian terluas di dunia, tetapi kita juga pengimpor produk-produk pangan terbesar di dunia; kita termasuk pengekspor gas dan batubara terbesar di dunia, tetapi PLN terus-menerus mengeluhkan kurangnya bahan bakar dan harus melakukan pemadaman bergilir untuk mengatasi persoalan ini.
Kita juga memiliki lahan sawit yang sangat luas dan menjadi eksportir CPO terbesar di dunia, tetapi sebagian besar rakyat kita terus menjerit karena kelangkaan atau kenaikan harga minyak goreng di pasaran.
Dulu, di tahun 1930-an, Indonesia pernah merajai produksi gula kristal putih di dunia. Saat itu Indonesia (Hindia-Belanda) punya 179 pabrik dan sanggup memproduksi tiga juta ton pertahun. Tetapi, pada tahun 2010, produksi gula nasional hanya 2,44 juta ton dan kita pun berubah menjadi negeri “pengimpor”.
Media luar negeri menyebut Indonesia sebagai “Blackberry nation”, tetapi di sini ada separuh dari total penduduk yang hidup dengan penghasilan di bawah 2 USD/hari. Pada tahun 2010, Jumlah kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan sekitar 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin penduduk.
Seorang Presiden bisa membiayai pernikahan anaknya sebesar 20 milyar, sedangkan kekayaan si Presiden hanya tercatat sebesar Rp 7,14 miliar ditambah US$ 44.887. Sementara pejabat negara bisa berpesta-pora dengan kekayaannya, anak-anak di pedalaman Kalimantan harus berjalan kaki puluhan kilometer karena keterbatasan jumlah sekolah dan buruknya infrastruktur jalan serta transportasi.
Masih banyak paradoks di negeri ini. Silahkan para pembaca menambahkan!
Selengkapnya...
Ambruknya Jembatan Mahakam
editorial
Jembatan kebanggaan rakyat Kutai Kartanegara itu pun ambruk. Hari itu, 26 November 2011, banyak orang dan kendaraan yang sedang melintas di atas jalan itu. Belum diketahui pasti berapa orang yang menjadi korban dari tragedi memilukan itu.
Fondasi jembatan Mahakam II selesai tahun 2000 dan mulai resmi beroperasi pada tahun 2002 lalu. Artinya, jembatan sepanjang 710 meter itu baru berumur kira-kira sepuluh tahun. Konon, jembatan ini didesain untuk 40 tahun, bahkan hingga 100 tahun. Entah mengapa, jembatan yang digelari “Golden Gate Kalimantan” itu terlalu cepat roboh.
Orang-orang pun mulai menduga-duga: ada yang salah dengan pembangunan dan proses perawatan jembatan itu. Jangan-jangan terjadi ketidaksesuaian antara bahan-bahan yang direncanakan dengan bahan yang dipergunakan. Motifnya: demi mendapatkan untung besar, maka pihak kontraktor menggunakan bahan yang lebih murah dan kurang bermutu. Bisa saja demikian!
Bisa pula, proses pembangunan jembatan ini sangat tergesa-gesa. Sehingga, beberapa aspek standar untuk memperkuat kualitas jembatan tak terpenuhi. Pemerintah pun tidak melakukan pengecekan secara teliti mengenai kesiapan jembatan itu. Akhirnya, karena ada faktor-faktor yang luput untuk terpenuhi, maka jembatan itu pun ambruk sebelum waktunya.
Mungkin juga ambruknya jembatan itu terkait pemeliharaan. Kesimpulan ini paling banyak diikuti oleh pejabat pemerintah di tingkatan pusat. Maklum, jika masalahnya memang pemeliharaan, maka pejabat dan petugas setempatlah yang “kena batunya”. Sementara pejabat berwenang di pusat bisa terhindar dari tanggung-jawab.
Akan tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri: ambruknya jembatan Mahakam II menyingkap buruknya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Banyak proyek pembangunan infrastruktur disandera oleh mafia anggaran dan mafia proyek. Tidak sedikit anggaran pembangunan yang sudah “tersunat” sejak awal ketika masih di bahas di DPR. Belum lagi ketika proyek itu ditenderkan, hingga proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor.
Tetapi hal-hal di atas hanya penyebab di permukaan saja. Ada penyebab yang lebih mendasar: semakin lunturnya semangat kebangsaan kita dan makin takluknya kita dihadapan kuasa keuntungan (profit). Orang tidak lagi membangun seperti membangun kebesaran dan kejayaan bangsanya. Orang-orang itu, umumnya kaum swasta, hanya membangun demi mendapatkan untung sebesar-besarnya. Dia tidak pernah berfikir tentang kepentingan nasional, apalagi kepentingan rakyat dan generasi di masa depan.
Lihatlah jembatan Ampera di atas sungai Musi, Sumatera Selatan. Kendati sudah berusia hampir 50 tahun, jembatan peninggalan pemerintahan Bung Karno itu masih terlihat kokoh berdiri dan sekaligus menjadi kebanggan nasional kita. Jembatan itu dibangun memang untuk menunjukkan kebanggaan nasional bangsa kita.
Menjadi benar apa yang dikatakan Bung Karno 50-an tahun lalu, bahwa soal membangun bukan sekedar kemajuan teknik dan keahlian, tetapi juga soal pembangunan mental manusia Indonesia itu sendiri. Pembangunan mental, atau sering disebut “mental invesment”, adalah dasar untuk memberi proyek pembangunan itu punya arah yang jelas: mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur di masa depan.
Sehingga, apapun yang hendak kita ciptakan dan hendak bangun, ia harus tahan lama dan tahan dalam segala keadaan. Apa yang kita ciptakan dan bangun mestilah berkontribusi untuk membuat rakyat Indonesia bisa lebih adil dan makmur. Dengan demikian, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan, bukan keuntungan demi kepentingan pribadi.
Selengkapnya...
Search
Pengunjung
Kategori
- Berdikari (14)
- Internasional (4)
- Kabar Juang (3)
- Kabar Rakyat (4)
- Organisasi (1)
- Politik (8)
- sastra (1)
- Soekarnoisme (6)
- Statement (5)
- Tokoh (4)
Jaringan
Mengenai Saya
- Randy Syahrizal
- mempunyai minat menulis sejak kuliah di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra USU tahun 2003. Pernah menulis di beberapa media lokal (Sumatera Utara) dan Media Online Nasional. Blog pribadi saya : http://ceritadarimedan.blogspot.com