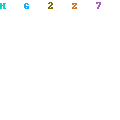diambil dari rangkuman diskusi rutin KPW-PRD Sumatera Utara
Tahun-tahun sekarang ini adalah tahun kemenangan Neoliberalisme. Setelah sukses dalam konsolidasi besar meneguhkan kepemimpinan Neolin di Indonesia selama 2 periode, Neoliberalisme semakin mapan di Bumi Pertiwi. Hampir tidak ada lagi paket kebijakan Negara yang dapat menghempang jalan dan beroperasinya system ekonomi liberal. Negara yang dipimpin oleh Kabinet Neolib dengan sukses mencampakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bernegara, sebagai kepribadian Negara, sebagai moralitas Negara. Akhirnya, Neolib di Indonesia dengan sukses menempuh jalan tol dalam meng-goa-kan paket kebijakannya. Pemerintahan kita nyaris tidak punya proteksi dalam melindungi kekayaan alam yang dirampok di negerinya sendiri.
Kemenangan Neoliberal dan semakin matangnya laju neoliberalisme di Indonesia bias dilihat dalam kasus terbaru yang hamper setiap hari kita saksikan di TV, dan menyita waktu banyak orang di Indonesia dalam memperbincangkan kasus ini, yakni kasus kebrutalan PT Freeport.
Selama 44 tahun Freeport mengeksploitasi tambang emas dan tembaga di tanah Papua, pihak Indonesia mendapat 1% dan pihak Freeport (imperialis) mendapat 99%. Jadi, pihak yang diuntungkan dari situasi Papua saat ini adalah imperialis. Dahulu, rakyat Papua bebas mencari makan di tanahnya sendiri. Setelah kemerdekaan di interupsi oleh rezim ORBA, rakyat Papua tidak lagi merdeka mencari makan. Saat ini, Freeport yang tidak bermanfaat untuk rakyat Papua sudah leluasa menguasai aparatur Negara, terbukti dengan pengiriman pasukan TNI/Polri untuk menjaga kepentingan PT. Freeport di Papua. Ini bukanlah karena ekspresi nasionalisme Indonesia. Tetapi sebaliknya: hal itu dilakukan karena pemerintahan Indonesia sekarang adalah boneka imperialisme. TNI/Polri justru diperalat (dipergunakan) untuk menjaga kepentingan neo-kolonialisme di Papua.
Memang ada kemajuan dalam perlawanan gagasan jalan keluar krisis imperialisme, yakni dengan mengobarkan semangat kemandirian nasional. Paling tidak sentiment ini secara serentak dihembuskan oleh semua elemen-elemen yang anti Imperialisme. Sentimen tersebut kemudian meluas, dan tidak hanya menjadi perbincangan dikalangan aktivis saja, melainkan menjadi jualannya kaum brjuasi nasional di kancah Pemilu 2009 yang lalu.
Meski banyak gerakan Anti Imperialis bermunculan dengan menghembuskan irama yang serupa, namun masih belum menciptakan sebuah persatuan nasional yang kokoh, sebagai syarat untuk perimbangan kekuatan pro neolib. Padahal, fakta-fakta Indonesia menuju kebangkrutan sudah semakin nyata, diantaranya karena 1. Indonesia masih menjadi komoditas utama bahan mentah, yakni Batu Bara (70%), Minyak (50%), Gas (60%) dll. 2. Indonesia masih menjadi tempat penanaman modal asing, yakni hamper 70% Industri di Indonesia adalah modal asing, diantaranya Minyak dan Gas (80%), Perbankan (50%), Pelayaran (94%), Pendidikan (49%).Yang ketiga, Indonesia masih menjadi tempat pemasaran barang-barang hasil produksi Negara-negara maju. Dan terakhir Indonesia masih menjadi penyedia tenaga kerja murah.
Pasal 33 sebagai Alat Pemersatu dan Senjata Melawan Neolib
Didalam Pembukaan UUD 1945, Para pendiri Negara ini dengan tegas menuliskan tujuan-tujuan dan dasar-dasar kita bernegara, yakni untuk menghapuskan penindasan di muka Bumi, menciptakan perdamaian dan mensejahterakan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan Pasal 33 adalah perisai Negara dalam membentengi rakyat Indonesia dari pengaruh jahat neoliberalisme. Dasar Negara kita tidak lagi dijalankan oleh Kabinet kaki tangan Asing seperti saat sekarang ini, sehingga dasar Negara tersebut tidak berfungsi sebagai perisai rakyat dalam melawan kepentingan serakah asing.
Ada 3 semangat didalam Pasal 33 UUD 1945, yakni 1. Sosio ekonomi, yaitu Perekonomian disusun secara bersama dan untuk kesejahteraan bersama, 2. Sosio Nasional, yakni Penguasaan kekayaan Alam oleh Negara dan diselenggarakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 3. Sosio Kerakyatan, yakni usaha-usaha dalam membangun perekonomian rakyat dan menyejahterakan rakyat Indonesia.
Semangat tersebut tentu bertentangan dengan kepentingan Imperialisme ditanah air, yakni Penguasaan bahan baku melalui perampokan kekayaan alam, kedua penguasaan dan pelebaran pasar, dan ketiga yakni mendapatkan tenaga kerja murah. Jika pasal 33 UUD 1945 diterapkan oleh Rezim SBY-Budiono, mustahil Neoliberalisme mendapatkan pondasinya di negeri ini. Namun elit politik kita lupa pesan bung KArno, yakni “Biarkanlah kekayaan alam kita disini sampai Insinyur-Insinyur kita mampu mengelolanya.”
Pasal 33 mempunyai kekhususan tersendiri, yakni karena dia adalah bagian dari dasar Negara kita, dan kedudukannya sebagai UU adalah kedudukan tertinggi. Jadi perjuangan ditegakkannya Pasal 33 UUD 1945 adalah perjuangan konstitusional yang legal dan berkemampuan meluas.
Pasal 33 adalah antitesis dari kepentingan serakah asing didalam negeri. Pasal 33 adalah tembok raksasa dalam membendung keserakahan-keserakahan asing. Gerakan pasal 33 haruslah menjadi gerakan yang dapat mempersatukan semua kekuatan bangsa yang ingin melihat kemandirian bangsa Indonesia, yang tidak lagi ketergantungan kepada asing, dan yang mampu membuka lapangan kerja dengan penguasaan kekayaan alam oleh Negara. Pasal 33 UUD 1945 haruslah menjadi ruh dalam gerakan pengembalian kekayaan alam.
Selengkapnya...
Memajukan Gerakan Pasal 33 UUD 1945 dalam Memimpin Gerakan Pengembalian Kekayaan Alam
Puluhan Aktivis Serukan Gerakan Pasal 33 Di Samarinda
Gerakan Pasal 33
Oleh : Niko
Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP-33) menggelar aksi di depan Mall Lembuswana, Samarinda. Mereka menyerukan perlawanan terhadap imperialisme, penegakan kembali pasal 33 UUD 1945, dan pelaksanaan reforma agraria.
Selain menggelar orasi secara bergantian, para aktivis mahasiswa ini membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan. “Imperialisme neoliberal hanya menghasilkan kemiskinan,” teriak seorang orator.
Menurut Parsauran Damanik, aktivis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), setelah 66 tahun bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bangsa Indonesia semakin menjauh dari cita-cita masyarakat adil dan makmur.
“Kita sekarang murni menjadi negara jajahan. Indonesia hanya menjadi penyedia bahan baku bagi negeri imperialis, penyedia tenaga kerja murah, pasar bagi produk negeri imperialis, dan tempat penanaman modal asing,” ujarnya.
Salah satu bukti konkretnya lagi, kata Parsauran, bahwa upah pekerja di Indonesia adalah terendah di Asia. Bahkan upah pekerja Indonesia tiga hingga empat kali lebih rendah dibanding Malaysia.
Katanya, situasi itu kian diperparah dengan dipraktekkannya sistim kontrak dan outsourcing.
Untuk itu, dalam pernyataan sikapnya, Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP-33) Samarinda menuntut agar penyelenggara negara kembali kepada semangat dan filosofi pasal 33 UUD 1945.
Mereka juga menuntut agar pemerintah segera melaksanakan UU Pokok Agraria tahun 1960 sebagai turunan dari semangat pasal 33 UUD 1945. Lebih lanjut, gerakan ini juga mendesak pemerintah segera menasionalisasi asset-aset strategis dan kemudian diserahkan di bawah kontrol rakyat.
Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 Samarinda merupakan aliansi bersama antara Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Selengkapnya...
Amandemen UUD 1945 Harus Melalui Referendum!
Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah mengalami empat kali perubahan (amandemen). Sekonyong-konyong perubahan itu membongkar pula beberapa landasan dasar mengenai sistim politik dan ekonomi Indonesia. Amandemen itu juga merombak batang tubuh dan menghapus penjelasan UUD 1945.
Sejalan dengan proses amandemen itu, sistem politik Indonesia pun semakin mengarah pada model demokrasi liberal. Gedung parlemen itu kita hari dipenuhi dengan riuh-gaduh perdebatan anggota parlemen. Akan tetapi, hampir semua perdebatan itu tidak pernah berkaitan dengan persoalan rakyat.
Di bidang ekonomi, amandemen UUD 1945 telah membuka jalan untuk membongkar filisofi mendasar pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistim ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen dibuat permisif terhadap kepemilikan swasta dan dominasi modal asing. Padahal, filosofi pasal 33 UUD 1945 sangatlah memerangi liberalisme dan anti-kapitalisme.
Boleh dikatakan, empat kali amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari proyek mengubah desain sistem ekonomi dan politik Indonesia, agar sejalan dengan tuntutan dan kepentingan imperialisme. Tidak salah kemudian jika Gus Dur, mantan Presiden RI, menyatakan penolakan keras terhadap UUD hasil perubahan. “perubahan UUD itu telah diselundupkan oleh lembaga-lembaga asing melalui para anggota MPR yang waktu itu dipimpin oleh Prof. Dr. Amin Rais,” kata almarhum Gus Dur.
Lebih parah lagi, empat kali proses amandemen itu tidak satupun yang meminta pendapat atau konsultasi dengan rakyat Indonesia. Padahal, di banyak negara, setiap perubahan terhadap satu pasal dala konstitusi mesti dilakukan melalui referendum. Juga dalam Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 dikatakan: “bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.”
Lalu, sekarang muncul lagi keinginan kuat dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendorong amandemen ke-V. Bahkan, demi mendapatkan kewenangan atas lembaganya, anggota DPD seperti ngotot memaksakan amandemen terhadap UUD 1945 tanpa konsultasi dengan rakyat.
Bung Karno memang mengatakan, “UUD ini bersifat sementara dan nanti kalau kita bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.”
Sekalipun begitu, bukan berarti bahwa amandemen terhadap UUD 1945 bisa dilakukan dengan serampangan dan seenaknya. Setiap proses amandemen mesti dikonsultasikan dengan rakyat Indonesia melalui referendum. Referendum itu tidak hanya menanyakan apakah rakyat setuju atau tidak terhadap amandemen, tetapi sampai pada memperdebatkan usulan perubahan.
Karena, menurut kami, UUD 1945 boleh saja mengalami perubahan, tetapi ada beberapa filosofi atau bangunan dasar yang tidak boleh berubah: anti-kolonialisme, anti-liberalisme, dan selalu menomor-satukan kepentingan rakyat banyak. Perubahan UUD 1945 tidak boleh bertolak belakang dengan cita-cita revolusi agustus 1945.
Itulah mengapa, bagi kami, empat kali amandemen UUD 1945 sebelumnya dan rencana amandemen oleh DPD sangat bertolak-belakang dengan semangat anti-kolonalisme, anti-liberalisme, dan kepentingan rakyat banyak itu. Amandemen itu hanya merupakan upaya lebih lanjut untuk merestrukturisasi sistim politik dan ekonomi Indonesia agar semakin gampang menampung kepentingan asing.
Selengkapnya...
Nasionalisme Kita dan Persoalan Papua
“Saya seorang nasionalisme, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan”. Kata-kata itu diucapkan oleh Bung Karno saat menyampaikan pidato di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945–sering disebut hari lahirnya Pancasila. Pidato itu memberi gambaran cukup jelas mengenai corak nasionalisme seperti apa yang hendak dibangun bangsa Indonesia.
Orde baru-lah yang bertanggung-jawab atas penyempitan makna kebangsaan Indonesia itu menjadi sangat chauvinis. Di masa itulah proyek nasionalisme Indonesia dihancur-leburkan dan kemudian dijadikan pembenaran untuk menghancurkan protes atas ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan.
Jika anda baca tulisan-tulisan Bung Karno, juga founding father yang lain seperti Hatta dan Tan Malaka, nasionalisme Indonesia dirumuskan sangat anti terhadap segala bentuk penjajahan, bahkan anti terhadap kapitalisme.
Bung Karno menyebut corak nasionalisme Indonesia sebagai sosio-nasionalisme, yaitu nasionalisme yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (massa rakyat) dan menghapus kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. “sosio-nasionalisme adalah nasionalismenya kaum marhaen, dan menolak tiap tindak borjuisme yang menjadi sebab kepincangan itu,” tulis Soekarno dalam “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi”.
Hatta juga punya pandangan yang serupa dengan Bung Karno. Kata bung Hatta, kebangsaan kita bukan kebangsaan ningrat dan bukan kebangsaan kaum intelek, melainkan kebangsaan rakyat. Karena, bagi Hatta, “rakyat itu adalah badan dan jiwa suatu bangsa.”
Dengan demikian, melihat nasionalisme Indonesia tidak bisa dengan mempersamakannya dengan trend nasionalisme di barat. Nasionalisme Indonesia sejak dalam kandungan para penggagasnya sudah berkarakter progressif: anti-kolonialisme, anti-imperialisme, menghargai demokrasi, dan menghubungkan diri dengan internasionalisme.
Akan tetapi, ketika orde baru berkuasa, nasionalisme seolah seperti ditawan sehingga tidak bisa menentang masuknya kembali pengaruh neo-kolonialisme. Yang terjadi justru sebaliknya: orde baru hanya mengatasnamakan nasionalisme untuk membenarkan tindakannya menghancurkan protes dan kritik terkait ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan. Orde barulah yang menghancurkan bangunan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri bangsa itu.
Dengan melihat fikiran para founding father itu, kami pun menyatakan ketidaksetujuan dengan anggapan banyak orang bahwa persoalan kekerasan di papua adalah ekspresi dari superioritas kebangsaan atau nasionalisme Indonesia. Saya rasa pendapat itu sangat keliru dan sangat salah kaprah dalam melihat sejarah nasionalisme Indonesia itu.
Yang terjadi di Papua itu adalah proses rekolonialisme dan itu berjalan beriringan dengan proses rekolonialisme di Indonesia. Orde barulah yang pelaksana proyek kolonialisme di Indonesia. Dan, orde baru pula yang menjadi penjaga kepentingan neokolonialisme di Indonesia.
Jadi, pengiriman pasukan TNI/Polri untuk menjaga kepentingan PT. Freeport di Papua bukanlah karena ekspresi nasionalisme Indonesia. Tetapi sebaliknya: hal itu dilakukan karena pemerintahan Indonesia sekarang adalah boneka imperialisme. TNI/Polri justru diperalat (dipergunakan) untuk menjaga kepentingan neo-kolonialisme di Papua.
Lagi pula, selama 44 tahun Freeport mengeksploitasi tambang emas dan tembaga di tanah Papua, pihak Indonesia mendapat 1% dan pihak Freeport (imperialis) mendapat 99%. Jadi, pihak yang diuntungkan dari situasi Papua saat ini adalah imperialis.
Kesalahan cara pandang soal ini bisa berakibat fatal: ini akan menjadi pintu masuk bagi imperialisme untuk memisahkan atau menjauhkan dukungan rakyat (nation) Indonesia terhadap perjuangan rakyat Papua.
Selengkapnya...
Mana Cetak BIru Industrialisasi Nasional Kita ?
Sudah 66 tahun proklamasi kemerdekaan, sebagian besar barang-barang kebutuhan rakyat Indonesia masih diperoleh melalui impor. Lebih ironis lagi, bukan cuma barang-barang yang menggunakan teknologi tinggi yang diimpor, tetapi hasil bumi seperti garam dan kedele pun sekarang sudah diimpor.
Inilah yang mengkhawatirkan kita: bukan cuma gagal membangun industri, tetapi membangun pertanian pun tidak bisa. Padahal, pembangunan sektor pertanian mestinya menjadi dasar untuk membangun masa depan industri nasional kita. Itu sudah difikirkan oleh para pendiri bangsa sejak Indonesia masih dalam gagasan mereka.
Sejak jaman kolonial hingga sekarang, Indonesia harus berpuas sebagai “negara pengekspor bahan mentah”. Sektor industri tidak pernah berkembang dan tidak pernah sanggup mengatasi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk impor. Bahkan, sejak neoliberalisme kian massif di Indonesia, Industri manufaktur yang sudah “setengah-nafas” itu pun kian hancur.
Menurut ekonom dari Econit, Hendri Saparini, sampai sekarang ini Indonesia belum punya cetak biru industri nasional yang mengaitkan semua sektor untuk mendukung industri yang akan dikembangkan. Justru sebaliknya yang terjadi: pemerintah yang bermental inlander ini cukup puas menjadi pengekspor bahan mentah. Padahal, basis industrialisasi nasional kita adalah industri yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam kita.
Situasinya kian parah saat ini: kita seperti bangsa tanpa haluan. Pembangunan ekonomi tidak jelas mau mengarah kemana. Sementara pemerintah lebih doyan mengikut pada jalan ekonomi yang sudah didiktekan oleh Washington Consensus. Kehancuran ekonomi pun nampak jelas di depan mata: industri nasional gulung tikar, sektor pertanian babak belur, pasar dalam negeri dikuasai produk asing, dan lain sebagainya.
Malahan, di tengah-tengah kehancuran industri nasional itu, pemerintah tiba-tiba berbicara soal industri kreatif sebagai salah satu soko-guru perekonomian nasional. Bahkan, seusai reshuffle kabinet baru-baru ini, dibentuk kementerian khusus untuk menangani industri kreatif ini.
Tanpa mengabaikan arti penting industri kreatif bagi ekonomi nasional, tetapi gembar-gembor soal pengembangan sektor ini justru seolah hendak menutupi kegagalan membangun pertanian dan industri.
Padahal, kegagalan proyek Industrialisasi ini berkonsekuensi serius di Indonesia: meluasnya pengangguran, ketergantungan pada impor, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, kegagalan proyek industrialisasi juga membuat bangsa Indonesia makin kehilangan keterampilan, pengetahuan, kreatifitas, dan lain-lain. Kita seolah merasa cukup sebagai bangsa konsumen.
Kami justru melihat bahwa kegagalan proyek industrialisasi berkait erat dengan masih berlangsung proyek penjajahan (neo-kolonialisme) di Indonesia. Sejarah memperlihatkan bahwa proyek kolonialisme selalu berusaha memblokir upaya membangkitkan industri di dalam negeri.
Negeri-negeri imperialis mengingingkan agar Indonesia tetap menjadi negara penyedia bahan baku bagi industri mereka. Kalaupun ada pembangunan industri di negara jajahan, maka hal itu harus berasal dari modal atau investasi mereka. Selain itu, dengan ketiadaan industri nasional yang tangguh, maka Indonesia akan terus-menerus menjadi pasar bagi hasil produksi negeri-negeri imperialis.
Oleh karena itu, jika serius hendak membangun ekonomi nasional, maka proyek industrialisasi harus selaras dengan upaya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan membangkitkan produksi rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing.
Pada Agustus 1959, pemerintahan Sukarno sudah menyusun rancangan pembangunan semesta (overall planning). Para penggagasnya berharap bahwa bangsa Indonesia punya cetak biru dalam pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.
Rancangan pembangunan semesta itu bahkan sudah memberi dasar menuju pembangunan masyarakat sosialis Indonesia. Sayang sekali, sebelum proyek itu mencapai banyak kemajuan, pihak imperialis sudah menjegalnya. Mereka menggulingkan pemerintahan Bung Karno.
Bagi kami, sebagai awal yang baik untuk memulai kembali pembangunan nasional–jika pemerintah memang masih berkeinginan—ialah dengan mengembalikan semangat dan filosofi pasal 33 UUD 1945 sesuai keinginan para pendiri bangsa. Itulah pijakan kita untuk menyusun cetak biro industrialisasi nasional.
Selengkapnya...
Kenapa Modal Asing di Persoalkan..?
Sejak UU PMA disahkan tahun 1967, modal asing kembali mengambil ‘kendali’ dalam perekonomian nasional Indonesia. Bahkan, karena regulasi yang membuka pintu ekonomi lebar-lebar, modal asing sudah berada dalam posisi “mendominasi” perekonomian. Ia sudah berjengkelitan di atas karpet ekonomi nasional.
Perdebatan soal modal asing sudah berlangsung sejak lama. Ia bahkan sudah berlangsung sejak Indonesia ini masih dalam gagasan para pejuang pembebasan nasional. Saat itu, mereka sangat sadar betul bahwa modal asing merupakan bagian dari praktek penjajahan itu sendiri. Dalam pidato pembelaannya di depan pengadilan kolonial, yang kemudian dikenal dengan Indonesia Menggugat, Bung Karno sudah menandai penanaman modal asing sebagai aspek melekat dalam imperialisme modern.
Kami anggap pandangan itu tidak berubah hingga detik-detik menjelang Indonesia dimerdekakan. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), hampir semua peserta sepakat bahwa ekonomi Indonesia merdeka haruslah diorganisir dari kemampuan rakyat dan tidak bergantung kepada modal asing.
Sekarang ini Indonesia menjadi ‘lahan suburnya modal asing’. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, pada semester 1-2011 realisasi investasi sebesar Rp115,6 triliun, dimana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp33 triliun dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp82,6 triliun.
Sebagian besar investasi itu berasal dari Amerika dan Eropa. Modal AS di Indonesia pada 2008 mencapai USD157 juta. Lalu, pada tahun 2010, jumlah investasi AS sudah berkisar USD871 juta di luar migas. Sementara Indonesia juga menjadi penyerap 1,6% dari total investasi dari Eropa. Setidaknya ada sekitar 700 perusahaan dengan total investasi sekitar 50 miliar euro.
Kami tidaklah anti-asing, atau asal-asalan anti-modal asing, tetapi berusaha berfikir kritis terhadap dampak buruk modal asing terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional indonesia.
Fakta sudah menunjukkan bahwa keberadaan modal asing tidak membawa kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Ambil contoh: sejak tahun 1967 hingga sekarang kegiatan pertambangan Freeport di Papua sudah menghasilkan sedikitnya 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika diuangkan, maka jumlahnya mencapai ratusan ribu billion rupiah (itu beratus-ratus kali lipat dari jumlah APBN kita).
Tetapi, lihatlah kondisi rakyat di sana: kondisi infrastruktur masih buruk, rakyat hidup miskin, pengangguran dimana-mana, sekolah susah diakses, layanan kesehatan mahal, dan lain sebagainya. Ini juga nampak dari penjelasan Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, “rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa asing keluar”.
Tidak ada nsatupu imperialis di dunia ini yang menanam kapital dengan semangat peri-kemanusiaan dan semangat menolong antar-sesama. Sebab kapitalisme, seperti dikatakan Lenin dalam “Imperialisme: Tahap Tertinggi Kapitalisme”, baik perkembangan tidak rata maupun taraf hidup yang setengah kelaparan dari massa adalah syarat fundamental dan tak terelakkan dan dalil utama cara produksi yang itu. Tujuan mereka adalah untuk menggali keuntungan sebesar-besarnya untuk kemakmuran segelintir orang: pemilik kapital.
Ini sudah disinggung oleh Bung Hatta sejak 70-an tahun yang lalu. Dalam satu potongan artikelnya di buku “Beberapa Fasal Ekonomi”, Bung Hatta menulis sebagai berikut:
“Soal kapital menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di Indonesia. Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau berarti sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran rakyat (cetak miring sesuai aslinya), mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pemerintah. Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran.
Pedoman bagi mereka untuk melekatkan kapital mereka di Indonesia ialah keuntungan. Keuntungan yang diharapkan mestilah lebih dari pada yang biasa, barulah berani mereka melekatkan kapitalnya itu. Supaya keuntungan itu dapat tertanggung, maka dikehendakinya supaya dipilih macam industri yang bakal diadakan, dan jumlahnya tidak boleh banyak. Berhubung dengan keadaan, industri agraria dan tambang yang paling menarik hati kaum kapitalis asing itu.
Dan, dengan jalan itu, tidak tercapai industrialisasi bagi Indonesia, melainkan hanya mengadakan pabrik-pabrik baru menurut keperluan kapitalis luar negeri itu saja. Sebab itu, Industrialisasi Indonesia dengan kapital asing tidak dapat diharapkan. Apalagi mengingat besarnya resiko yang akan menimpa kapital yang akan dipakai itu. Industrialisasi dengan bantuan kapital asing hanya mungkin, apabila pemerintah ikut serta dengan aktif, dengan mengadakan rencana yang dapat menjamin keselamatan modal asing itu. (Hal. 141)
Selengkapnya...

Ho Chi Minh
Berikut ini adalah bahan kuliah Professor Sakurai Yumio, Department of Asian History, the University of Tokyo, tentang Ho Chin Minh, pahlawan revolusi sosialis di Vietnam. Artikel ini diterjemahkan oleh Tri Ramidjo pada 27 Juli 1988. Bung Tri mendengar langsung Prof Sakurai berbicara, dan kemudian mengetiknya.
——————————–
Kami memuat kembali bahan kuliah ini untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan sejarah. Semoga generasi-generasi sekarang bisa mengambil pelajaran penting dari gerakan ini.
———————-
Partai Komunis Viet Nam (PKV), yang sejak berdirinya sudah mempunyai sejarah selama 58 tahun, sampai sekarang ini belum pernah tercatat tentang adanya terrorisme di dalam Partainya sendiri, walaupun di Viet Nam terjadi terrorisme kekejaman Perancis. Partai Komunis Vietnam belum pernah menterror atau membunuh anggota Partainya sendiri.
Sejarah PKV ini berbeda dengan sejarah PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) dalam zamannya Stalin atau PKC (Partai Komunis Cina) dalam zaman revolusi kebudayaan.
Setiap tahun sebagian besar murid-murid Ho Chi Minh yang masih menjadi pemimpin-pemimpin tua selalu tidak pernah absen untuk ikut serta menghadiri peringatan ulang tahun kemerdekaan (2 SEPTEMBER 1945).
Tradisi seperti ini sudah dibuat sejak Ho Chi Minh. Semua orang Viet Nam mengetahui, bahwa Ho Chi Minh tidak suka melihat darah. Dengan membaca surat-surat dari Ho Chi Minh, kita akan mengerti bahwa Ho Chi Minh sangat keras membenci pelaksanaan kekerasan dan pembunuhan.
Tetapi perjuangan politik adalah perjuangan untuk merebut kekuasaan.
Dengan begitu, bagaimanapun juga, Ho Chi Minh tidak bisa terbebas dari Machiavelisme, seperti pada waktu orang-orang barat mengkritik atau mencela Ho Chi Minh tentang tindakannya (dan orang-orang barat sering mengutip) peristiwa pembunuhan atas Ta Thu Tau pada tahun 1945.
Ta Thu Tau adalah pemimpin Partai berhaluan Trotskisme di daerah selatan Vietnam antara tahun 1935 – 1939. Pada masa itu, partai ini (Partainya Ta Thu Tau) berada dalam keadaan lebih kuat daripada PKV pertama di Saigon .
Sejak Jepang menyerah kalah dalam perang pada bulan Agustus 1945 di daerah selatan Vietnam, kekuatan partai trotskisme ini hidup kembali dan berjuang bersama-sama dengan PKV. Pemimpin PKV di Saigon, Tran Van Giau, ingin menterror Ta Thu Tau. Tetapi Ho Chi Minh tidak memperbolehkan (tidak mengizinkan).
Akhirnya, Tran Van Giau mengirim surat laporan yang mengatakan, “kalau masih ada Ta Thu Tau, maka mungkin sekali PKV akan dikalahkan di selatan. Ho Chi Minh harus memilih antara dua pilihan untuk memimpin revolusi di selatan: memilih Ta Thu Tau atau Tran Van Giau. Ho Chi Minh terpaksa memberikan izin untuk menangkap dan mengeksekusi Ta Thu Tau pada bulan September tahun 1945.
Pada bulan Juli tahun 1946, ketika Ho Chi Minh berkunjung ke Perancis untuk menghadiri konferensi tentang kemerdekaan Vietnam, seorang wartawan terkenal bernama Daniel Gueren mengkritik tentang eksekusi Ta Thu Tau.
Kemudian Daniel Gueren menulis dalam artikelnya bagaimana Ho Chi Minh dengan mimik dan perasaan yang jujur menjelaskan kejadian yang sesungguhnya: “Ta Thu Tau adalah seorang nasionalis yang besar, Saya tahu. Saya menangis untuknya.”
Tetapi kemudian Ho Chi Minh mengatakan dengan tegas : “Tetapi kalau ada orang yang tidak mau mengikuti jejak saya, saya harus mengganyangnya”.
Semua orang barat yang mengkritik Ho Chi Minh kemudian menyimpulkan, bahwa Ho Chi Minh mempunyai perasaan yang halus dan baik untuk orang lain dan juga mempunyai ketegasan.
Tetapi, saya kira tidak ada seorang pun orang Vietnam yang menghendaki atau menginginkan pemimpin mereka, Ho Chi Minh, untuk menangis. Karena, bagi orang Vietnam, Ho Chi Minh dianggap sebagai ayah-ibu atau orang tua mereka.
Seperti apa yang ditulis oleh Truong Nhu Tan “orang kapal” (pengungsi Vietnam) dan apa yang dikatakan oleh pengarang buku “Vietnam Memoir”: “Kalau Ho Chi Minh masih hidup, tidak akan ada Orang Kapal atau Pengungsi Vietnam”.
Apa yang dikatakan Truonh Nhu Tan ini seperti kata-kata seorang anak yang telah kehilangan Ayah-Ibunya. Karakter pemimpin Ho Chi Minh ini adalah seperti perasaan hati orang tua terhadap anaknya. Tetapi perasaan-hati orang tua seperti Ho Chi Minh ini bukanlah perasaan orang tua yang mencintai bangsa Asia saja, tetapi mencintai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ho Chi Minh banyak menulis surat kepada orang-orang Vietnam , orang barat dan banyak lagi yang lain.
Diantara surat-suratnya yang sangat menarik adalah suratnya tanggal 23 November 1946.Ketika itu tentara Perancis sedang menghujani bom pelabuhan kota Hai Phong. Sepuluh ribu orang menjadi korban pengeboman itu dan semuanya adalah orang Vietnam.
Ketika itulah Ho Chi Minh menulis surat kepada saudara-saudaranya orang Vietnam dan saudara-saudaranya orang Perancis serta saudara-sadaranya orang-orang di seluruh dunia. Isi surat itu antara lain :
“Seluruh Rakyat Vietnam bertekad untuk mematuhi seruan Pemerintah Vietnam dan bersama-sama dengan Rakyat Perancis untuk menciptakan perdamaian. Sekarang ini saya menerima laporan dari pasukan Vietnam, bahwa dengan adanya peperangan antara dua negeri banyak darah tertumpah di Hai Phong. Hal ini disebabkan karena sebagian kecil orang Perancis salah mengerti (salah pengertian) mengenai perasaan-hati orang Vietnam dan mengira bahwa orang Vietnam tidak mau mentaati orang Perancis. Saya kira dengan perasaan dan semangat yang dicetuskan oleh revolusi Perancis, darah orang Perancis dan orang Vietnam adalah sama-sama merahnya. Orang Perancis dan orang Vietnam adalah sama-sama manusia.
Letak tanah Perancis adalah sangat jauh dari Vietnam berpuluh-puluh-ribu kilometer jaraknya. Vietnam yang merdeka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Perancis yang begitu jauh.
Kenapa (mengapa) orang Perancis mau menghancurkan kemerdekaan dan persatuan Vietnam? Orang Vietnam akan menerima dengan senang hati kedatangan orang Perancis di bumi Vietnam dan bekerja di Vietnam.
Pemerintah Vietnam akan melindungi orang Perancis di Vietnam, melindungi keuntungannya, melindungi harta bendanya dan melindungi kebudayaannya.
Jadi pemerintah Perancis harus mengakui pemerintah Vietnam .
Pemerintah Vietnam dan Rakyat Vietnam berjanji kepada Rakyat Perancis.
Saya sebagai pemimpin pemerintahan Vietnam sekarang memerintahkan kepada seluruh Rakyat Vietnam untuk tidak memerangi Rakyat Perancis dan karena itu juga Rakyat Perancis janganlah hendaknya memerangi Rakyat Vietnam .
Sekarang tanah air Vietnam menjadi merah karena mengalirnya darah Rakyat Vietnam dan Rakyat Perancis. Saya tidak ingin menjadi lebih memerah lagi.
Kenapa darah pemuda-pemuda Perancis harus memerahi tanah-tanah, gunung-gunung dan sungai-sungai di Vietnam?
Seluruh pemuda mempunyai hari-depan. Pemuda-pemuda Perancis dan pemuda-pemuda Vietnam bisa bergandengan tangan dan harus erat berjabatan tangan. Seluruh pemuda kedua bangsa ini harus menciptakan kebahagiaan untuk kedua bangsa. Saya dan seluruh Rakyat Vietnam menginginkan itu.
Saya ingin seluruh Rakyat Perancis dan Rakyat-Rakyat seluruh dunia mau mengerti isi-hati Rakyat Vietnam.”
- – - – - – - – - – - – -
Ketika Ho Chi Minh menulis surat itu, banyak Rakyat Vietnam yang mati.
Saya kira, Stalin– juga Mao Tse Tung dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya, tidak akan bisa menulis surat seperti itu. Surat tersebut adalah seperti surat seorang ayah-dunia yang ditujukan kepada anak-anak dunia.
Saya kira surat seperti ini hanya bisa ditulis oleh orang-orang angkatan (generasi) duapuluhan.
Seperti juga Nehru yang tinggal di Inggris, Ho Chi Minh tinggal di Perancis antara tahun-tahun 1917 – 1924.
Kawan lama Ho Chi Minh pernah menulis pada waktu itu, bahwa Ho Chi Minh banyak membaca buku-buku tulisan Tolstoy, Anatole France, Emile Zola, Roman Rolland dan lain-lain serta bergaul dengan orang-orang yang beraliran anarkis.
Biasanya orang-orang dari negeri barat sering membandingkan Ho Chi Minh dengan pemimpin India, Mahatma Gandhi. Kedua pemimpin itu isi surat-suratnya hampir sama.
Tentu saja angkatan (generasi) Ho Chi Minh dengan angkatan (generasi) Gandhi tidak sama.
Ho Chi Minh lahir pada tahun 1890, sedangkan Gandhi dilahirkan pada tahun 1869. Dan Gandhi adalah anak keturunan aristokrat dan bahkan sudah menjadi Sarjana Hukum pada usia dua-puluh-tahun di Inggris. Sementara Ho Chi Minh harus bekerja keras sebagai jongos (kelasi-kapal) pada tahun-tahun 1920–1923.
Sekalipun kedua orang itu mempunyai perbedaan yang besar, tetapi potret keduanya ketika tinggal di negeri barat sangat mirip. Walaupun keduanya (kedua orang itu) berpakaian cara barat, tetapi mereka bersikap ketimuran dalam potretnya. Mereka ingin menjadi seperti orang barat, tetapi tidak bisa.
(Contoh: Orang barat dalam potretnya menunjukkan kegagahannya dan menyombongkan diri, tetapi Ho Chi Minh atau Gandhi dalam potretnya walaupun berpakaian barat tidak kelihatan kegagahan dan kesombongannya. Seperti orang Jawa sikapnya selalu “ngapurancang”.)
Waktu Gandhi mempelajari ilmu hukum di Inggris, beliau pertama-tama menjadi sadar dan mengetahui bahwa kebudayaan India adalah kebudayaan yang baik.
Ho Chi Minh juga demikian dan pernah menulis sebagai berikut : “Perancis ingin membuat Rakyat Vietnam menjadi manusia-manusia yang tidak berpendirian (tidak berkepribadian)–tidak menjadi orang Perancis dan tidak menjadi orang Vietnam. Semua orang tentu tidak ingin menjadi begitu. Anda harus memilih menjadi orang Vietnam atau menjadi orang Perancis.”
Saya kira Gandhi dan Ho Chi Minh sudah cukup mengetahui betapa baiknya kebudayaan barat. Jadi mereka juga cukup mengenal dan mengetahui tentang kebaikan (betapa bagusnya) kebudayaan bangsanya sendiri.
Waktu saya tinggal di Perancis, teman saya di Perancis memperkenalkan kepada saya lima buah dokumen tentang mahasiswa Vietnam di zaman yang lalu.
Lima dokumen itu masih tersimpan baik di Pusat Arsip Nasional Perancis. Dan lima dokumen itu adalah dokumen tahun 1911.
Seorang pemuda namanya Nguyen Tat Tanh mengirimkan sepucuk surat kepada Presiden Perancis waktu itu yang isinya minta izin untuk belajar di sekolah Pamong-Praja (sekolah yang mendidik untuk bisa menjadi pegawai pemerintah kolonial Perancis) dan pemuda itu minta untuk bisa mendapatkan bea-siswa (scholarship).
Tetapi Presiden Perancis ketika itu menolak permohonan pemuda itu, karena tidak ada rekomendasi dari pemerintah kolonial Indo-China-Perancis. Dari dokumen ini nyatalah, bahwa pemuda Nguyen Tat Tanh berkeinginan untuk menjadi pamong-praja. (pegawai pemerintah kolonial Perancis),
Nguyen Tat Tanh adalah nama asli Ho Chi Minh.
Alamat Nguyen Tat Tanh dalam suratnya itu adalah nama kapal TELEVILLE,
Dalam otobiografinya Ho Chi Minh dalam tahun-tahun itu menyebutkan, bahwa beliau bekerja di kapal itu. Jadi Nguyen Tat Tanh tidak dapat disangsikan lagi adalah Ho Chi Minh.
Kalau pada waktu Ho Chi Minh ingin menjadi pegawai pamong-praja, hal itu sangatlah wajar.
Karena pemuda miskin Vietnam pada waktu itu ingin belajar pengetahuan Perancis dan itu adalah hanya jalan satu-satunya.
Otobiografi Ho Chi Minh yang ditulis resmi oleh PKV juga menyatakan bahwa kepergian Ho Chi Minh ke luar negeri adalah untuk mempelajari kebenaran dan kebijaksanaan. Saya kira, bagi Ho Chi Minh, kebenaran dan kebijaksanaan itu adalah kebudayaan Perancis.
Sejak pemerintah kolonial Perancis menolak suratnya, Ho Chi Minh terpaksa harus bekerja sebagai jongos-kelasi-kapal, sebagai kuli pembersih salju di musim dingin dan juga sebagai pelukis potret (melukis dan mentusir foto-foto).
Kadang-kadang Ho Chi Minh tidak bisa mendapatkan makanan untuk dimakan karena tidak mempunyai uang dan terpaksa tidur dipinggir-pinggir jalan. Tetapi surat-surat Ho Chi Minh pada waktu itu tidak pernah mencela atau mengkritik tindakan pemerintah Perancis.
Misalnya, dalam salah satu suratnya yang ditulis pada tahun 1914, yang ditujukan kepada seorang nasionalis terkenal Vietnam, Ho Chi Minh menulis dan menyatakan dalam suratnya itu bahwa beliau (Ho Chi Minh) ingin belajar bahasa Perancis dan bahasa Inggris saja.
Tetapi Ho Chi Minh mungkin belajar dari masyarakat miskin Perancis.
Pertama : bahwa di Perancis juga ada klas-kaum-miskin. Klas miskin Perancis itu sendiri bisa menjadi kawan sejati Rakyat Vietnam .
Ini adalah sosialisme – internasional Ho Chi Minh.
Kedua : Ho Chi Minh berfikir, karena kejujuran orang menjadi miskin. Jadi sampai akhir hidupnya (sampai meninggal), Ho Chi Minh tidak suka kemewahan. Sampai akhir hidupnya Ho Chi Minh hanya memiliki (mempunyai) dua helai pakaian terbuat dari katun.
Sekarang ini di Vietnam banyak terdapat buku-buku sejarah untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Sebagian besar isi buku sejarah itu adalah sejarah tentang kemiskinan Ho Chi Minh. Tentang kepahlawanannya hanya ditulis sedikit saja.
Kalau membaca sejarah itu, saya bisa mengerti bahwa Ho Chi Minh menentang kemewahan. Beliau bersikap seperti pendeta, pastor atau biksu.
Pada tahun 1945, sesudah Vietnam merdeka, di negeri itu tidak ada makanan, karena makanan yang ada sudah dihabiskan oleh tentara Jepang.
Ho Chi Minh, yang baru saja menjadi Presiden, menyerukan kepada seluruh Rakyat Vietnam: “Saudara-saudara, sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun ini, sudah 2,000,000 (dua juta) Rakyat Vietnam yang meninggal akibat kelaparan karena tidak ada makanan. Sekarang ini negeri kita dilanda air-bah (banjir) dan keadaan kekurangan makanan bertambah buruk. Waktu saya akan mengangkat piring nasi untuk makan, saya teringat kepada Rakyat yang kelaparan dan saya tidak bisa makan.
Jadi, saya ingin supaya orang-orang yang masih bisa makan setiap harinya, dalam sepuluh hari satu kali ( 10 hari sekali) mau memyisihkan bagian satu kali makan untuk diberikan kepada Rakyat (orang-orang) yang miskin, yang tidak bisa mendapatkan makanan. Saya juga akan melakukan hal itu. Dengan begitu orang yang miskin bisa melanjutkan hidupnya sampai musim panen nanti”.
Saya kira, hanya orang yang pernah merasakan lapar saja yang bisa membuat (membikin) seruan seperti ini. Saya belum pernah melihat pemimpin-pemimpin dunia yang lain yang menyerukan kepada Rakyatnya seruan seperti ini.
Kalau pun ada, mungkin hanya dua orang saja, yaitu Tolstoy dan Gandhi.
Bersambung->
Selengkapnya...
Mimpi Negara Kesejahteraan
DPR sudah mensahkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Bagi sebagian orang, pengesahan UU BPS itu merupakan jalan untuk mewujudkan konsep ‘negara kesejahteraan’ sebagaimana digariskan founding father. Bahkan PDIP, partai yang selalu mengklaim suara wong cilik, menyebut pengesahan BPJS sebagai kemenangan rakyat Indonesia.
Lebih jauh lagi, ada yang menganggap pengesahan UU BPJS sebagai penerapan semangat Pancasila (sila ke-5) dan UUD 1945. Mereka bahkan begitu berani menyimpulkan bahwa semangat BPJS itu selaras dengan cita-cita pendiri bangsa (founding father) tentang negara kesejahteraan (welfare state).
Di sini muncul sejumlah pertanyaan: Apakah benar cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan? Apakah mungkin negara kesejahteraan bisa diterapkan di tengah negara seperti Indonesia yang menganut neoliberalisme?
Kami kira, istilah “sosio-demokrasi” yang diperkenalkan oleh Bung Karno tidak bisa dipersamakan dengan “sosial-demokrasi” sebagaimana dianut sejumlah partai beraliran kiri-tengah di eropa. Sosio-demokrasi ala Soekarno adalah antisipasi terhadap kegagalan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, yang hanya mengejar kebebasan politik tetapi mengabaikan demokrasi ekonomi. Sementara sosio-demokrasi di barat, khususnya yang dibangun oleh Eduard Bernstein di akhir abad-kesembilan belas di Jerman, merupakan antisipasi terhadap kapitalisme dan juga sosialisme.
Sementara Soekarno berbicara bahwa hari depan masyarakat adil dan makmur adalah masyarakat sosialisme Indonesia, sedangkan sosio-demokrasi di eropa semakin bergerak menjauhi politik radikal dan semakin berorientasi sangat tengah (kanan). Soekarno berbicara tentang masa depan Indonesia dimana tidak ada lagi imperialisme dan kapitalisme, sedangkan sosio-demokrasi semakin mengadaftasikan diri untuk menambal-sulam kapitalisme.
Dan, menurut kami, masa depan masyarakat Indonesia sebagaimana digariskan founding father adalah masyarakat adil dan makmur. Adil dan makmur jelas berbeda dengan negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan, pencapaian masyarakat adil dan makmur belum tentu terjadi. Dalam banyak kasus, negara kesejahteraan hanya mencoba mencampurkan antara kapitalisme dan peran negara (mixed economy). Menurut kami, masyarakat adil dan makmur hanya mungkin terwujud dalam masyarakat sosialis.
Partai-partai sosial-demokrasi di Eropa berhasil meraih sedikit kemajuan terkait konsep negara kesejahteraan hanya pada periode booming ekonomi tahun 1950-an dan 1960-an. Pada saat itu, terjadi ekspansi ekonomi luar biasa dalam ekonomi dunia, belanja negara besar-besaran, dan peningkatan upah pekerja.
Pada saat itu, pengeluaran negara telah menjadi faktor kunci untuk mendorong permintaan. Di hampir seluruh negara kapitalis maju, belanja negara cukup tinggi, yakni rata-rata 28% dari PDB pada tahun 1950an dan meningkat 41% menjelang 1970an. Tingkat pengangguran juga sangat rendah pada saat itu. Sementara kenaikan upah real dalam kurun waktu tahun 1946-1976 (30 tahun) adalah 280 % (4.5 %/tahun).
Akan tetapi, ketika kapitalisme memasuki periode stagnasi pada tahun 1970-an, negara kesejahteraan di eropa satu per satu diutak-atik. Tidak sedikit partai berhaluan sosial-demokrat yang menjadi pendukung neoliberal.
Lenin, dalam karyanya “Imperialisme, Tahap Tertinggi Kapitalisme”, menguraikan bagaiamana negara-negara imperialis bisa menyogok lapisan tertentu dari klas pekerjanya karena keberhasilan mereka menarik laba besar dari negara-negara yang dijajah.
Nah, bagaimana dengan Indonesia yang merupakan negara jajahan? Periode panjang kolonialisme tidak menyediakan basis untuk perkembangan internal ekonomi nasional Indonesia. Sebagian besar surplus ekonomi mengalir atau diangkut ke negeri-negeri imperialis. Bahkan, ketika Indonesia dipaksa mengadopsi neoliberalisme, sebagian besar industri telah gulung tikar, pengangguran bertambah luas dan sektor informal membengkak.
Dengan kondisi begitu, penarikan iuran jaminan sosial hanya akan menjadi beban tambahan bagi rakyat. Ini sama saja dengan memeras orang yang sudah miskin, sehingga mereka akan menjadi semakin miskin.
Justru adanya kewajiban “iuran” ini adalah pelanggaran terhadap UUD 1945. Sebab, dalam UUD 1945, negara diwajibkan untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain). Sementara sistim “iuran” ini bermakna pelemparan tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab “setiap orang/individu”. “Setiap orang”-lah yang membayar dan memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan negara.
Belum lagi, jika dana jaminan sosial itu bisa diperdagangkan di bursa saham, maka semakin rentanlah rakyat miskin ini menjadi objek pemerasan oleh swasta atas nama jaminan sosial.
Sementara itu, negara sendiri belum tentu punya sumber daya yang cukup. Mengingat bahwa sebagian besar sumber daya dan potensi ekonomi nasional masih dikuasai oleh pihak asing. Sehingga, yang paling mendesak adalah perjuangan melikuidasi ekonomi kolonial dan menjalankan semangat pasal 33 UUD 1945 terlebih dahulu. Hanya setelah itu bisa dikerjakan, maka negara punya kemampuan untuk menjalankan “sistim jaminan sosial yang sebenarnya”.
Selengkapnya...
Search
Pengunjung
Kategori
- Berdikari (14)
- Internasional (4)
- Kabar Juang (3)
- Kabar Rakyat (4)
- Organisasi (1)
- Politik (8)
- sastra (1)
- Soekarnoisme (6)
- Statement (5)
- Tokoh (4)
Jaringan
Mengenai Saya
- Randy Syahrizal
- mempunyai minat menulis sejak kuliah di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra USU tahun 2003. Pernah menulis di beberapa media lokal (Sumatera Utara) dan Media Online Nasional. Blog pribadi saya : http://ceritadarimedan.blogspot.com
Followers
Blog Archive
-
▼
2011
(24)
-
▼
November
(8)
- Memajukan Gerakan Pasal 33 UUD 1945 dalam Memimpin...
- Puluhan Aktivis Serukan Gerakan Pasal 33 Di Samarinda
- Amandemen UUD 1945 Harus Melalui Referendum!
- Nasionalisme Kita dan Persoalan Papua
- Mana Cetak BIru Industrialisasi Nasional Kita ?
- Kenapa Modal Asing di Persoalkan..?
- Ho Chi MinhBerikut ini adalah bahan kuliah Profess...
- Mimpi Negara Kesejahteraan
-
▼
November
(8)