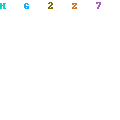Sebuah ide dari guyonan, bahkan cenderung gila, bisa menjadi masuk akal di tengah kebuntuan. Begitulah ide ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengenai “kebun koruptor” tampak masuk akal. Ia bisa menjadi ide cemerlang di tengah kefrustasian akan keadaan.
Korupsi memang satu soal besar di negara kita. Bahkan, begitu tidak berdayanya pemerintah, juga lembaga-lembaga anti-korupsi, dalam menghadapi perilaku korup membuat orang hampir putus-asa. Korupsi berjalan terus..dan terus!
Muncur pertanyaan: apakah ide membuat “kebun koruptor” bisa dipraktekkan dan seberapa efektif ide itu bisa mengurangi perilaku koruptif?
Ide “kebun koruptor” memang sangat mungkin dipraktekkan. Ide mempermalukan koruptor sendiri sudah banyak diusulkan; mulai dari usulan baju khusus untuk koruptor, penjara khusus untuk koruptor, dan lain sebagainya.
Di negara lain, khususnya Tiongkok, ide mempermalukan koruptor juga terkadang dipakai, disamping model hukuman yang keras: hukuman mati. Di sana, katanya, koruptor diborgol tangan dan kakinya, serta menjalani kerja paksa yang ditayangkan oleh televisi nasional.
Seberapa efektif ide mempermalukan koruptor di negara kita? Menurut kami, seorang koruptor adalah manusia yang sudah hilang rasa malunya. Mereka sanggup melakukan tindakan korupsi karena merasa tidak malu terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya. Bahkan, ketika seorang koruptor sudah menjalani penjara atau hukuman, ia tidak akan merasa malu ketika kembali ke masyarakat.
Hukuman berat juga belum tentu efektif di negara kita. Ini hanya soal memberi efek jera kepada koruptor dan calon koruptor. Difikirnya, dengan memberi efek jera seperti itu, orang akan berfikir dua kali untuk melakukan tindakan serupa.
Akan tetapi, bagi kami, hal semacam itu belum tentu efektif di Indonesia: negara yang sistim ekonomi dan politiknya sangat membuka celah bagi korupsi. Proses penegakan hukum di Indonesia juga sangat gampang “terbeli”. Jadi, metode mempermalukan dan menghukum berat koruptor belum tentu efektif.
Justru, bagi kami, pemberantasan korupsi di Indonesia mesti juga bersifat sistemik. Artinya, gerakan memberantas korupsi harus melekat dengan perjuangan untuk mengubah sistim ekonomi dan politik yang korup ini. Selama ekonomi nasional kita belum produktif, maka korupsi sebagai penyakit tentu akan terus-menerus tumbuh dan berkembang.
Sistim politik kita juga sangat rentan dengan korupsi. Selain terlalu birokratis, sistim politik kita juga sangat jauh dari kontrol dan partisipasi rakyat. Sistim politik kita memungkinkan kontrol terhadap sumber daya dan kekayaan publik tersentralisasi di tangan segelintir elit/pejabat politik. Hal itu menyebabkan jabatan politik menjadi ‘surga abadi” bagi para koruptor.
Untuk itu, jika hendak memerangi korupsi, maka sistim ekonomi dan politik ini perlu dirombak total. Ekonomi nasional yang tidak produktif, karena dikangkangi oleh imperialisme dan segelintir swasta nasional, menyebabkan konsentrasi kekayaan ke tangan segelintir orang. Ekonomi nasional yang tidak produktif ini juga tidak menyediakan basis akumulasi yang produktif pula.
Selain itu, sistim kapitalisme juga mengajarkan korupsi secara inheren: kapitalisme adalah sistim yang tumbuh karena pencurian nilai lebih, karena perampasan hasil kerja dan keringat manusia yang bekerja, dan perampasan kemakmuran bangsa lain. Kapitalisme juga mengajarkan fetitisme terhadap uang dan kekayaan.
Karena itu, bagi kami, hanya dengan menghapuskan imperialisme dan kapitalismelah yang membuka jalan untuk pemberantasan korupsi yang sejati. Dan, hanya dengan kekuasaan politik yang ditransfer ke rakyatlah yang membuat sistim politik makin sehat dan menjauh dari praktek korupsi.
Kalau proses politik dikontrol dan dijalankan langsung oleh rakyat, termasuk perumusan kebijakan dan penentuan alokasi sumber daya, maka korupsi bisa dikurangi hingga tingkat yang paling rendah.
Selengkapnya...
Efektifkah Kebun Koruptor..?
Kita Butuh Pemimpin Penggerak Rakyat
Indonesia masa kini sedang krisis kepemimpinan. Pemimpin sekarang punya banyak kelemahan: terlalu mengalah kepada kepentingan asing, tidak sanggup menjaga kepentingan nasional, tidak mampu menggerakkan rakyat, dan kurang cakap dalam mengelola pemerintahan.
Dulu, pada tahun 1950, Herbert Feith, penulis buku “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962)”, membagi dua tipe pemimpin Indonesia: administrator (ahli pemerintahan) dan solidarity maker (pemimpin massa).
Kategori administrator adalah orang yang memiliki kemampuan hukum, teknis pemerintahan, dan kecakapan bahasa asing yang diperlukan untuk menjalankan negara modern. Sedangkan tipe solidarity maker adalah mereka yang memiliki keahlian menghimpun dan membakar gelora massa.
Kita akan membahas tipe kedua, yaitu solidarity maker. Feith sendiri kurang setuju dengan tipe solidarity-maker ini, karena dianggapnya hanya pandai memberikan harapan yang muluk tentang masa depan Indonesia, tapi tidak memiliki kecakapan untuk mewujudkannya. Tetapi, bagi kami, tipe pemimpin solidarity-maker justru sangat dibutuhkan dalam situasi seperti saat ini: kita terkotak-kotak dalam berbagai partai yang berorientasi sempit; rakyat kita teratomisasi menjadi individu tanpa orientasi kolektif; sementara kita terjajah oleh imperialisme.
Kita membutuhkan pemimpin yang bisa menggerakkan rakyat. Bagi Bung Karno, seorang pemimpin harus bisa menggerakkan rakyatnya untuk mencapai cita-cita nasional yang sudah dirumuskan. Ini semacam “leistar” yang menggerakkan rakyat menuju cita-cita masyarakat masa depan.
Bung Karno sendiri menyebut tiga syarat yang mesti dipunyai seorang pemimpin agar bisa menggerakkan rakyat: pertama, pemimpin harus bisa melukiskan cita-citanya kepada rakyat banyak. Kedua, pemimpin harus bisa membangunkan (menyakinkan) rakyat bahwa mereka mampu. Ketiga, setelah membangkitkan rasa mampu dari rakyat, seorang pemimpin harus mengetahui cara mengorganisir rakyat itu.
SBY sendiri masuk kategori pemimpin salon. Ia tidak punya kemampuan untuk menggerakkan massa rakyat. Banyak seruan-seruannya tidak diikuti oleh rakyat, bahkan terkadang dilawan oleh rakyat. Pasalnya, banyak seruan-seruan politiknya bertentangan dengan keinginan rakyat.
Jangankan pandai melukiskan cita-cita kepada rakyat banyak, SBY justru mengalah kepada kepentingan asing dan membiarkan cita-cita nasional kita tenggelam akibat amukan badai neoliberalisme. SBY pun gagal memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan seluruh rakyat.
Banyak seruan-seruan SBY juga bertolak-belakang antara ucapan dan tindakan. Sebagai contoh, ketika sedang berkampanye besar-besaran melawan korupsi, ia justru tidak punya itikad politik untuk mengusut kasus korupsi yang melibatkan anggota partai dan menteri di dalam kabinetnya.
Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Dulu, ketika Republik baru berdiri, rakyat Indonesia rela berkorban jiwa dan raga untuk memperjuangkan cita-cita itu. Sekarang, seiring dengan seringnya para pemimpin melupakan dan menghianati rakyatnya, rakyat pun seperti kehilangan asa dan harapan.
Dalam situasi sekarang ini, dimana penjajahan telah begitu menghisap bangsa kita, seorang pemimpin bertipe penggerak massa rakyat sangat diperlukan. Kita butuh seorang pemimpin yang pandai melukiskan cita-cita masa depan. Tetapi bukan cita-cita yang muluk-muluk, melainkan cita-cita yang lahir dari analisa dan tuntutan sejarah perkembangan masyarakat. Sejumlah bangsa di Amerika Latin, seperti Venezuela dan Bolivia, sedang merintis jalan cita-cita semacam itu. Lalu, kalau rakyat Bolivia dan Venezuela bisa melakukanya, kenapa kita tidak!
Selengkapnya...
Turunnya Produksi Padi Kita
Produksi padi Indonesia untuk tahun 2011 diperkirakan akan menurun. Menurut Biro Pusat Statistik, produksi padi berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) III diperkirakan turun hingga 1,63 persen atau 1,08 juta ton. Penurunan juga terjadi pada produksi jagung dan kedelai.
Merespon produksi padi yang jeblok itu, pemerintah justru menyalahkan petani. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa produktivitas padi rendah karena petani tidak bisa menggunakan teknologi. “Problemanya adalah ketidakmampuan melaksanakan anjuran teknologi di tingkat usaha tani,” kata Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Udhoro Kasih Anggoro, seperti dikutip TEMPO.
Persoalannya tidaklah sesederhana itu. Jika ditinjau dengan seksama, penyebab penurunan produksi padi banyak disebabkan oleh “kesalahan pemerintah”. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah justru banyak memproduksi kebijakan yang merugikan kaum tani, seperti kebijakan impor beras, pencabutan subsidi pertanian, dan lain-lain.
Impor pangan menyebabkan petani kehilangan akses pasar mereka. Lemahnya daya dukung pemerintah dalam urusan permodalan dan teknologi menyebabkan petani tidak bisa bersaing secara bebas dengan produk impor. Akibatnya, karena ketidakmampuan bersaing itu, petani banyak yang bertransformasi menjadi kaum urban.
Atas anjuran IMF dan Bank Dunia, pemerintah juga sangat intensif memangkas subsidi atau anggaran untuk pertanian. Pemerintah juga gagal untuk menjamin ketersediaan pupuk murah dan massal bagi petani. Dalam banyak kasus, pemerintah hanya pura-pura tuli ketika petani di berbagai daerah menjerit akibat kelangkaan atau mahalnya harga pupuk.
Petani juga tidak bisa mengakses modal. Pemerintah tidak punya skenario pembiayaan pertanian yang efektif. Di negara lain, khususnya Venezuela, pemerintah membangun bank khusus untuk pertanian. Bank inilah yang berfungsi untuk menyalurkan kredit mikro kepada seluruh petani.
Penurunan produksi pertanian juga berkaitan dengan menyusutnya jumlah lahan pertanian. Banyak lahan pertanian yang berpindah tangan ke swasta dan beralih-fungsi menjadi perkebunan sawit, kawasan bisnis, dan lain sebagainya. Sementara banyak lahan menganggur tidak bisa diproduktifkan oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak konsisten menjalankan reformasi agraria sebagaimana diamanatkan UUPA 1960. Padahal, belum ada negara di dunia yang sukses membangun pertanian dan tumbuh menjadi industrialis tanpa melampaui reforma agraria.
Infrastruktur pertanian juga sangat buruk. Sedikitnya 3,21 juta hektare, atau 45% dari total jaringan irigasi di Indonesia, mengalami kerusakan. Kerusakan irigasi ini berkontribusi pada menurunnya produksi pertanian. Sementara itu, masih banyak juga lahan pertanian di Indonesia yang belum tersentuh sistim irigasi yang baik.
Infrastruktur lainnya, seperti waduk dan bendungan, juga tidak memadai. Pemerintah SBY-Budiono hampir tidak bisa melakukan apa-apa terhadap infrastruktur ini. Bahkan banyak waduk yang mengalami pengeringan. Infrastruktur lain yang turut bermasalah adalah jalan desa. Banyak jalan desa yang mengalami kerusakan parah dan sama sekali tidak tersentuh oleh program rehabilitasi pemerintah. Padahal, jalan desa sangat membantu petani dalam proses distribusi hasil pertanian.
Meski sering gembar-gembor soal swasembada pangan, pemerintahan SBY-Budiono sendiri tidak punya program konkret untuk membangun pertanian. Sebaliknya, SBY-Budiono justru menyerahkan sektor pertanian di bawah tekuk neoliberalisme.
Selengkapnya...
Sejumlah Paradoks di Negeri Kita
Sejarah memang membentangkan paradoks kepada kita. Terkadang paradoks itu cukup menggelikan. Tetapi itulah kenyataan yang mesti kita hadapi dan langkahi untuk melangkah maju kepada masa depan yang lebih baik.
Paradoks pertama, yang baru saja diumumkan kemarin (28/11), adalah fakta bahwa Departemen Agama menjadi lembaga terkorup di Indonesia. Dari survey integritas yang diselenggarakan KPK, diketahui bahwa memiliki indeks integritas terendah, mencapai 5,37, disusul Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,44) dan Kementerian Koperasi dan Usahan Kecil dan Menengah (5,52).
Ini adalah paradoks: Lembaga yang paling banyak berhubungan dengan urusan moral justru ditempatkan sebagai lembaga terkorup. Ini sekaligus menjelaskan bahwa korupsi bukanlah sekedar urusan moral, tetapi sudah merupakan problem sistem. Kapitalisme, entah dengan wajah apapun, telah menjadi penyebab korupsi kian merajela.
Paradoks lainnya adalah soal pengelolaan kekayaan alam kita: kita punya garis pantai terpanjang di dunia, tetapi kita juga adalah pengimpor garam terbesar di dunia; kita memiliki lahan pertanian terluas di dunia, tetapi kita juga pengimpor produk-produk pangan terbesar di dunia; kita termasuk pengekspor gas dan batubara terbesar di dunia, tetapi PLN terus-menerus mengeluhkan kurangnya bahan bakar dan harus melakukan pemadaman bergilir untuk mengatasi persoalan ini.
Kita juga memiliki lahan sawit yang sangat luas dan menjadi eksportir CPO terbesar di dunia, tetapi sebagian besar rakyat kita terus menjerit karena kelangkaan atau kenaikan harga minyak goreng di pasaran.
Dulu, di tahun 1930-an, Indonesia pernah merajai produksi gula kristal putih di dunia. Saat itu Indonesia (Hindia-Belanda) punya 179 pabrik dan sanggup memproduksi tiga juta ton pertahun. Tetapi, pada tahun 2010, produksi gula nasional hanya 2,44 juta ton dan kita pun berubah menjadi negeri “pengimpor”.
Media luar negeri menyebut Indonesia sebagai “Blackberry nation”, tetapi di sini ada separuh dari total penduduk yang hidup dengan penghasilan di bawah 2 USD/hari. Pada tahun 2010, Jumlah kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan sekitar 15 juta keluarga atau 60 juta jiwa paling miskin penduduk.
Seorang Presiden bisa membiayai pernikahan anaknya sebesar 20 milyar, sedangkan kekayaan si Presiden hanya tercatat sebesar Rp 7,14 miliar ditambah US$ 44.887. Sementara pejabat negara bisa berpesta-pora dengan kekayaannya, anak-anak di pedalaman Kalimantan harus berjalan kaki puluhan kilometer karena keterbatasan jumlah sekolah dan buruknya infrastruktur jalan serta transportasi.
Masih banyak paradoks di negeri ini. Silahkan para pembaca menambahkan!
Selengkapnya...
Ambruknya Jembatan Mahakam
editorial
Jembatan kebanggaan rakyat Kutai Kartanegara itu pun ambruk. Hari itu, 26 November 2011, banyak orang dan kendaraan yang sedang melintas di atas jalan itu. Belum diketahui pasti berapa orang yang menjadi korban dari tragedi memilukan itu.
Fondasi jembatan Mahakam II selesai tahun 2000 dan mulai resmi beroperasi pada tahun 2002 lalu. Artinya, jembatan sepanjang 710 meter itu baru berumur kira-kira sepuluh tahun. Konon, jembatan ini didesain untuk 40 tahun, bahkan hingga 100 tahun. Entah mengapa, jembatan yang digelari “Golden Gate Kalimantan” itu terlalu cepat roboh.
Orang-orang pun mulai menduga-duga: ada yang salah dengan pembangunan dan proses perawatan jembatan itu. Jangan-jangan terjadi ketidaksesuaian antara bahan-bahan yang direncanakan dengan bahan yang dipergunakan. Motifnya: demi mendapatkan untung besar, maka pihak kontraktor menggunakan bahan yang lebih murah dan kurang bermutu. Bisa saja demikian!
Bisa pula, proses pembangunan jembatan ini sangat tergesa-gesa. Sehingga, beberapa aspek standar untuk memperkuat kualitas jembatan tak terpenuhi. Pemerintah pun tidak melakukan pengecekan secara teliti mengenai kesiapan jembatan itu. Akhirnya, karena ada faktor-faktor yang luput untuk terpenuhi, maka jembatan itu pun ambruk sebelum waktunya.
Mungkin juga ambruknya jembatan itu terkait pemeliharaan. Kesimpulan ini paling banyak diikuti oleh pejabat pemerintah di tingkatan pusat. Maklum, jika masalahnya memang pemeliharaan, maka pejabat dan petugas setempatlah yang “kena batunya”. Sementara pejabat berwenang di pusat bisa terhindar dari tanggung-jawab.
Akan tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri: ambruknya jembatan Mahakam II menyingkap buruknya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Banyak proyek pembangunan infrastruktur disandera oleh mafia anggaran dan mafia proyek. Tidak sedikit anggaran pembangunan yang sudah “tersunat” sejak awal ketika masih di bahas di DPR. Belum lagi ketika proyek itu ditenderkan, hingga proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor.
Tetapi hal-hal di atas hanya penyebab di permukaan saja. Ada penyebab yang lebih mendasar: semakin lunturnya semangat kebangsaan kita dan makin takluknya kita dihadapan kuasa keuntungan (profit). Orang tidak lagi membangun seperti membangun kebesaran dan kejayaan bangsanya. Orang-orang itu, umumnya kaum swasta, hanya membangun demi mendapatkan untung sebesar-besarnya. Dia tidak pernah berfikir tentang kepentingan nasional, apalagi kepentingan rakyat dan generasi di masa depan.
Lihatlah jembatan Ampera di atas sungai Musi, Sumatera Selatan. Kendati sudah berusia hampir 50 tahun, jembatan peninggalan pemerintahan Bung Karno itu masih terlihat kokoh berdiri dan sekaligus menjadi kebanggan nasional kita. Jembatan itu dibangun memang untuk menunjukkan kebanggaan nasional bangsa kita.
Menjadi benar apa yang dikatakan Bung Karno 50-an tahun lalu, bahwa soal membangun bukan sekedar kemajuan teknik dan keahlian, tetapi juga soal pembangunan mental manusia Indonesia itu sendiri. Pembangunan mental, atau sering disebut “mental invesment”, adalah dasar untuk memberi proyek pembangunan itu punya arah yang jelas: mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur di masa depan.
Sehingga, apapun yang hendak kita ciptakan dan hendak bangun, ia harus tahan lama dan tahan dalam segala keadaan. Apa yang kita ciptakan dan bangun mestilah berkontribusi untuk membuat rakyat Indonesia bisa lebih adil dan makmur. Dengan demikian, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan, bukan keuntungan demi kepentingan pribadi.
Selengkapnya...
Memajukan Gerakan Pasal 33 UUD 1945 dalam Memimpin Gerakan Pengembalian Kekayaan Alam
diambil dari rangkuman diskusi rutin KPW-PRD Sumatera Utara
Tahun-tahun sekarang ini adalah tahun kemenangan Neoliberalisme. Setelah sukses dalam konsolidasi besar meneguhkan kepemimpinan Neolin di Indonesia selama 2 periode, Neoliberalisme semakin mapan di Bumi Pertiwi. Hampir tidak ada lagi paket kebijakan Negara yang dapat menghempang jalan dan beroperasinya system ekonomi liberal. Negara yang dipimpin oleh Kabinet Neolib dengan sukses mencampakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bernegara, sebagai kepribadian Negara, sebagai moralitas Negara. Akhirnya, Neolib di Indonesia dengan sukses menempuh jalan tol dalam meng-goa-kan paket kebijakannya. Pemerintahan kita nyaris tidak punya proteksi dalam melindungi kekayaan alam yang dirampok di negerinya sendiri.
Kemenangan Neoliberal dan semakin matangnya laju neoliberalisme di Indonesia bias dilihat dalam kasus terbaru yang hamper setiap hari kita saksikan di TV, dan menyita waktu banyak orang di Indonesia dalam memperbincangkan kasus ini, yakni kasus kebrutalan PT Freeport.
Selama 44 tahun Freeport mengeksploitasi tambang emas dan tembaga di tanah Papua, pihak Indonesia mendapat 1% dan pihak Freeport (imperialis) mendapat 99%. Jadi, pihak yang diuntungkan dari situasi Papua saat ini adalah imperialis. Dahulu, rakyat Papua bebas mencari makan di tanahnya sendiri. Setelah kemerdekaan di interupsi oleh rezim ORBA, rakyat Papua tidak lagi merdeka mencari makan. Saat ini, Freeport yang tidak bermanfaat untuk rakyat Papua sudah leluasa menguasai aparatur Negara, terbukti dengan pengiriman pasukan TNI/Polri untuk menjaga kepentingan PT. Freeport di Papua. Ini bukanlah karena ekspresi nasionalisme Indonesia. Tetapi sebaliknya: hal itu dilakukan karena pemerintahan Indonesia sekarang adalah boneka imperialisme. TNI/Polri justru diperalat (dipergunakan) untuk menjaga kepentingan neo-kolonialisme di Papua.
Memang ada kemajuan dalam perlawanan gagasan jalan keluar krisis imperialisme, yakni dengan mengobarkan semangat kemandirian nasional. Paling tidak sentiment ini secara serentak dihembuskan oleh semua elemen-elemen yang anti Imperialisme. Sentimen tersebut kemudian meluas, dan tidak hanya menjadi perbincangan dikalangan aktivis saja, melainkan menjadi jualannya kaum brjuasi nasional di kancah Pemilu 2009 yang lalu.
Meski banyak gerakan Anti Imperialis bermunculan dengan menghembuskan irama yang serupa, namun masih belum menciptakan sebuah persatuan nasional yang kokoh, sebagai syarat untuk perimbangan kekuatan pro neolib. Padahal, fakta-fakta Indonesia menuju kebangkrutan sudah semakin nyata, diantaranya karena 1. Indonesia masih menjadi komoditas utama bahan mentah, yakni Batu Bara (70%), Minyak (50%), Gas (60%) dll. 2. Indonesia masih menjadi tempat penanaman modal asing, yakni hamper 70% Industri di Indonesia adalah modal asing, diantaranya Minyak dan Gas (80%), Perbankan (50%), Pelayaran (94%), Pendidikan (49%).Yang ketiga, Indonesia masih menjadi tempat pemasaran barang-barang hasil produksi Negara-negara maju. Dan terakhir Indonesia masih menjadi penyedia tenaga kerja murah.
Pasal 33 sebagai Alat Pemersatu dan Senjata Melawan Neolib
Didalam Pembukaan UUD 1945, Para pendiri Negara ini dengan tegas menuliskan tujuan-tujuan dan dasar-dasar kita bernegara, yakni untuk menghapuskan penindasan di muka Bumi, menciptakan perdamaian dan mensejahterakan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan Pasal 33 adalah perisai Negara dalam membentengi rakyat Indonesia dari pengaruh jahat neoliberalisme. Dasar Negara kita tidak lagi dijalankan oleh Kabinet kaki tangan Asing seperti saat sekarang ini, sehingga dasar Negara tersebut tidak berfungsi sebagai perisai rakyat dalam melawan kepentingan serakah asing.
Ada 3 semangat didalam Pasal 33 UUD 1945, yakni 1. Sosio ekonomi, yaitu Perekonomian disusun secara bersama dan untuk kesejahteraan bersama, 2. Sosio Nasional, yakni Penguasaan kekayaan Alam oleh Negara dan diselenggarakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 3. Sosio Kerakyatan, yakni usaha-usaha dalam membangun perekonomian rakyat dan menyejahterakan rakyat Indonesia.
Semangat tersebut tentu bertentangan dengan kepentingan Imperialisme ditanah air, yakni Penguasaan bahan baku melalui perampokan kekayaan alam, kedua penguasaan dan pelebaran pasar, dan ketiga yakni mendapatkan tenaga kerja murah. Jika pasal 33 UUD 1945 diterapkan oleh Rezim SBY-Budiono, mustahil Neoliberalisme mendapatkan pondasinya di negeri ini. Namun elit politik kita lupa pesan bung KArno, yakni “Biarkanlah kekayaan alam kita disini sampai Insinyur-Insinyur kita mampu mengelolanya.”
Pasal 33 mempunyai kekhususan tersendiri, yakni karena dia adalah bagian dari dasar Negara kita, dan kedudukannya sebagai UU adalah kedudukan tertinggi. Jadi perjuangan ditegakkannya Pasal 33 UUD 1945 adalah perjuangan konstitusional yang legal dan berkemampuan meluas.
Pasal 33 adalah antitesis dari kepentingan serakah asing didalam negeri. Pasal 33 adalah tembok raksasa dalam membendung keserakahan-keserakahan asing. Gerakan pasal 33 haruslah menjadi gerakan yang dapat mempersatukan semua kekuatan bangsa yang ingin melihat kemandirian bangsa Indonesia, yang tidak lagi ketergantungan kepada asing, dan yang mampu membuka lapangan kerja dengan penguasaan kekayaan alam oleh Negara. Pasal 33 UUD 1945 haruslah menjadi ruh dalam gerakan pengembalian kekayaan alam.
Selengkapnya...
Puluhan Aktivis Serukan Gerakan Pasal 33 Di Samarinda
Gerakan Pasal 33
Oleh : Niko
Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP-33) menggelar aksi di depan Mall Lembuswana, Samarinda. Mereka menyerukan perlawanan terhadap imperialisme, penegakan kembali pasal 33 UUD 1945, dan pelaksanaan reforma agraria.
Selain menggelar orasi secara bergantian, para aktivis mahasiswa ini membagi-bagikan selebaran kepada para pengguna jalan. “Imperialisme neoliberal hanya menghasilkan kemiskinan,” teriak seorang orator.
Menurut Parsauran Damanik, aktivis dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), setelah 66 tahun bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bangsa Indonesia semakin menjauh dari cita-cita masyarakat adil dan makmur.
“Kita sekarang murni menjadi negara jajahan. Indonesia hanya menjadi penyedia bahan baku bagi negeri imperialis, penyedia tenaga kerja murah, pasar bagi produk negeri imperialis, dan tempat penanaman modal asing,” ujarnya.
Salah satu bukti konkretnya lagi, kata Parsauran, bahwa upah pekerja di Indonesia adalah terendah di Asia. Bahkan upah pekerja Indonesia tiga hingga empat kali lebih rendah dibanding Malaysia.
Katanya, situasi itu kian diperparah dengan dipraktekkannya sistim kontrak dan outsourcing.
Untuk itu, dalam pernyataan sikapnya, Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP-33) Samarinda menuntut agar penyelenggara negara kembali kepada semangat dan filosofi pasal 33 UUD 1945.
Mereka juga menuntut agar pemerintah segera melaksanakan UU Pokok Agraria tahun 1960 sebagai turunan dari semangat pasal 33 UUD 1945. Lebih lanjut, gerakan ini juga mendesak pemerintah segera menasionalisasi asset-aset strategis dan kemudian diserahkan di bawah kontrol rakyat.
Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 Samarinda merupakan aliansi bersama antara Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Selengkapnya...
Amandemen UUD 1945 Harus Melalui Referendum!
Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah mengalami empat kali perubahan (amandemen). Sekonyong-konyong perubahan itu membongkar pula beberapa landasan dasar mengenai sistim politik dan ekonomi Indonesia. Amandemen itu juga merombak batang tubuh dan menghapus penjelasan UUD 1945.
Sejalan dengan proses amandemen itu, sistem politik Indonesia pun semakin mengarah pada model demokrasi liberal. Gedung parlemen itu kita hari dipenuhi dengan riuh-gaduh perdebatan anggota parlemen. Akan tetapi, hampir semua perdebatan itu tidak pernah berkaitan dengan persoalan rakyat.
Di bidang ekonomi, amandemen UUD 1945 telah membuka jalan untuk membongkar filisofi mendasar pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistim ekonomi Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen dibuat permisif terhadap kepemilikan swasta dan dominasi modal asing. Padahal, filosofi pasal 33 UUD 1945 sangatlah memerangi liberalisme dan anti-kapitalisme.
Boleh dikatakan, empat kali amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari proyek mengubah desain sistem ekonomi dan politik Indonesia, agar sejalan dengan tuntutan dan kepentingan imperialisme. Tidak salah kemudian jika Gus Dur, mantan Presiden RI, menyatakan penolakan keras terhadap UUD hasil perubahan. “perubahan UUD itu telah diselundupkan oleh lembaga-lembaga asing melalui para anggota MPR yang waktu itu dipimpin oleh Prof. Dr. Amin Rais,” kata almarhum Gus Dur.
Lebih parah lagi, empat kali proses amandemen itu tidak satupun yang meminta pendapat atau konsultasi dengan rakyat Indonesia. Padahal, di banyak negara, setiap perubahan terhadap satu pasal dala konstitusi mesti dilakukan melalui referendum. Juga dalam Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 dikatakan: “bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.”
Lalu, sekarang muncul lagi keinginan kuat dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendorong amandemen ke-V. Bahkan, demi mendapatkan kewenangan atas lembaganya, anggota DPD seperti ngotot memaksakan amandemen terhadap UUD 1945 tanpa konsultasi dengan rakyat.
Bung Karno memang mengatakan, “UUD ini bersifat sementara dan nanti kalau kita bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.”
Sekalipun begitu, bukan berarti bahwa amandemen terhadap UUD 1945 bisa dilakukan dengan serampangan dan seenaknya. Setiap proses amandemen mesti dikonsultasikan dengan rakyat Indonesia melalui referendum. Referendum itu tidak hanya menanyakan apakah rakyat setuju atau tidak terhadap amandemen, tetapi sampai pada memperdebatkan usulan perubahan.
Karena, menurut kami, UUD 1945 boleh saja mengalami perubahan, tetapi ada beberapa filosofi atau bangunan dasar yang tidak boleh berubah: anti-kolonialisme, anti-liberalisme, dan selalu menomor-satukan kepentingan rakyat banyak. Perubahan UUD 1945 tidak boleh bertolak belakang dengan cita-cita revolusi agustus 1945.
Itulah mengapa, bagi kami, empat kali amandemen UUD 1945 sebelumnya dan rencana amandemen oleh DPD sangat bertolak-belakang dengan semangat anti-kolonalisme, anti-liberalisme, dan kepentingan rakyat banyak itu. Amandemen itu hanya merupakan upaya lebih lanjut untuk merestrukturisasi sistim politik dan ekonomi Indonesia agar semakin gampang menampung kepentingan asing.
Selengkapnya...
Nasionalisme Kita dan Persoalan Papua
“Saya seorang nasionalisme, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan”. Kata-kata itu diucapkan oleh Bung Karno saat menyampaikan pidato di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945–sering disebut hari lahirnya Pancasila. Pidato itu memberi gambaran cukup jelas mengenai corak nasionalisme seperti apa yang hendak dibangun bangsa Indonesia.
Orde baru-lah yang bertanggung-jawab atas penyempitan makna kebangsaan Indonesia itu menjadi sangat chauvinis. Di masa itulah proyek nasionalisme Indonesia dihancur-leburkan dan kemudian dijadikan pembenaran untuk menghancurkan protes atas ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan.
Jika anda baca tulisan-tulisan Bung Karno, juga founding father yang lain seperti Hatta dan Tan Malaka, nasionalisme Indonesia dirumuskan sangat anti terhadap segala bentuk penjajahan, bahkan anti terhadap kapitalisme.
Bung Karno menyebut corak nasionalisme Indonesia sebagai sosio-nasionalisme, yaitu nasionalisme yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (massa rakyat) dan menghapus kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. “sosio-nasionalisme adalah nasionalismenya kaum marhaen, dan menolak tiap tindak borjuisme yang menjadi sebab kepincangan itu,” tulis Soekarno dalam “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi”.
Hatta juga punya pandangan yang serupa dengan Bung Karno. Kata bung Hatta, kebangsaan kita bukan kebangsaan ningrat dan bukan kebangsaan kaum intelek, melainkan kebangsaan rakyat. Karena, bagi Hatta, “rakyat itu adalah badan dan jiwa suatu bangsa.”
Dengan demikian, melihat nasionalisme Indonesia tidak bisa dengan mempersamakannya dengan trend nasionalisme di barat. Nasionalisme Indonesia sejak dalam kandungan para penggagasnya sudah berkarakter progressif: anti-kolonialisme, anti-imperialisme, menghargai demokrasi, dan menghubungkan diri dengan internasionalisme.
Akan tetapi, ketika orde baru berkuasa, nasionalisme seolah seperti ditawan sehingga tidak bisa menentang masuknya kembali pengaruh neo-kolonialisme. Yang terjadi justru sebaliknya: orde baru hanya mengatasnamakan nasionalisme untuk membenarkan tindakannya menghancurkan protes dan kritik terkait ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan. Orde barulah yang menghancurkan bangunan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri bangsa itu.
Dengan melihat fikiran para founding father itu, kami pun menyatakan ketidaksetujuan dengan anggapan banyak orang bahwa persoalan kekerasan di papua adalah ekspresi dari superioritas kebangsaan atau nasionalisme Indonesia. Saya rasa pendapat itu sangat keliru dan sangat salah kaprah dalam melihat sejarah nasionalisme Indonesia itu.
Yang terjadi di Papua itu adalah proses rekolonialisme dan itu berjalan beriringan dengan proses rekolonialisme di Indonesia. Orde barulah yang pelaksana proyek kolonialisme di Indonesia. Dan, orde baru pula yang menjadi penjaga kepentingan neokolonialisme di Indonesia.
Jadi, pengiriman pasukan TNI/Polri untuk menjaga kepentingan PT. Freeport di Papua bukanlah karena ekspresi nasionalisme Indonesia. Tetapi sebaliknya: hal itu dilakukan karena pemerintahan Indonesia sekarang adalah boneka imperialisme. TNI/Polri justru diperalat (dipergunakan) untuk menjaga kepentingan neo-kolonialisme di Papua.
Lagi pula, selama 44 tahun Freeport mengeksploitasi tambang emas dan tembaga di tanah Papua, pihak Indonesia mendapat 1% dan pihak Freeport (imperialis) mendapat 99%. Jadi, pihak yang diuntungkan dari situasi Papua saat ini adalah imperialis.
Kesalahan cara pandang soal ini bisa berakibat fatal: ini akan menjadi pintu masuk bagi imperialisme untuk memisahkan atau menjauhkan dukungan rakyat (nation) Indonesia terhadap perjuangan rakyat Papua.
Selengkapnya...
Mana Cetak BIru Industrialisasi Nasional Kita ?
Sudah 66 tahun proklamasi kemerdekaan, sebagian besar barang-barang kebutuhan rakyat Indonesia masih diperoleh melalui impor. Lebih ironis lagi, bukan cuma barang-barang yang menggunakan teknologi tinggi yang diimpor, tetapi hasil bumi seperti garam dan kedele pun sekarang sudah diimpor.
Inilah yang mengkhawatirkan kita: bukan cuma gagal membangun industri, tetapi membangun pertanian pun tidak bisa. Padahal, pembangunan sektor pertanian mestinya menjadi dasar untuk membangun masa depan industri nasional kita. Itu sudah difikirkan oleh para pendiri bangsa sejak Indonesia masih dalam gagasan mereka.
Sejak jaman kolonial hingga sekarang, Indonesia harus berpuas sebagai “negara pengekspor bahan mentah”. Sektor industri tidak pernah berkembang dan tidak pernah sanggup mengatasi ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk impor. Bahkan, sejak neoliberalisme kian massif di Indonesia, Industri manufaktur yang sudah “setengah-nafas” itu pun kian hancur.
Menurut ekonom dari Econit, Hendri Saparini, sampai sekarang ini Indonesia belum punya cetak biru industri nasional yang mengaitkan semua sektor untuk mendukung industri yang akan dikembangkan. Justru sebaliknya yang terjadi: pemerintah yang bermental inlander ini cukup puas menjadi pengekspor bahan mentah. Padahal, basis industrialisasi nasional kita adalah industri yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam kita.
Situasinya kian parah saat ini: kita seperti bangsa tanpa haluan. Pembangunan ekonomi tidak jelas mau mengarah kemana. Sementara pemerintah lebih doyan mengikut pada jalan ekonomi yang sudah didiktekan oleh Washington Consensus. Kehancuran ekonomi pun nampak jelas di depan mata: industri nasional gulung tikar, sektor pertanian babak belur, pasar dalam negeri dikuasai produk asing, dan lain sebagainya.
Malahan, di tengah-tengah kehancuran industri nasional itu, pemerintah tiba-tiba berbicara soal industri kreatif sebagai salah satu soko-guru perekonomian nasional. Bahkan, seusai reshuffle kabinet baru-baru ini, dibentuk kementerian khusus untuk menangani industri kreatif ini.
Tanpa mengabaikan arti penting industri kreatif bagi ekonomi nasional, tetapi gembar-gembor soal pengembangan sektor ini justru seolah hendak menutupi kegagalan membangun pertanian dan industri.
Padahal, kegagalan proyek Industrialisasi ini berkonsekuensi serius di Indonesia: meluasnya pengangguran, ketergantungan pada impor, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, kegagalan proyek industrialisasi juga membuat bangsa Indonesia makin kehilangan keterampilan, pengetahuan, kreatifitas, dan lain-lain. Kita seolah merasa cukup sebagai bangsa konsumen.
Kami justru melihat bahwa kegagalan proyek industrialisasi berkait erat dengan masih berlangsung proyek penjajahan (neo-kolonialisme) di Indonesia. Sejarah memperlihatkan bahwa proyek kolonialisme selalu berusaha memblokir upaya membangkitkan industri di dalam negeri.
Negeri-negeri imperialis mengingingkan agar Indonesia tetap menjadi negara penyedia bahan baku bagi industri mereka. Kalaupun ada pembangunan industri di negara jajahan, maka hal itu harus berasal dari modal atau investasi mereka. Selain itu, dengan ketiadaan industri nasional yang tangguh, maka Indonesia akan terus-menerus menjadi pasar bagi hasil produksi negeri-negeri imperialis.
Oleh karena itu, jika serius hendak membangun ekonomi nasional, maka proyek industrialisasi harus selaras dengan upaya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan membangkitkan produksi rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing.
Pada Agustus 1959, pemerintahan Sukarno sudah menyusun rancangan pembangunan semesta (overall planning). Para penggagasnya berharap bahwa bangsa Indonesia punya cetak biru dalam pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.
Rancangan pembangunan semesta itu bahkan sudah memberi dasar menuju pembangunan masyarakat sosialis Indonesia. Sayang sekali, sebelum proyek itu mencapai banyak kemajuan, pihak imperialis sudah menjegalnya. Mereka menggulingkan pemerintahan Bung Karno.
Bagi kami, sebagai awal yang baik untuk memulai kembali pembangunan nasional–jika pemerintah memang masih berkeinginan—ialah dengan mengembalikan semangat dan filosofi pasal 33 UUD 1945 sesuai keinginan para pendiri bangsa. Itulah pijakan kita untuk menyusun cetak biro industrialisasi nasional.
Selengkapnya...
Kenapa Modal Asing di Persoalkan..?
Sejak UU PMA disahkan tahun 1967, modal asing kembali mengambil ‘kendali’ dalam perekonomian nasional Indonesia. Bahkan, karena regulasi yang membuka pintu ekonomi lebar-lebar, modal asing sudah berada dalam posisi “mendominasi” perekonomian. Ia sudah berjengkelitan di atas karpet ekonomi nasional.
Perdebatan soal modal asing sudah berlangsung sejak lama. Ia bahkan sudah berlangsung sejak Indonesia ini masih dalam gagasan para pejuang pembebasan nasional. Saat itu, mereka sangat sadar betul bahwa modal asing merupakan bagian dari praktek penjajahan itu sendiri. Dalam pidato pembelaannya di depan pengadilan kolonial, yang kemudian dikenal dengan Indonesia Menggugat, Bung Karno sudah menandai penanaman modal asing sebagai aspek melekat dalam imperialisme modern.
Kami anggap pandangan itu tidak berubah hingga detik-detik menjelang Indonesia dimerdekakan. Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), hampir semua peserta sepakat bahwa ekonomi Indonesia merdeka haruslah diorganisir dari kemampuan rakyat dan tidak bergantung kepada modal asing.
Sekarang ini Indonesia menjadi ‘lahan suburnya modal asing’. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, pada semester 1-2011 realisasi investasi sebesar Rp115,6 triliun, dimana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp33 triliun dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp82,6 triliun.
Sebagian besar investasi itu berasal dari Amerika dan Eropa. Modal AS di Indonesia pada 2008 mencapai USD157 juta. Lalu, pada tahun 2010, jumlah investasi AS sudah berkisar USD871 juta di luar migas. Sementara Indonesia juga menjadi penyerap 1,6% dari total investasi dari Eropa. Setidaknya ada sekitar 700 perusahaan dengan total investasi sekitar 50 miliar euro.
Kami tidaklah anti-asing, atau asal-asalan anti-modal asing, tetapi berusaha berfikir kritis terhadap dampak buruk modal asing terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional indonesia.
Fakta sudah menunjukkan bahwa keberadaan modal asing tidak membawa kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Ambil contoh: sejak tahun 1967 hingga sekarang kegiatan pertambangan Freeport di Papua sudah menghasilkan sedikitnya 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika diuangkan, maka jumlahnya mencapai ratusan ribu billion rupiah (itu beratus-ratus kali lipat dari jumlah APBN kita).
Tetapi, lihatlah kondisi rakyat di sana: kondisi infrastruktur masih buruk, rakyat hidup miskin, pengangguran dimana-mana, sekolah susah diakses, layanan kesehatan mahal, dan lain sebagainya. Ini juga nampak dari penjelasan Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, “rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa asing keluar”.
Tidak ada nsatupu imperialis di dunia ini yang menanam kapital dengan semangat peri-kemanusiaan dan semangat menolong antar-sesama. Sebab kapitalisme, seperti dikatakan Lenin dalam “Imperialisme: Tahap Tertinggi Kapitalisme”, baik perkembangan tidak rata maupun taraf hidup yang setengah kelaparan dari massa adalah syarat fundamental dan tak terelakkan dan dalil utama cara produksi yang itu. Tujuan mereka adalah untuk menggali keuntungan sebesar-besarnya untuk kemakmuran segelintir orang: pemilik kapital.
Ini sudah disinggung oleh Bung Hatta sejak 70-an tahun yang lalu. Dalam satu potongan artikelnya di buku “Beberapa Fasal Ekonomi”, Bung Hatta menulis sebagai berikut:
“Soal kapital menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di Indonesia. Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau berarti sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran rakyat (cetak miring sesuai aslinya), mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pemerintah. Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran.
Pedoman bagi mereka untuk melekatkan kapital mereka di Indonesia ialah keuntungan. Keuntungan yang diharapkan mestilah lebih dari pada yang biasa, barulah berani mereka melekatkan kapitalnya itu. Supaya keuntungan itu dapat tertanggung, maka dikehendakinya supaya dipilih macam industri yang bakal diadakan, dan jumlahnya tidak boleh banyak. Berhubung dengan keadaan, industri agraria dan tambang yang paling menarik hati kaum kapitalis asing itu.
Dan, dengan jalan itu, tidak tercapai industrialisasi bagi Indonesia, melainkan hanya mengadakan pabrik-pabrik baru menurut keperluan kapitalis luar negeri itu saja. Sebab itu, Industrialisasi Indonesia dengan kapital asing tidak dapat diharapkan. Apalagi mengingat besarnya resiko yang akan menimpa kapital yang akan dipakai itu. Industrialisasi dengan bantuan kapital asing hanya mungkin, apabila pemerintah ikut serta dengan aktif, dengan mengadakan rencana yang dapat menjamin keselamatan modal asing itu. (Hal. 141)
Selengkapnya...

Ho Chi Minh
Berikut ini adalah bahan kuliah Professor Sakurai Yumio, Department of Asian History, the University of Tokyo, tentang Ho Chin Minh, pahlawan revolusi sosialis di Vietnam. Artikel ini diterjemahkan oleh Tri Ramidjo pada 27 Juli 1988. Bung Tri mendengar langsung Prof Sakurai berbicara, dan kemudian mengetiknya.
——————————–
Kami memuat kembali bahan kuliah ini untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan sejarah. Semoga generasi-generasi sekarang bisa mengambil pelajaran penting dari gerakan ini.
———————-
Partai Komunis Viet Nam (PKV), yang sejak berdirinya sudah mempunyai sejarah selama 58 tahun, sampai sekarang ini belum pernah tercatat tentang adanya terrorisme di dalam Partainya sendiri, walaupun di Viet Nam terjadi terrorisme kekejaman Perancis. Partai Komunis Vietnam belum pernah menterror atau membunuh anggota Partainya sendiri.
Sejarah PKV ini berbeda dengan sejarah PKUS (Partai Komunis Uni Soviet) dalam zamannya Stalin atau PKC (Partai Komunis Cina) dalam zaman revolusi kebudayaan.
Setiap tahun sebagian besar murid-murid Ho Chi Minh yang masih menjadi pemimpin-pemimpin tua selalu tidak pernah absen untuk ikut serta menghadiri peringatan ulang tahun kemerdekaan (2 SEPTEMBER 1945).
Tradisi seperti ini sudah dibuat sejak Ho Chi Minh. Semua orang Viet Nam mengetahui, bahwa Ho Chi Minh tidak suka melihat darah. Dengan membaca surat-surat dari Ho Chi Minh, kita akan mengerti bahwa Ho Chi Minh sangat keras membenci pelaksanaan kekerasan dan pembunuhan.
Tetapi perjuangan politik adalah perjuangan untuk merebut kekuasaan.
Dengan begitu, bagaimanapun juga, Ho Chi Minh tidak bisa terbebas dari Machiavelisme, seperti pada waktu orang-orang barat mengkritik atau mencela Ho Chi Minh tentang tindakannya (dan orang-orang barat sering mengutip) peristiwa pembunuhan atas Ta Thu Tau pada tahun 1945.
Ta Thu Tau adalah pemimpin Partai berhaluan Trotskisme di daerah selatan Vietnam antara tahun 1935 – 1939. Pada masa itu, partai ini (Partainya Ta Thu Tau) berada dalam keadaan lebih kuat daripada PKV pertama di Saigon .
Sejak Jepang menyerah kalah dalam perang pada bulan Agustus 1945 di daerah selatan Vietnam, kekuatan partai trotskisme ini hidup kembali dan berjuang bersama-sama dengan PKV. Pemimpin PKV di Saigon, Tran Van Giau, ingin menterror Ta Thu Tau. Tetapi Ho Chi Minh tidak memperbolehkan (tidak mengizinkan).
Akhirnya, Tran Van Giau mengirim surat laporan yang mengatakan, “kalau masih ada Ta Thu Tau, maka mungkin sekali PKV akan dikalahkan di selatan. Ho Chi Minh harus memilih antara dua pilihan untuk memimpin revolusi di selatan: memilih Ta Thu Tau atau Tran Van Giau. Ho Chi Minh terpaksa memberikan izin untuk menangkap dan mengeksekusi Ta Thu Tau pada bulan September tahun 1945.
Pada bulan Juli tahun 1946, ketika Ho Chi Minh berkunjung ke Perancis untuk menghadiri konferensi tentang kemerdekaan Vietnam, seorang wartawan terkenal bernama Daniel Gueren mengkritik tentang eksekusi Ta Thu Tau.
Kemudian Daniel Gueren menulis dalam artikelnya bagaimana Ho Chi Minh dengan mimik dan perasaan yang jujur menjelaskan kejadian yang sesungguhnya: “Ta Thu Tau adalah seorang nasionalis yang besar, Saya tahu. Saya menangis untuknya.”
Tetapi kemudian Ho Chi Minh mengatakan dengan tegas : “Tetapi kalau ada orang yang tidak mau mengikuti jejak saya, saya harus mengganyangnya”.
Semua orang barat yang mengkritik Ho Chi Minh kemudian menyimpulkan, bahwa Ho Chi Minh mempunyai perasaan yang halus dan baik untuk orang lain dan juga mempunyai ketegasan.
Tetapi, saya kira tidak ada seorang pun orang Vietnam yang menghendaki atau menginginkan pemimpin mereka, Ho Chi Minh, untuk menangis. Karena, bagi orang Vietnam, Ho Chi Minh dianggap sebagai ayah-ibu atau orang tua mereka.
Seperti apa yang ditulis oleh Truong Nhu Tan “orang kapal” (pengungsi Vietnam) dan apa yang dikatakan oleh pengarang buku “Vietnam Memoir”: “Kalau Ho Chi Minh masih hidup, tidak akan ada Orang Kapal atau Pengungsi Vietnam”.
Apa yang dikatakan Truonh Nhu Tan ini seperti kata-kata seorang anak yang telah kehilangan Ayah-Ibunya. Karakter pemimpin Ho Chi Minh ini adalah seperti perasaan hati orang tua terhadap anaknya. Tetapi perasaan-hati orang tua seperti Ho Chi Minh ini bukanlah perasaan orang tua yang mencintai bangsa Asia saja, tetapi mencintai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ho Chi Minh banyak menulis surat kepada orang-orang Vietnam , orang barat dan banyak lagi yang lain.
Diantara surat-suratnya yang sangat menarik adalah suratnya tanggal 23 November 1946.Ketika itu tentara Perancis sedang menghujani bom pelabuhan kota Hai Phong. Sepuluh ribu orang menjadi korban pengeboman itu dan semuanya adalah orang Vietnam.
Ketika itulah Ho Chi Minh menulis surat kepada saudara-saudaranya orang Vietnam dan saudara-saudaranya orang Perancis serta saudara-sadaranya orang-orang di seluruh dunia. Isi surat itu antara lain :
“Seluruh Rakyat Vietnam bertekad untuk mematuhi seruan Pemerintah Vietnam dan bersama-sama dengan Rakyat Perancis untuk menciptakan perdamaian. Sekarang ini saya menerima laporan dari pasukan Vietnam, bahwa dengan adanya peperangan antara dua negeri banyak darah tertumpah di Hai Phong. Hal ini disebabkan karena sebagian kecil orang Perancis salah mengerti (salah pengertian) mengenai perasaan-hati orang Vietnam dan mengira bahwa orang Vietnam tidak mau mentaati orang Perancis. Saya kira dengan perasaan dan semangat yang dicetuskan oleh revolusi Perancis, darah orang Perancis dan orang Vietnam adalah sama-sama merahnya. Orang Perancis dan orang Vietnam adalah sama-sama manusia.
Letak tanah Perancis adalah sangat jauh dari Vietnam berpuluh-puluh-ribu kilometer jaraknya. Vietnam yang merdeka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Perancis yang begitu jauh.
Kenapa (mengapa) orang Perancis mau menghancurkan kemerdekaan dan persatuan Vietnam? Orang Vietnam akan menerima dengan senang hati kedatangan orang Perancis di bumi Vietnam dan bekerja di Vietnam.
Pemerintah Vietnam akan melindungi orang Perancis di Vietnam, melindungi keuntungannya, melindungi harta bendanya dan melindungi kebudayaannya.
Jadi pemerintah Perancis harus mengakui pemerintah Vietnam .
Pemerintah Vietnam dan Rakyat Vietnam berjanji kepada Rakyat Perancis.
Saya sebagai pemimpin pemerintahan Vietnam sekarang memerintahkan kepada seluruh Rakyat Vietnam untuk tidak memerangi Rakyat Perancis dan karena itu juga Rakyat Perancis janganlah hendaknya memerangi Rakyat Vietnam .
Sekarang tanah air Vietnam menjadi merah karena mengalirnya darah Rakyat Vietnam dan Rakyat Perancis. Saya tidak ingin menjadi lebih memerah lagi.
Kenapa darah pemuda-pemuda Perancis harus memerahi tanah-tanah, gunung-gunung dan sungai-sungai di Vietnam?
Seluruh pemuda mempunyai hari-depan. Pemuda-pemuda Perancis dan pemuda-pemuda Vietnam bisa bergandengan tangan dan harus erat berjabatan tangan. Seluruh pemuda kedua bangsa ini harus menciptakan kebahagiaan untuk kedua bangsa. Saya dan seluruh Rakyat Vietnam menginginkan itu.
Saya ingin seluruh Rakyat Perancis dan Rakyat-Rakyat seluruh dunia mau mengerti isi-hati Rakyat Vietnam.”
- – - – - – - – - – - – -
Ketika Ho Chi Minh menulis surat itu, banyak Rakyat Vietnam yang mati.
Saya kira, Stalin– juga Mao Tse Tung dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya, tidak akan bisa menulis surat seperti itu. Surat tersebut adalah seperti surat seorang ayah-dunia yang ditujukan kepada anak-anak dunia.
Saya kira surat seperti ini hanya bisa ditulis oleh orang-orang angkatan (generasi) duapuluhan.
Seperti juga Nehru yang tinggal di Inggris, Ho Chi Minh tinggal di Perancis antara tahun-tahun 1917 – 1924.
Kawan lama Ho Chi Minh pernah menulis pada waktu itu, bahwa Ho Chi Minh banyak membaca buku-buku tulisan Tolstoy, Anatole France, Emile Zola, Roman Rolland dan lain-lain serta bergaul dengan orang-orang yang beraliran anarkis.
Biasanya orang-orang dari negeri barat sering membandingkan Ho Chi Minh dengan pemimpin India, Mahatma Gandhi. Kedua pemimpin itu isi surat-suratnya hampir sama.
Tentu saja angkatan (generasi) Ho Chi Minh dengan angkatan (generasi) Gandhi tidak sama.
Ho Chi Minh lahir pada tahun 1890, sedangkan Gandhi dilahirkan pada tahun 1869. Dan Gandhi adalah anak keturunan aristokrat dan bahkan sudah menjadi Sarjana Hukum pada usia dua-puluh-tahun di Inggris. Sementara Ho Chi Minh harus bekerja keras sebagai jongos (kelasi-kapal) pada tahun-tahun 1920–1923.
Sekalipun kedua orang itu mempunyai perbedaan yang besar, tetapi potret keduanya ketika tinggal di negeri barat sangat mirip. Walaupun keduanya (kedua orang itu) berpakaian cara barat, tetapi mereka bersikap ketimuran dalam potretnya. Mereka ingin menjadi seperti orang barat, tetapi tidak bisa.
(Contoh: Orang barat dalam potretnya menunjukkan kegagahannya dan menyombongkan diri, tetapi Ho Chi Minh atau Gandhi dalam potretnya walaupun berpakaian barat tidak kelihatan kegagahan dan kesombongannya. Seperti orang Jawa sikapnya selalu “ngapurancang”.)
Waktu Gandhi mempelajari ilmu hukum di Inggris, beliau pertama-tama menjadi sadar dan mengetahui bahwa kebudayaan India adalah kebudayaan yang baik.
Ho Chi Minh juga demikian dan pernah menulis sebagai berikut : “Perancis ingin membuat Rakyat Vietnam menjadi manusia-manusia yang tidak berpendirian (tidak berkepribadian)–tidak menjadi orang Perancis dan tidak menjadi orang Vietnam. Semua orang tentu tidak ingin menjadi begitu. Anda harus memilih menjadi orang Vietnam atau menjadi orang Perancis.”
Saya kira Gandhi dan Ho Chi Minh sudah cukup mengetahui betapa baiknya kebudayaan barat. Jadi mereka juga cukup mengenal dan mengetahui tentang kebaikan (betapa bagusnya) kebudayaan bangsanya sendiri.
Waktu saya tinggal di Perancis, teman saya di Perancis memperkenalkan kepada saya lima buah dokumen tentang mahasiswa Vietnam di zaman yang lalu.
Lima dokumen itu masih tersimpan baik di Pusat Arsip Nasional Perancis. Dan lima dokumen itu adalah dokumen tahun 1911.
Seorang pemuda namanya Nguyen Tat Tanh mengirimkan sepucuk surat kepada Presiden Perancis waktu itu yang isinya minta izin untuk belajar di sekolah Pamong-Praja (sekolah yang mendidik untuk bisa menjadi pegawai pemerintah kolonial Perancis) dan pemuda itu minta untuk bisa mendapatkan bea-siswa (scholarship).
Tetapi Presiden Perancis ketika itu menolak permohonan pemuda itu, karena tidak ada rekomendasi dari pemerintah kolonial Indo-China-Perancis. Dari dokumen ini nyatalah, bahwa pemuda Nguyen Tat Tanh berkeinginan untuk menjadi pamong-praja. (pegawai pemerintah kolonial Perancis),
Nguyen Tat Tanh adalah nama asli Ho Chi Minh.
Alamat Nguyen Tat Tanh dalam suratnya itu adalah nama kapal TELEVILLE,
Dalam otobiografinya Ho Chi Minh dalam tahun-tahun itu menyebutkan, bahwa beliau bekerja di kapal itu. Jadi Nguyen Tat Tanh tidak dapat disangsikan lagi adalah Ho Chi Minh.
Kalau pada waktu Ho Chi Minh ingin menjadi pegawai pamong-praja, hal itu sangatlah wajar.
Karena pemuda miskin Vietnam pada waktu itu ingin belajar pengetahuan Perancis dan itu adalah hanya jalan satu-satunya.
Otobiografi Ho Chi Minh yang ditulis resmi oleh PKV juga menyatakan bahwa kepergian Ho Chi Minh ke luar negeri adalah untuk mempelajari kebenaran dan kebijaksanaan. Saya kira, bagi Ho Chi Minh, kebenaran dan kebijaksanaan itu adalah kebudayaan Perancis.
Sejak pemerintah kolonial Perancis menolak suratnya, Ho Chi Minh terpaksa harus bekerja sebagai jongos-kelasi-kapal, sebagai kuli pembersih salju di musim dingin dan juga sebagai pelukis potret (melukis dan mentusir foto-foto).
Kadang-kadang Ho Chi Minh tidak bisa mendapatkan makanan untuk dimakan karena tidak mempunyai uang dan terpaksa tidur dipinggir-pinggir jalan. Tetapi surat-surat Ho Chi Minh pada waktu itu tidak pernah mencela atau mengkritik tindakan pemerintah Perancis.
Misalnya, dalam salah satu suratnya yang ditulis pada tahun 1914, yang ditujukan kepada seorang nasionalis terkenal Vietnam, Ho Chi Minh menulis dan menyatakan dalam suratnya itu bahwa beliau (Ho Chi Minh) ingin belajar bahasa Perancis dan bahasa Inggris saja.
Tetapi Ho Chi Minh mungkin belajar dari masyarakat miskin Perancis.
Pertama : bahwa di Perancis juga ada klas-kaum-miskin. Klas miskin Perancis itu sendiri bisa menjadi kawan sejati Rakyat Vietnam .
Ini adalah sosialisme – internasional Ho Chi Minh.
Kedua : Ho Chi Minh berfikir, karena kejujuran orang menjadi miskin. Jadi sampai akhir hidupnya (sampai meninggal), Ho Chi Minh tidak suka kemewahan. Sampai akhir hidupnya Ho Chi Minh hanya memiliki (mempunyai) dua helai pakaian terbuat dari katun.
Sekarang ini di Vietnam banyak terdapat buku-buku sejarah untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Sebagian besar isi buku sejarah itu adalah sejarah tentang kemiskinan Ho Chi Minh. Tentang kepahlawanannya hanya ditulis sedikit saja.
Kalau membaca sejarah itu, saya bisa mengerti bahwa Ho Chi Minh menentang kemewahan. Beliau bersikap seperti pendeta, pastor atau biksu.
Pada tahun 1945, sesudah Vietnam merdeka, di negeri itu tidak ada makanan, karena makanan yang ada sudah dihabiskan oleh tentara Jepang.
Ho Chi Minh, yang baru saja menjadi Presiden, menyerukan kepada seluruh Rakyat Vietnam: “Saudara-saudara, sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun ini, sudah 2,000,000 (dua juta) Rakyat Vietnam yang meninggal akibat kelaparan karena tidak ada makanan. Sekarang ini negeri kita dilanda air-bah (banjir) dan keadaan kekurangan makanan bertambah buruk. Waktu saya akan mengangkat piring nasi untuk makan, saya teringat kepada Rakyat yang kelaparan dan saya tidak bisa makan.
Jadi, saya ingin supaya orang-orang yang masih bisa makan setiap harinya, dalam sepuluh hari satu kali ( 10 hari sekali) mau memyisihkan bagian satu kali makan untuk diberikan kepada Rakyat (orang-orang) yang miskin, yang tidak bisa mendapatkan makanan. Saya juga akan melakukan hal itu. Dengan begitu orang yang miskin bisa melanjutkan hidupnya sampai musim panen nanti”.
Saya kira, hanya orang yang pernah merasakan lapar saja yang bisa membuat (membikin) seruan seperti ini. Saya belum pernah melihat pemimpin-pemimpin dunia yang lain yang menyerukan kepada Rakyatnya seruan seperti ini.
Kalau pun ada, mungkin hanya dua orang saja, yaitu Tolstoy dan Gandhi.
Bersambung->
Selengkapnya...
Mimpi Negara Kesejahteraan
DPR sudah mensahkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Bagi sebagian orang, pengesahan UU BPS itu merupakan jalan untuk mewujudkan konsep ‘negara kesejahteraan’ sebagaimana digariskan founding father. Bahkan PDIP, partai yang selalu mengklaim suara wong cilik, menyebut pengesahan BPJS sebagai kemenangan rakyat Indonesia.
Lebih jauh lagi, ada yang menganggap pengesahan UU BPJS sebagai penerapan semangat Pancasila (sila ke-5) dan UUD 1945. Mereka bahkan begitu berani menyimpulkan bahwa semangat BPJS itu selaras dengan cita-cita pendiri bangsa (founding father) tentang negara kesejahteraan (welfare state).
Di sini muncul sejumlah pertanyaan: Apakah benar cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan? Apakah mungkin negara kesejahteraan bisa diterapkan di tengah negara seperti Indonesia yang menganut neoliberalisme?
Kami kira, istilah “sosio-demokrasi” yang diperkenalkan oleh Bung Karno tidak bisa dipersamakan dengan “sosial-demokrasi” sebagaimana dianut sejumlah partai beraliran kiri-tengah di eropa. Sosio-demokrasi ala Soekarno adalah antisipasi terhadap kegagalan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, yang hanya mengejar kebebasan politik tetapi mengabaikan demokrasi ekonomi. Sementara sosio-demokrasi di barat, khususnya yang dibangun oleh Eduard Bernstein di akhir abad-kesembilan belas di Jerman, merupakan antisipasi terhadap kapitalisme dan juga sosialisme.
Sementara Soekarno berbicara bahwa hari depan masyarakat adil dan makmur adalah masyarakat sosialisme Indonesia, sedangkan sosio-demokrasi di eropa semakin bergerak menjauhi politik radikal dan semakin berorientasi sangat tengah (kanan). Soekarno berbicara tentang masa depan Indonesia dimana tidak ada lagi imperialisme dan kapitalisme, sedangkan sosio-demokrasi semakin mengadaftasikan diri untuk menambal-sulam kapitalisme.
Dan, menurut kami, masa depan masyarakat Indonesia sebagaimana digariskan founding father adalah masyarakat adil dan makmur. Adil dan makmur jelas berbeda dengan negara kesejahteraan. Dalam negara kesejahteraan, pencapaian masyarakat adil dan makmur belum tentu terjadi. Dalam banyak kasus, negara kesejahteraan hanya mencoba mencampurkan antara kapitalisme dan peran negara (mixed economy). Menurut kami, masyarakat adil dan makmur hanya mungkin terwujud dalam masyarakat sosialis.
Partai-partai sosial-demokrasi di Eropa berhasil meraih sedikit kemajuan terkait konsep negara kesejahteraan hanya pada periode booming ekonomi tahun 1950-an dan 1960-an. Pada saat itu, terjadi ekspansi ekonomi luar biasa dalam ekonomi dunia, belanja negara besar-besaran, dan peningkatan upah pekerja.
Pada saat itu, pengeluaran negara telah menjadi faktor kunci untuk mendorong permintaan. Di hampir seluruh negara kapitalis maju, belanja negara cukup tinggi, yakni rata-rata 28% dari PDB pada tahun 1950an dan meningkat 41% menjelang 1970an. Tingkat pengangguran juga sangat rendah pada saat itu. Sementara kenaikan upah real dalam kurun waktu tahun 1946-1976 (30 tahun) adalah 280 % (4.5 %/tahun).
Akan tetapi, ketika kapitalisme memasuki periode stagnasi pada tahun 1970-an, negara kesejahteraan di eropa satu per satu diutak-atik. Tidak sedikit partai berhaluan sosial-demokrat yang menjadi pendukung neoliberal.
Lenin, dalam karyanya “Imperialisme, Tahap Tertinggi Kapitalisme”, menguraikan bagaiamana negara-negara imperialis bisa menyogok lapisan tertentu dari klas pekerjanya karena keberhasilan mereka menarik laba besar dari negara-negara yang dijajah.
Nah, bagaimana dengan Indonesia yang merupakan negara jajahan? Periode panjang kolonialisme tidak menyediakan basis untuk perkembangan internal ekonomi nasional Indonesia. Sebagian besar surplus ekonomi mengalir atau diangkut ke negeri-negeri imperialis. Bahkan, ketika Indonesia dipaksa mengadopsi neoliberalisme, sebagian besar industri telah gulung tikar, pengangguran bertambah luas dan sektor informal membengkak.
Dengan kondisi begitu, penarikan iuran jaminan sosial hanya akan menjadi beban tambahan bagi rakyat. Ini sama saja dengan memeras orang yang sudah miskin, sehingga mereka akan menjadi semakin miskin.
Justru adanya kewajiban “iuran” ini adalah pelanggaran terhadap UUD 1945. Sebab, dalam UUD 1945, negara diwajibkan untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain). Sementara sistim “iuran” ini bermakna pelemparan tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab “setiap orang/individu”. “Setiap orang”-lah yang membayar dan memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan negara.
Belum lagi, jika dana jaminan sosial itu bisa diperdagangkan di bursa saham, maka semakin rentanlah rakyat miskin ini menjadi objek pemerasan oleh swasta atas nama jaminan sosial.
Sementara itu, negara sendiri belum tentu punya sumber daya yang cukup. Mengingat bahwa sebagian besar sumber daya dan potensi ekonomi nasional masih dikuasai oleh pihak asing. Sehingga, yang paling mendesak adalah perjuangan melikuidasi ekonomi kolonial dan menjalankan semangat pasal 33 UUD 1945 terlebih dahulu. Hanya setelah itu bisa dikerjakan, maka negara punya kemampuan untuk menjalankan “sistim jaminan sosial yang sebenarnya”.
Selengkapnya...
Kabinet Sekarang Makin Liberal
Ada satu hal yang makin terang dari reshuffle kabinet: pemerintahan sekarang makin berwatak neoliberal. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pendukung setia neoliberalisme yang ditampung dalam kabinet baru. Sementara beberapa menteri yang cenderung kritis terhadap neoliberal telah disingkirkan.
Salah satu menteri yang disingkirkan adalah Fadel Muhamad. Politisi partai golkar ini, dalam beberapa derajat, cukup kritis terhadap neoliberalisme. Ia meluncurkan sebuah gerakan berama “revolusi biru”, yakni sebuah perubahan paradigma yang mulai melihat pembangunan maritim itu sangat penting.
Fadel juga sering geram melihat tingkah-laku pertamina yang tak mau menjual BBM kepada nelayan. Ia juga sempat berseteru dengan Menteri Perdagangan, Maria Elka Pangestu, soal impor garam yang merugikan nelayan. Kementeriannya juga memperjuangkan penghapusan retribusi bagi nelayan.
Program semacam itu, sekalipun dirasa masih kurang, tetap punya makna di tengah gempuran neoliberal seperti sekarang. Setidaknya upaya Fadel itu masih dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dan, rasanya, itu merupakan ‘batu sandungan’ bagi agenda neoliberal di sektor kelautan dan perikanan.
Lalu apa yang makin neoliberal? SBY tidak mencopot atau mengurangi porsi menteri berhaluan neoliberal di kabinet. Maria Elka Pangestu, yang sudah dihujani kritik karena agenda perdagangan bebasnya, masih dipertahankan dan cuma digeser ke pos kementerian yang baru.
Sebaliknya, SBY makin membuka tempat kepada menteri berhaluan neoliberal. Di posisi Kementerian BUMN, SBY menunjuk Dahlan Iskan menggantikan Mustafa Abubakar. Mustafa Abubakar sebetulnya pro-neoliberal, tetapi ia dinilai kurang kapabel dalam menjalankan pekerjaannya. Maka ditunjuklah Dahlan Iskan, seorang neoliberal yang piawai dalam menjalankan tugasnya.
Saat Dahlan Iskan ditunjuk sebagai Dirut PLN, Serikat Pekerja PLN sudah melakukan penolakan keras. Dahlan Iskan dianggap titipan asing untuk menjalankan agenda privatisasi di tubuh perusahaan listrik negara itu. Dan memang begitu, Dahlan Iskan sangat komitmen untuk menjalankan agenda privatisasi PLN. Bahkan ia melakukan tindakan “union busting” terhadap pekerja yang menolak agenda privatisasi.
Sosok neoliberal dalam formasi menteri baru lainnya adalah Gita Wirjawan. Mantan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini dianggap sangat pro kepada modal asing. Kita bisa melihat hal itu pada sepak terjang Gita Wirjawan saat menjabat pimpinan di BKPM, tetapi kita juga bisa melihat pada fikiran-fikirannya.
Pada 7 Oktober 2010, Gita Wirjawan sempat menulis sebuah opini berjudul “Nasionalisme Ekonomi” di harian Kompas. Dalam artikel itu, Gita menghakimi apa yang disebutnya sebagai ‘penempatan kepentingan nasional yang kurang tepat’.
Salah satu bentuk penempatan nasionalisme yang kurang tepat, kata Gita Wirjawan, adalah fokus pada besarnya struktur kepemilikan. Baginya, seperti analogi kucing hitam dan putih yang bisa menangkap tikus, Gita tidak mempersoalkan antara modal asing dan nasional, asalkan bisa memberi manfaat kepada rakyat banyak.
Padahal, 70 tahun yang lalu, Bung Hatta sudah menulis: ““Soal kapital menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di Indonesia. Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau berarti sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran rakyat (cetak miring sesuai aslinya), mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pemerintah. Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran.”
Keadaan sekarang juga memperlihatkan hal itu: modal asing tidak membawa kebaikan sedikitpun pada kesejahteraan rakyat. Malahan membawa kemiskinan dan kesengsaraan pada rakyat. Kita bisa melihat bagaimana perusahaan asing mengeruk kekayaan alam Indonesia di berbagai tempat. Sementara manfaatnya terhadap rakyat setempat hampir tidak ada sama sekali. Bahkan yang terjadi adalah perampasan tanah, kekerasan, pengrusakan lingkungan, dan lain sebagainya.
Dua orang itu, Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan, hanya contoh kuatnya agenda neoliberal dalam formasi kabinet baru. Tetapi ada hal penting lain yang harus dicatat pula: pemerintahan SBY tidak punya komitmen terhadap pemerintahan bersih atau pemberantasan korupsi. Dua orang menteri yang terduga terlibat kasus korupsi, yaitu Muhaimin Iskandar dan Andi Malarangeng, masih tetap dipertahankan. Ini menjelaskan bahwa praktek korupsi di Indonesia adalah bagian tak-terpisahkan dari proyek neoliberalisme itu sendiri. Atau bahasa sederhananya: “neoliberalisme perlu terus berjalan dan berkelanjutan. Tetapi, supaya terus berkelanjutan, ia mesti didukung oleh pundi-pundi yang didapat dari politik korup.”
Selengkapnya...
Reforma Agraria untuk Kemandirian Bangsa

Materi diskusi Dewan Nasional - Serikat Tani Nasional di Bandar Lampung 2011
“Kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak ditempatkannya
pembaruan agraria yang berupa penataan kembali penguasaan,
penggunaan, pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber
agraria sebagai pra-kondisi dari pembangunan… Pembaruan agraria
dipercayai pula sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali
struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga
tercipta dasar pertanian yang sehat, terjaminnya kepastian penguasaan atas
tanah bagi rakyat sebagai sumberdaya kehidupan mereka, sistem
kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta
penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.” (Deklarasi Pembaruan Agraria, Jogjakarta 1998)
Presiden SBY dalam rangka pidato awal tahun 2007 di TVRI (31/01/2007 malam) menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria (Reforma Agraria) yang pada intinya adalah melakukan redistribusi Tanah Negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani termiskin. Dalam hal mengatasi kemiskinan, ketimpangan agraria dan konflik agraria Presiden SBY pada tahun 2010 kembali berjanji segera melaksanakan program pembaharuan agraria nasional dan mendistribusikan tanah-tanah kepada para petani, yang pertama dalam peresmian program strategis pertanahan yang digagas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan Berikat Nusantara, Cilincing, Jakarta Utara bulan Januari 2010, kedua di bulan September 2010 di Istana melalui Staff Khusus Presiden (SKP) bidang pangan dan energi dan SKP bidang otonomi dan pembangunan daerah serta ketiga dibulan Oktober dalam peringatan Hari Tani Nasional ke 50 di Istana Bogor.
Apa yang disampaikan oleh kepala BPN dan Presiden SBY dalam peringatan acara Hari Tani pada 21 Oktober 2010 lalu, mengenai prioritas kerja BPN kedepan (Pembaruan Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria, Penyelesaian persoalan tanah terlantar, distribusinya kepada rakyat dan percepatan sertifikasi pertanahan) merupakan janji yang diulangi lagi. Karena pengalaman sejak tahun 2006 hingga hari ini janji tersebut tidak kunjung terealisasi. Pada Bulan Maret 2010 BPN menyatakan bahwa ada 7,3 juta hektar lahan terlantar yang siap didistribusikan. Namun pada tahun 2010 hanya 260 hektar tanah yang didistribusikan kepada 5.141 petani. Artinya rata-rata petani hanya mendapatkan 0.05 ha atau 500m2 per KK.
Belum lagi realisasi janji dan program kampanye, pemerintah justru seakan terus melegalkan berbagai bentuk perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar melalui program-program seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), REDD+ dan lainnya. Awal tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2010 tentang food estate atau pertanian tanaman pangan berskala luas. Yang kemudian disusul dengan Permentan yang menindaklanjuti PP tersebut. Poin penting dari pelaksanaan program perkebunan skala luas ini ialah kepastian dan perlindungan ijin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan industri pertanian pangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan (BKPMDP), Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah memberikan ijin bagi 32 perusahaan untuk mengelola lahan pertanian seluas 1,6 juta hektar di Merauke. Data BPS menunjukkan luas lahan pertanian padi di Indonesia pada tahun 2010 tinggal 12,870 juta hektar, menyusut 0,1% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 12,883 juta hektar. Luas lahan pertanian secara keseluruhan termasuk non-padi pada 2010 diperkirakan berjumlah 19,814 juta hektar, menyusut 13 persen dibanding tahun 2009 yang mencapai 19,853 juta ha.
isue tentang krisis pangan yg melanda dunia
Badan PBB untuk Urusan Pangan dan Pertanian (FAO) merilis indeks harga pangan dunia per Januari lalu naik 3,4 persen menjadi 231 poin. Itu merupakan angka tertinggi sejak 1990, saat FAO mulai memantau harga pangan dunia. Naiknya indeks itu terjadi akibat melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan, seperti sereal atau padi-padian, gula dan minyak sayur. Indeks FAO mengukur perubahan harga sejumlah komoditas pangan internasional setiap bulan. Survei itu menjadi barometer bagi para analis dan investor sebagai patokan global tren harga pangan dunia
Laporan Bank Dunia yang dimuat dalam jurnal edisi terbaru, Food Price Watch, selama Oktober 2010 hingga Januari 2011 menyatakan harga pangan di tingkat global naik 15 persen. Tingginya harga pangan ini membuat sekitar 44 juta orang miskin di penjuru dunia kian melarat sejak Juni 2010. “Harga pangan dunia tengah naik menuju tingkat yang berbahaya dan mengancam puluhan juta kaum miskin di penjuru dunia,” kata Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick, seperti dikutip stasiun berita BBC. Bank Dunia menyerukan agar para pejabat keuangan negara-negara G20–di mana Indonesia termasuk di dalamnya–untuk membahas masalah ini.
Sejak pemerintah menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil swasembada beras kembali 2008 lalu, di penghujung tahun 2010 ini impor beras kembali dibuka. Lebih lanjut dengan persetujuan Kementrian Perdagangan bea masuk beras impor dihapuskan hingga Februari 2011. Padahal produksi gabah nasional menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 sebesar 65.980.670 ton atau naik 64.398.890 ton dibandingkan tahun 2009. Namun cadangan beras di BULOG hanya 1,8 juta ton sekitar separuh dari penyerapannya pada tahun 2009 sebanyak 3,8 juta ton. Kekurangan cadangan beras di BULOG inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk membuka impor beras tahun ini
Dihapuskannya bea masuk impor hingga nol persen ini tentu akan menyebabkan serbuan beras-beras impor dari Negara tetangga, hal ini tentu akan merugikan petani dalam negeri. Saat ini saja sudah dipastikan adanya kontrak impor beras sebanyak 850 ribu ton, yang mulai masuk ke Indonesia. Kemudian ditambah dengan 200 ribu ton dari vietnam. Tidak terserapnya produksi beras dalam negeri menandakan perlu adanya perbaikan kinerja dan daya serap BULOG. Lebih lanjut kebijakan harga beras (HPP) pemerintah tidak membantu peningkatan kesejahteraan petani. Keuntungan yang lebih besar dalam margin perdagangan beras justru jatuh di tangan penggilingan dan BULOG. Impor beras akan sangat menekan produksi yang dilakukan oleh para petani dan pada akhirnya komoditas beras akan bernasib sama dengan komoditas pertanian lain. Import beras pun akan menghabiskan begitu banyak devisa negara anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk mengimpor 1,05 juta ton beras sekitar Rp 4,86 triliun, lebih lanjut 1,05 juta ton beras setara dengan produksi yang dihasilkan dari 216.000 hektar sawah, jika rata-rata per hektar memproduksi 5 ton gabah. Kalau rata-rata keluarga petani padi memiliki 0,5 hektar lahan artinya dana impor ini setara dengan pendapatan 432.000 keluarga petani di Indonesia.
Janji hanya tinggal janji
Janji Redistribusi lahan kepada petani juga relevan dengan janji SBY untuk meningkatkan produksi pertanian/pangan nasional. Ujungnya adalah tercapainya swasembada pangan sebagai komponen utama kehidupan bangsa. Swasembada pangan juga berarti memutus rantai ketergantung kita terhadap pangan impor, terutama beras dari Vietnam, Thailand, Filipina, India dan AS. Sejauh ini didengungkan bahwa impor beras merupakan konsekuensi dari kesenjangan antara kebutuhan konsumsi nasional.
Sayangnya, kedua janji tersebut hingga kini tidak terwujud dan menyisakan kegetiran di kalangan petani dan kelompok miskin. Padahal, redistribusi lahan merupakan pamungkas untuk memerangi kemiskinan sekaligus mendongkrak tingkat kesejahteraan petani. Begitu pula swasembada pangan merupakan ukuran pulihnya peran Negara dalam menghadirkan kesejahteraan sosial. Seperti diperkirakan banyak orang, janji tersebut sengaja diembuskan SBY untuk membalutkan citra dirinya sebagai pemimpin berhati mulia yang sensitif dan peduli terhadap penderitaan kaum miskin.
Terlalu mewah rasanya kalau kita berharap SBY akan menjadikan Morales sebagai idola dan inspirasi penting dalam melaksanakan reforma agraria. Sebaliknya, SBY melalui Badan Pertanahan Nasional yang digawangi Joyo Winoto, Ph.D justru gesit melahirkan regulasi yang berpotensi membunuh petani dan kaum miskin.
Pertama, PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman yang dikhususkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada pengusaha, untuk mengembangkan industri pangan berskala besar atau food estate. Di samping memicu lahirnya monopoli kepemilikan lahan oleh pemodal PP ini, juga mempertegas keberpihakan pemerintahan SBY terhadap pasar tanah yang semakin liberal yang sesungguhnya ditolak oleh UUPA tahun 1960. PP ini juga mengkondisikan masyarakat bukan lagi sebagai kekuatan produktif, melainkan sekadar konsumen pasif terhadap kebijakan-kebijakan impor pangan.
Kedua, RUU Pertanahan. Inti dari RUU ini adalah demi kepentingan umum, maka hambatan-hambatan dalam perolehan tanah harus dihilangkan. RUU ini memang ditujukan untuk memuluskan investasi di negeri ini yang oleh pemerintah diproyeksikan sebagai skenario penting untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan sekaligus memompa devisa.
Dari situ terlihat bahwa SBY-Boediono mengabaikan reforma agraria karena tidak memiliki visi dan agenda yang jelas.
“Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak
dari Revolusi Indonesia.” (Soekarno, Djalannja Revolusi Kita, 1960)
Selengkapnya...
Marhaen dan Proletar
oleh: Ir. Soekarno
Di dalam konferensi di kota Mataram baru-baru ini, Partindo telah mengambil putusan tentang Marhaen dan Marhaenisme, yang poin-poinnya antara lain sebagai berikut:
1. Marhaenisme, yaitu Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.
2. Marhaen yaitu kaum Proletar Indonesia, kaum Tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.
3. Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar, oleh karena perkataan proletar sudah termaktub di dalam perkataan Marhaen, dan oleh karena perkataan proletar itu bisa juga diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub di dalamnya.
4. Karena Partindo berkeyakinan, bahwa di dalam perjuangan, kaum melarat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya (bagian-bagiannya), maka Partindo memakai perkataan Marhaen itu.
5. Di dalam perjuangan Marhaen itu maka Partindo berkeyakinan bahwa kaum Proletar mengambil bagian yang besar sekali.
6. Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan Marhaen.
7. Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu cara perjuangan yang revolusioner.
8. Jadi Marhaenisme adalah : cara perjuangan dan azas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme.
9. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan Marhaenisme.
* * *
Sembilan kalimat dari putusan ini sebenarnya sudah cukup terang menerangkan apa artinya Marhaen dan Marhaenisme. Memang perkataan-perkataannya di sengaja perkataan-perkataan yang populer, sehingga siapa saja yang membacanya, dengan segera mengerti apa maksud-maksudnya. Namun, -ada satu kalimat yang sangat sekali perlu diterangkan lebih luas, karena memang ssangat sekali pentingnya. Kalimat itu ialah kalimat yang kelima. Ia berbunyi: “Di dalam perjuangan Marhaen itu, maka Partindo berkeyakinan, bahwa kaum Proletar mengambil bagian yang besar sekali.”
Satu kalimat ini saja sudahlah membuktikan, bahwa cara perjuanngan yang dimaksudkan ialah cara perjuangan yang tidak ngelamun, cara perjuangan yang dimaksudkan ialah cara perjuangan yang “menurut kenyataan”, -cara perjuangan yang modern. Sebab, apa yang dikatakan di situ? Yang dikatakan disitu ialah, bahwa didalam perjuangan Marhaen, kaum Proletar mengambil bagian yang besar sekali.
Ya, disini dibikin perbedaan paham yang tajam sekali antara Marhaen dan Proletar. Memang di dalam kalimat nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 daripada putusan itu adalah diterangkan perbedaan paham itu: bahwa Marhaen bukanlah kaum Proletar (kaum buruh) saja, tetapi ialah kaum Proletar dan kaum Tani melarat Indonesia yang lain-lain, -misalnya kaum dagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum grobag, kaum nelayan, dan kaum lain-lain. Dan kemodernannya dan kerasionilannya kalimat nomor 5 itu ialah, bahwa di dalam perjuanngan bersama daripada kaum Proletar dan kaum Tani dan kaum melarat lain-lain itu, kaum Proletarlah mengambil bagian yang besar sekali: Marhaen seumumnya sama berjuang, Marhaen seumumnya sama merebut hidup, Marhaen seumumnya sama berikhtiar mendatangkan masyarakat yang menyelamatkan Marhaen seumumnya pula –namun kaum Proletar yang mengambil bagian yang besar sekali.
Ini, paham ”Proletar mengambil bagian yang besar sekali”-, inilah yang saya sebutkan modern, inilah yang bernama rasional. Sebab kaum Proletarlah yang kini lebih hidup di dalam ideologi modern, kaum Proletarlah yang sebagai klasse lebih langsung terkenal oleh kapitalisme, kaum Proletarlah yang lebih “mengerti” akan segala-galanya kemodernan Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Mereka lebih “selaras dengan jaman”, mereka lebih “nyata pemikirannya,” mereka lebih “konkret”, dan…Mereka lebih besar harga perlawanannya, lebih besar gevechtswaarde-nya dari kaum yang lain-lain. Kaum tani adalah umumnya masih hidup dengan satu kaki di dalam ideologi feodalisme, hidup di dalam angan-angan mistik yang melayang-layang diatas awang-awang, tidak begitu “selaras jaman” dan “nyata pikiran” sebagai kaum Proletar yang hidup di dalam kegemparan percampur gaulan abad keduapuluh. Mereka masih banyak mengagung-agungkan ningratisme, percaya pada seorang “Ratu Adil” atau “Heru Cokro” yang nanti akan terjelma dari kalangan membawa kenikmatan surga dunia yang penuh dengan rezeki dan keadailan, ngandel akan “kekuatan-kekuatan rahasia” yang bisa “memujakan” datangnya pergaulan hidup baru dengan termenung di dalam gua.
Mereka di dalam segala-galanya masih terbelakang, masih “kolot”, masih “kuno”. Mereka memang sepantasnya begitu: mereka punya pergaulan hidup adalah pergaulan hidup “kuno”. Mereka punya cara produksi adalah cara produksi dari jaman Medang Kamulan dan Majapahit, mereka punya beluku adalah belukunya Kawulo seribu lima ratus tahun yang lalu, mereka punya garu adalah sama tuanya dengan nama garu sendiri, mereka punya cara menanam padi, cara hidup, pertukar-tukaran hasil, pembahagian tanah, pendek seluruh kehidupan sosial ekonominya adalah masih berwarna kuno, -mereka punya ideologi pasti berwarna kuno pula!
Sebaliknya kaum Proletar sebagai klas adalah hasil langsung daripada kapitalisme dan imperialisme. Mereka adalah kenal akan pabrik, kenal akan mesin, kenal akan listrik, kenal akan cara produksi kapitalisme, kenal akan kemodernannya abad keduapuluh. Mereka ada pula lebih langsung menggenggam mati hidupnya kapitalisme di dalam mereka punya tangan, lebih direct (langsung, ed.) mempunyai gevechtswaarde anti kapitalisme. Oleh karena itu, adalah rasionil jika mereka yang di dalam perjuangan anti kapitalisme dan imperialisme itu berjalan di muka, jika mereka yang menjadi pandu, jika mereka yang menjadi “voorlooper”, -jika mereka yang menjadi “pelopor”. Memang! Sejak adanya soal “Agrarfrage” alias “soal kaum tani”, sejak adanya soal ikutnya si tani di dalam perjuangan melawan stelsel (sistem, ed.) kapitalisme yang juga tak sedikit menyengsarakan si tani itu, maka Marx sudah berkata bahwa di dalam perjuangan tani dan buruh ini, kaum buruh lah yang harus menjadi “revolutionaire voorhode” alias “barisan muka yang revolusioner”: kaum tani harus dijadikan kawannya kaum buruh, dipersatukan dan dirukunkan dengan kaum buruh, dibela dalam perjuangan anti kapitalisme agar jangan nanti menjadi begundalnya kaum kapitalisme itu, -tetapi di dalam perjuangan bersama ini kaum buruhlah yang “menjadi pemanggul panji-panji Revolusi Sosial”. Sebab, memang merekalah yang, menurut Marx, sebagai klasse ada suatu “social noodwendigheid” (suatu keharusan dalam sejarah, ed.), dan memang kemeangan ideologi merkalah yang nanti ada suatu “historische noodwendigheid”, -suatu keharusan riwayat, suatu kemustian di dalam riwayat.
Welnu, jikalau benar ajaran Marx ini, maka benar pula kalimat nomor 5 daripada sembilan kalimat diatas tadi, yang mengatakan bahwa di dalam perjuangan Marhaen, kaum Buruh mempunyai bagian yang besar sekali.
Tetapi orang bisa membantah bahwa keadaan di Eropa tak sama dengan keadaan di Indonesia? Bahwa disana kapitalisme terutama sekali kapitalisme kepabrikan, sedang disini ia adalah terutama sekali kapitalisme pertanian? Bahwa disana kapitalisme bersifat zulvere industrie, sedang disini ia buat 75% bersifat onderneming (perkebunan, ed.) karet, “onderneming” teh, onderneming tembakau, onderneming karet, onderneming kina, dan lain sebagainya? Bahwa disana hasil kapitalisme itu ialah terutama sekali kaum Proletar 100%, sedang disini ia terutama sekali ia menghasilkan kaum tani melarat yang papa dan sengsara? Bahwa disana memang benar mati hidup kapitalisme itu ada di dalam genggaman kaum Proletar, tetapi di sini ia buat sebagian besaar ada di dalam genggaman kaum tani? Bahwa dus sepantasnya disana kaum Proletar yang menjadi “pembawa panji-panji,” tetapi disini belum tentu harus begitu juga?
Ya,… benar kapitalisme disini adalah 75% industril kapitalisme pertanian, benar mati hidupnya kapitalisme disini itu buat sebagian besar ada di dalam genggamannya kaum tani, tetapi hal ini tidak merubah kebenaran pendirian, bahwa kaum buruhlah yang harus menjadi “pembawa panji-panji”. Lihatlah sebagai tamzil sepak teryangnya suatu tentara militer: yang menghancurkan tentaranya musuh adalah tenaga daripada seluruh tentara itu, tetapi toh ada satu barisan daripadanya yang ditaruh dimuka, berjalan dimuka, berkelahi mati-matian dimuka, -mempengaruhi dan menjalankan kenekatan dan keberaniannya seluruh tentara itu: barisan ini adalah barisannya barisan pelopor. Nah, tentara kita adalah benar tentaranya Marhaen, tentaranya klas Marhaen, tentara yang banyak mengambil tenaganya kaum tani, tetapi barisan pelopor kita adalah barisannya kaum buruh, barisannya kaum Proletar.
Oleh karena itu, pergerakan kaum Marhaen tidak akan menang, jika tidak sebagai bagian daripada pergerakan Marhaen itu diadakan barisan “buruh dan sekerja” yang kokoh dan berani. Camkanlah ajaran ini, kerjakanlah ajaran ini! Bangunkanlah barisan “buruh dan sekerja” itu, bangkitkanlah semangat dan keinsyafan, susunkanlah semua tenaganya! Pergerakan politik Marhaen umum adalah perlu, -tetapi sarekat buruh dan sekerja adalah juga perlu, amat perlu, teramat perlu, maha perlu dengan tiada hingganya!
Fikiran Ra’jat 1933
Catatan: Sociale Noodwendigheid: Suatu keharusan di dalam masyarakat.
Selengkapnya...
soekarno dan Konsepsi Persatuan Nasional

Sebuah News Latter INSTITUTE SOEKARNO Edisi I Maret 2011
Membicarakan konsep front persatuan, tidak lengkap rasanya jika tidak menyebutkan nama Bung karno dan gagasan-gagasan politiknya. Ia memegang teguh keyakinan politiknya sejak awal hingga akhir, termasuk keyakinannya soal persatuan nasional yang dinamainya Nasakom, akronim dari nasionalis, agama, dan komunis.
Ada banyak yang mengatakan, pemikiran Bung Karno mengenai Nasakom adalah yang paling orisinil dan acceptable di Indonesia. Sedangkan tak sedikitpula yang mencibir, bahwa persatuan nasional nasakom hanya konsep belaka dan akan berantakan jika dipraktekkan.
Kondisi Yang Melahirkan Gagasan Persatuan
Bung Karno menginjak masa kematangan dalam pergerakan untuk kemerdekaan nasional dengan melalui dua fase penting. Pertama, ketika dia tinggal di Surabaya, yaitu rumah Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional kenalan bapaknya. Rumah Tjokroaminoto merupakan “universitas politik” bagi Bung Karno, dimana ia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan dan menyerap teori-teori politik mereka.
Kedua, ketika Bung Karno melanjutkan sekolahnya di HBS Bandung, tempat dimana ia mendengarkan kuliah-kuliah dari sosialis-demokrat dan demokrat radikal Belanda. Di Bandung, Bung Karno menemukan semangat lain, bukan hanya karena mendengar ceramah-ceramah orang-orang sosialis demokrat macam J.E. Stokvis dan C. Hartogh, tetapi juga karena mendapat siraman radikalisme dari tokoh-tokoh pergerakan Indische Partij, seperti Tjipto Mangkunkusumo dan Douwes Dekker.
Kedua pengalaman itu sangat mempengaruhi gagasan-gagasan politik Bung Karno muda. Di satu sisi, dia sangat kagum dengan guru dan sekaligus mertuanya, Tjokroaminoto, tetapi kurang puas dengan langkah moderatnya. Sedangkan, pada sisi yang lain, dia semakin menyerap teori-teori baru (nasionalisme radikal dan sosialisme) dan memantapkan diri untuk terbenam dalam perjuangan anti-kolonialisme dan pembebasan rakyat.
Namun, pada tahun 1921, Bung Karno mulai menyaksikan dinamika yang sangat cepat di kalangan pergerakan; saling kritik, perpecahan, dan persatuan. Ada beberapa hal yang menandai situasi gerakan pada kurun waktu 1921 hingga 1926 (lahirnya tulisan Bung Karno: Marxisme, nasionalisme, dan islamisme). Pertama, semakin menguatnya pengaruh gerakan rakyat yang menolak untuk mengemis kemajuan kepada pihak kolonialis Belanda. Partai-partai ini, terutama sekali PKI dan Indische Partij, telah memaklumkan sikap non-koperasi terhadap pemerintahan kolonial. Bung Karno dalam sebuah pidato menggebu-gebu di tahun 1923, mengatakan: “….Sudah tiba saatnya untuk tidak lagi mengemis-ngemis, tetapi adalah menuntut kepada tuan-tuan kaum Imperialis.”
Seiring dengan periode surutnya gerakan mengemis-ngemis itu, maka pamor tokoh-tokoh semacam Tjokroaminoto dan Dr. Soetomo pun semakin merosot di mata kaum pergerakan dan rakyat.
Kedua, Bung Karno menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saling serang di kalangan pergerakan pembebasan nasional. Dalam tahun 1921, di dalam Sarekat Islam (SI), organisasi politik terbesar saat itu, telah terjadi perpecahan yang tak terhindarkan. Para pemimpin sayap kanan (SI putih) telah berhasil memaksa keluar pengikut-pengikutnya yang kiri (SI-merah)—yang sangat dipengaruhi oleh ISDV/PKI.
Pemuda Bung Karno juga menyaksikan bagaimana gurunya, Tjokroaminoto, diserang secara pribadi oleh Haji Misbach, tokoh haji merah yang berfikiran radikal dan anti-kolonial. Dalam kongres PKI itu, pemuda Bung Karno berdiri dan meminta Haji Misbach untuk meminta maaf.
Ketiga, Bung Karno menyaksikan kesuksesan setidaknya 17 organisasi mendirikan front persatuan yang diberi nama ‘Konsentrasi Radikal’, yang menggabukan organisasi, diantaranya, Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan Perkumpulan Sosial Demokratis Indonesia.
Konsep Persatuan: Nasionalis, Islamis, Dan Marxis
Pada tahun 1926 Bung Karno mengeluarkan tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, dimana ia menegaskan bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah “kebesaran dan kemerdekaan”.
Dalam tulisan itu, yang didalamnya disertai penjelasan yang sangat mendalam, Bung Karno menegaskan bahwa tiga aliran dalam politik Indonesia, yaitu nasionalis, agama, dan marxis, bisa bersatu untuk mencapai Indonesia merdeka.
“Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” demikian ditulis Bung Karno untuk menyakinkan keharusan front persatuan tiga kekuatan itu.
Dengan meminjam kata-kata Gandhi dan pengalamannya, Bung Karno telah menunjukkan bahwa kaum nasionalis bisa bersatu dengan kaum marxis dan pan-islamisme.
Bung Karno membedakan antara nasionalis sejati, yaitu nasionalis cintanya pada tanah-air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, dengan nasionalis chauvinis. Menurut pendapatnya, nasionalis sejati akan terbuka untuk bekerjasama dengan golongan politik lain yang memiliki tujuan sama.
Demikian pula terhadap islam, Bung Karno telah membedakan antara islam kolot dan islam sejati. “Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham Nasionalisme yang luas budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum islamis tidak berdiri di atas Sirothol Mustaqim,” tulis Bung Karno.
Ditariknya pendekatan mengenai kesamaan antara islam dan marxisme, yaitu sama-sama bersifat sosialistis, dan letakkannya musuh bersama bagi keduanya; kapitalisme (paham riba).
Sementara terhadap kaum Marxis, Bung Karno telah mengambil taktik perjuangan kaum marxis yang baru, yaitu “tidak menolak pekerjaan-bersama-sama dengan Nasionalis dan Islamis di Asia”. Untuk menyakinkan kaum marxis, Bung Karno mengambil contoh: Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Nasionalis di negeri Tiongkok; dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di negeri Afganistan.
Sesuai dengan keadaan Indonesia
Konsep persatuan diantara tiga kekuatan itu tidaklah jatuh dari langit, ataupun dari imajinasi biasa dari Bung Karno, melainkan dipetik dari kenyataan real dari keadaan Indonesia.
Bung Karno adalah salah seorang dari berbagai tokoh gerakan pembebasan nasional yang tidak menginjakkan kakinya di luar negeri, namun menyerap ilmu pergerakannya dari tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan, seperti Tjokroaminoto, Tjipto Mangungkusumo, dan lain-lain.
Pengetahuannya mengenai marxisme didapatkan dari kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah kaum sosialis Belanda, dan paling banyak didapatkan dari berbagai literatur marxis yang dibacanya. Tetapi Bung Karno bukan seorang dogmatis, ia selalu berhasil meletakkan teori itu dalam syarat-syarat keadaan Indonesia dan dipergunakan untuk mencapai satu tujuan; Indonesia merdeka!
Demkian pula saat mengeluarkan konsep persatuan tiga kekuatan itu, Bung Karno telah mengambilnya dari kenyataan politik di Indonesia. Bagaiaman Bung Karno bisa membangun konsepsi persatuannya:
Pertama, Bung Karno adalah orang yang paling tekun dalam mempelajari berbagai aliran politik dalam gerakan nasional Indonesia. Dalam penyelidikan dan pengamatannya secara langsung, ketiga aliran itulah yang mewakili perjuangan melawan kolonialisme dan mewakili pengaruh luas di kalangan rakyat.
Bung Karno pernah menjadi anggota Sarekat Islam, meskipun tidak pernah terdaftar sebagai pengurus. Dia juga sering menemani Tjokroaminoto dalam menghadiri rapat-rapat akbar (vergadering) dan pertemuan-pertemuan.
Selain itu, ketika beraktivitas di Bandung, Bung Karno juga sangat dekat dengan tokoh nasionalis radikal, khususnya Tjipto Mangungkusumo, yang oleh belanda dikenal dikenal sebagai ”elemen paling berbahaya dalam gerakan rakyat di jawa.
Dari segi pemikiran, Bung Karno sangat dipengaruhi oleh nasionalis-nasionalis progressif, terutama Gandhi dan Sun Yat Sen. Dia juga bersentuhan dengan pemikiran nasionalis-nasionalis lain macam Mazzini, Cavour, dan Garibaldi.
Terhadap gerakan komunis, Bung Karno sangat tekun mempelajari marxisme dan menyebut dirinya sebagai Marxis. Semasa di rumah Tjokroaminoto, Bung Karno telah berkenalan dengan Snevleet, Baars, dan orang-orang Indonesia: Semaun, Musso, Tan Malaka, dan Alimin. Bahkan Bung Karno mengakui bahwa Marhaenisme, hasil temuannya sendiri, adalah marxisme yang dicocokkan dan dilaksanakan menurut keadaan Indonesia.
Kedua, Bung Karno, seperti juga kaum marxis pada umumnya, mengakui adanya kontradiksi tak terdamaikan antara kolonialisme/imperialisme dengan rakyat Indonesia, atau dalam bahasa Bung Karno: pertentangan sana dan sini; sana mau kesana, sini mau ke sini.
Dengan begitu, tidak benar juga kalau dikatakan front persatuan ala Bung Karno ini terlalu eklektis, sebab pembedaan sini dan sana itu sudah merupakan sebuah pembedaan yang jelas, gamblang.
Bung Karno sangat menyakini, bahwa jika ketiga kekuatan ini dapat disatukan dalam sebuah persatuan, maka dia menjadi gabungan kekuatan yang maha dahsyat. Karena, menurut perhitungan Bung Karno, gabungan kekuatan ini meliputi 90% paling sedikit daripada seluruh rakyat Indonesia.
Lapangan Praktek
Pada bulan September 1927, berpidato di hadapan peserta kongres Partai Sarekat Indonesia, Bung Karno telah mengusulkan untuk mendirikan semacam federasi diantara organisasi-organisasi pergerakan nasional.
Ide yang dilemparkan Bung Karno mendapat sambutan luas, dan kepada Bung Karno diserahi tugas untuk merancang konsep persatuannya. Dan, pada desember 1927, enam organisasi politik telah bersepakat mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Namun, Bung Karno berhasil menyatukan perbedan-perbedaan diantara organisasi terkait taktik, khususnya soal koperasi dan non-koperasi, dengan mengatasnamakan tujuan kemerdekaan. Akan tetapi, sebagai konsekuensi logisnya, Bung Karno gagal membawa federasi ini menjadi radikal.
Beberapa front persatuan sesudahnya, seperti Gabungan Aksi Politik Indonesia (GAPI), dimana Partindo tergabung di dalamnya, sedikit-banyaknya sesuai dengan konsep persatuan ala Bung Karno.
Lebih jauh lagi, rumusan persatuan tiga kekuatan ini akan sangat nampak pula dalam pidato Bung Karno mengenai dasar negara di depan BPUPKI, 1 Juni 1945, yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan Pancasila adalah rumusan dari tiga kekuatan; nasionalis, agamais, dan marxis. Bung Karno
mengatakan, pancasila itu dapat diperas menjadi tiga, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-nasionalisme, dan Sosio-demokrasi. Ketiga perasan pancasila tersebut, lanjut Bung Karno, masih dapat diperas lagi menjadi satu, atau sering disebut Ekasila, yaitu: Gotong Royong.
Belakangan, Bung Karno mempersamakan antara pancasila, Gotong-royong, dan Nasakom (nasionalis, Agama, dan Komunis). “Nasakom adalah perasan dari pancasila, dus nasakom adalah sebenarnya juga gotong royong, sebab gotong royong adalah de totale perasan dari pancasila, maka perasan daripada Nasakom adalah gotong royong pula,” demikian kata Bung Karno pada pembukaan kursus kilat kader Nasakom, 1 Juni 1965.
Pada tahun 1959, Soekarno telah memprakarsai pembentukan Front Nasional, yang tujuannya adalah menuntaskan revolusi nasional dan dibentuknya sebuah masyarakat adil dan makmur. Soekarno, yang telah berhasil menyakinkan PKI, berusaha menghidupkan kembali kolaborasi antara kaum nasionalis, agamais, dan marxis untuk menghadapi imperialisme.
PKI sendiri sangat menyambut uluran tangan Bung Karno untuk bersama-sama melawan imperialisme. Dan, di akhir tahun 1960-an, sebagaimana dicatat oleh Rex Mortimer, PKI telah secara terbuka menegaskan untuk mensubordinasikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional.
Sebetulnya Front Nasional dirancang untuk memobilisasi seluruh kekuatan rakyat guna melawan imperialisme. Dan, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, Soekarno menganjurkan agar Front Nasional dibangun hingga ke dusun-dusun. Sayang sekali, niat ini tidak sepenuhnya berjalan dan lebih banyak disabotase.
Di penghujung 1965, ketika sebuah kudeta merangkak berusaha menggusur dirinya dari kekuasaan, Soekarno menolak pertumpahan darah dan memilih untuk terus mengedepankan persatuan nasional. Pada pidato 17 Agustus 1966, Bung Karno menyerukan agar tetap memperkuat persatuan tiga kekuatan, yaitu Nasakom. Pun, ketika demonstrasi mahasiswa kanan menuntut Bung Karno agar segera membubarkan PKI dan ormas-ormas komunis, Ia telah menolaknya. Dan, dengan suara yang lebih tegas, bahwa Pancasila tidak anti Nas (nasionalis), tidak anti A (agama), dan tidak anti Kom (komunis)
Selengkapnya...
Search
Pengunjung
Kategori
- Berdikari (14)
- Internasional (4)
- Kabar Juang (3)
- Kabar Rakyat (4)
- Organisasi (1)
- Politik (8)
- sastra (1)
- Soekarnoisme (6)
- Statement (5)
- Tokoh (4)
Jaringan
Mengenai Saya
- Randy Syahrizal
- mempunyai minat menulis sejak kuliah di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra USU tahun 2003. Pernah menulis di beberapa media lokal (Sumatera Utara) dan Media Online Nasional. Blog pribadi saya : http://ceritadarimedan.blogspot.com
Followers
Blog Archive
-
▼
2011
(24)
-
►
November
(8)
- Memajukan Gerakan Pasal 33 UUD 1945 dalam Memimpin...
- Puluhan Aktivis Serukan Gerakan Pasal 33 Di Samarinda
- Amandemen UUD 1945 Harus Melalui Referendum!
- Nasionalisme Kita dan Persoalan Papua
- Mana Cetak BIru Industrialisasi Nasional Kita ?
- Kenapa Modal Asing di Persoalkan..?
- Ho Chi MinhBerikut ini adalah bahan kuliah Profess...
- Mimpi Negara Kesejahteraan
-
►
November
(8)