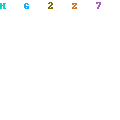Ada satu hal yang makin terang dari reshuffle kabinet: pemerintahan sekarang makin berwatak neoliberal. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pendukung setia neoliberalisme yang ditampung dalam kabinet baru. Sementara beberapa menteri yang cenderung kritis terhadap neoliberal telah disingkirkan.
Salah satu menteri yang disingkirkan adalah Fadel Muhamad. Politisi partai golkar ini, dalam beberapa derajat, cukup kritis terhadap neoliberalisme. Ia meluncurkan sebuah gerakan berama “revolusi biru”, yakni sebuah perubahan paradigma yang mulai melihat pembangunan maritim itu sangat penting.
Fadel juga sering geram melihat tingkah-laku pertamina yang tak mau menjual BBM kepada nelayan. Ia juga sempat berseteru dengan Menteri Perdagangan, Maria Elka Pangestu, soal impor garam yang merugikan nelayan. Kementeriannya juga memperjuangkan penghapusan retribusi bagi nelayan.
Program semacam itu, sekalipun dirasa masih kurang, tetap punya makna di tengah gempuran neoliberal seperti sekarang. Setidaknya upaya Fadel itu masih dalam kerangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dan, rasanya, itu merupakan ‘batu sandungan’ bagi agenda neoliberal di sektor kelautan dan perikanan.
Lalu apa yang makin neoliberal? SBY tidak mencopot atau mengurangi porsi menteri berhaluan neoliberal di kabinet. Maria Elka Pangestu, yang sudah dihujani kritik karena agenda perdagangan bebasnya, masih dipertahankan dan cuma digeser ke pos kementerian yang baru.
Sebaliknya, SBY makin membuka tempat kepada menteri berhaluan neoliberal. Di posisi Kementerian BUMN, SBY menunjuk Dahlan Iskan menggantikan Mustafa Abubakar. Mustafa Abubakar sebetulnya pro-neoliberal, tetapi ia dinilai kurang kapabel dalam menjalankan pekerjaannya. Maka ditunjuklah Dahlan Iskan, seorang neoliberal yang piawai dalam menjalankan tugasnya.
Saat Dahlan Iskan ditunjuk sebagai Dirut PLN, Serikat Pekerja PLN sudah melakukan penolakan keras. Dahlan Iskan dianggap titipan asing untuk menjalankan agenda privatisasi di tubuh perusahaan listrik negara itu. Dan memang begitu, Dahlan Iskan sangat komitmen untuk menjalankan agenda privatisasi PLN. Bahkan ia melakukan tindakan “union busting” terhadap pekerja yang menolak agenda privatisasi.
Sosok neoliberal dalam formasi menteri baru lainnya adalah Gita Wirjawan. Mantan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini dianggap sangat pro kepada modal asing. Kita bisa melihat hal itu pada sepak terjang Gita Wirjawan saat menjabat pimpinan di BKPM, tetapi kita juga bisa melihat pada fikiran-fikirannya.
Pada 7 Oktober 2010, Gita Wirjawan sempat menulis sebuah opini berjudul “Nasionalisme Ekonomi” di harian Kompas. Dalam artikel itu, Gita menghakimi apa yang disebutnya sebagai ‘penempatan kepentingan nasional yang kurang tepat’.
Salah satu bentuk penempatan nasionalisme yang kurang tepat, kata Gita Wirjawan, adalah fokus pada besarnya struktur kepemilikan. Baginya, seperti analogi kucing hitam dan putih yang bisa menangkap tikus, Gita tidak mempersoalkan antara modal asing dan nasional, asalkan bisa memberi manfaat kepada rakyat banyak.
Padahal, 70 tahun yang lalu, Bung Hatta sudah menulis: ““Soal kapital menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi di Indonesia. Rakyat sendiri tidak mempunyai kapital. Kalau industrialisasi mau berarti sebagai jalan untuk mencapai kemakmuran rakyat (cetak miring sesuai aslinya), mestilah kapitalnya datang dari pihak rakyat atau pemerintah. Karena, kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran.”
Keadaan sekarang juga memperlihatkan hal itu: modal asing tidak membawa kebaikan sedikitpun pada kesejahteraan rakyat. Malahan membawa kemiskinan dan kesengsaraan pada rakyat. Kita bisa melihat bagaimana perusahaan asing mengeruk kekayaan alam Indonesia di berbagai tempat. Sementara manfaatnya terhadap rakyat setempat hampir tidak ada sama sekali. Bahkan yang terjadi adalah perampasan tanah, kekerasan, pengrusakan lingkungan, dan lain sebagainya.
Dua orang itu, Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan, hanya contoh kuatnya agenda neoliberal dalam formasi kabinet baru. Tetapi ada hal penting lain yang harus dicatat pula: pemerintahan SBY tidak punya komitmen terhadap pemerintahan bersih atau pemberantasan korupsi. Dua orang menteri yang terduga terlibat kasus korupsi, yaitu Muhaimin Iskandar dan Andi Malarangeng, masih tetap dipertahankan. Ini menjelaskan bahwa praktek korupsi di Indonesia adalah bagian tak-terpisahkan dari proyek neoliberalisme itu sendiri. Atau bahasa sederhananya: “neoliberalisme perlu terus berjalan dan berkelanjutan. Tetapi, supaya terus berkelanjutan, ia mesti didukung oleh pundi-pundi yang didapat dari politik korup.”
Selengkapnya...
Kabinet Sekarang Makin Liberal
Reforma Agraria untuk Kemandirian Bangsa

Materi diskusi Dewan Nasional - Serikat Tani Nasional di Bandar Lampung 2011
“Kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak ditempatkannya
pembaruan agraria yang berupa penataan kembali penguasaan,
penggunaan, pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber
agraria sebagai pra-kondisi dari pembangunan… Pembaruan agraria
dipercayai pula sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali
struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga
tercipta dasar pertanian yang sehat, terjaminnya kepastian penguasaan atas
tanah bagi rakyat sebagai sumberdaya kehidupan mereka, sistem
kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta
penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.” (Deklarasi Pembaruan Agraria, Jogjakarta 1998)
Presiden SBY dalam rangka pidato awal tahun 2007 di TVRI (31/01/2007 malam) menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menjalankan pembaruan agraria (Reforma Agraria) yang pada intinya adalah melakukan redistribusi Tanah Negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani termiskin. Dalam hal mengatasi kemiskinan, ketimpangan agraria dan konflik agraria Presiden SBY pada tahun 2010 kembali berjanji segera melaksanakan program pembaharuan agraria nasional dan mendistribusikan tanah-tanah kepada para petani, yang pertama dalam peresmian program strategis pertanahan yang digagas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan Berikat Nusantara, Cilincing, Jakarta Utara bulan Januari 2010, kedua di bulan September 2010 di Istana melalui Staff Khusus Presiden (SKP) bidang pangan dan energi dan SKP bidang otonomi dan pembangunan daerah serta ketiga dibulan Oktober dalam peringatan Hari Tani Nasional ke 50 di Istana Bogor.
Apa yang disampaikan oleh kepala BPN dan Presiden SBY dalam peringatan acara Hari Tani pada 21 Oktober 2010 lalu, mengenai prioritas kerja BPN kedepan (Pembaruan Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria, Penyelesaian persoalan tanah terlantar, distribusinya kepada rakyat dan percepatan sertifikasi pertanahan) merupakan janji yang diulangi lagi. Karena pengalaman sejak tahun 2006 hingga hari ini janji tersebut tidak kunjung terealisasi. Pada Bulan Maret 2010 BPN menyatakan bahwa ada 7,3 juta hektar lahan terlantar yang siap didistribusikan. Namun pada tahun 2010 hanya 260 hektar tanah yang didistribusikan kepada 5.141 petani. Artinya rata-rata petani hanya mendapatkan 0.05 ha atau 500m2 per KK.
Belum lagi realisasi janji dan program kampanye, pemerintah justru seakan terus melegalkan berbagai bentuk perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar melalui program-program seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), REDD+ dan lainnya. Awal tahun 2010 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2010 tentang food estate atau pertanian tanaman pangan berskala luas. Yang kemudian disusul dengan Permentan yang menindaklanjuti PP tersebut. Poin penting dari pelaksanaan program perkebunan skala luas ini ialah kepastian dan perlindungan ijin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan industri pertanian pangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan (BKPMDP), Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah memberikan ijin bagi 32 perusahaan untuk mengelola lahan pertanian seluas 1,6 juta hektar di Merauke. Data BPS menunjukkan luas lahan pertanian padi di Indonesia pada tahun 2010 tinggal 12,870 juta hektar, menyusut 0,1% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 12,883 juta hektar. Luas lahan pertanian secara keseluruhan termasuk non-padi pada 2010 diperkirakan berjumlah 19,814 juta hektar, menyusut 13 persen dibanding tahun 2009 yang mencapai 19,853 juta ha.
isue tentang krisis pangan yg melanda dunia
Badan PBB untuk Urusan Pangan dan Pertanian (FAO) merilis indeks harga pangan dunia per Januari lalu naik 3,4 persen menjadi 231 poin. Itu merupakan angka tertinggi sejak 1990, saat FAO mulai memantau harga pangan dunia. Naiknya indeks itu terjadi akibat melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan, seperti sereal atau padi-padian, gula dan minyak sayur. Indeks FAO mengukur perubahan harga sejumlah komoditas pangan internasional setiap bulan. Survei itu menjadi barometer bagi para analis dan investor sebagai patokan global tren harga pangan dunia
Laporan Bank Dunia yang dimuat dalam jurnal edisi terbaru, Food Price Watch, selama Oktober 2010 hingga Januari 2011 menyatakan harga pangan di tingkat global naik 15 persen. Tingginya harga pangan ini membuat sekitar 44 juta orang miskin di penjuru dunia kian melarat sejak Juni 2010. “Harga pangan dunia tengah naik menuju tingkat yang berbahaya dan mengancam puluhan juta kaum miskin di penjuru dunia,” kata Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick, seperti dikutip stasiun berita BBC. Bank Dunia menyerukan agar para pejabat keuangan negara-negara G20–di mana Indonesia termasuk di dalamnya–untuk membahas masalah ini.
Sejak pemerintah menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil swasembada beras kembali 2008 lalu, di penghujung tahun 2010 ini impor beras kembali dibuka. Lebih lanjut dengan persetujuan Kementrian Perdagangan bea masuk beras impor dihapuskan hingga Februari 2011. Padahal produksi gabah nasional menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 sebesar 65.980.670 ton atau naik 64.398.890 ton dibandingkan tahun 2009. Namun cadangan beras di BULOG hanya 1,8 juta ton sekitar separuh dari penyerapannya pada tahun 2009 sebanyak 3,8 juta ton. Kekurangan cadangan beras di BULOG inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk membuka impor beras tahun ini
Dihapuskannya bea masuk impor hingga nol persen ini tentu akan menyebabkan serbuan beras-beras impor dari Negara tetangga, hal ini tentu akan merugikan petani dalam negeri. Saat ini saja sudah dipastikan adanya kontrak impor beras sebanyak 850 ribu ton, yang mulai masuk ke Indonesia. Kemudian ditambah dengan 200 ribu ton dari vietnam. Tidak terserapnya produksi beras dalam negeri menandakan perlu adanya perbaikan kinerja dan daya serap BULOG. Lebih lanjut kebijakan harga beras (HPP) pemerintah tidak membantu peningkatan kesejahteraan petani. Keuntungan yang lebih besar dalam margin perdagangan beras justru jatuh di tangan penggilingan dan BULOG. Impor beras akan sangat menekan produksi yang dilakukan oleh para petani dan pada akhirnya komoditas beras akan bernasib sama dengan komoditas pertanian lain. Import beras pun akan menghabiskan begitu banyak devisa negara anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk mengimpor 1,05 juta ton beras sekitar Rp 4,86 triliun, lebih lanjut 1,05 juta ton beras setara dengan produksi yang dihasilkan dari 216.000 hektar sawah, jika rata-rata per hektar memproduksi 5 ton gabah. Kalau rata-rata keluarga petani padi memiliki 0,5 hektar lahan artinya dana impor ini setara dengan pendapatan 432.000 keluarga petani di Indonesia.
Janji hanya tinggal janji
Janji Redistribusi lahan kepada petani juga relevan dengan janji SBY untuk meningkatkan produksi pertanian/pangan nasional. Ujungnya adalah tercapainya swasembada pangan sebagai komponen utama kehidupan bangsa. Swasembada pangan juga berarti memutus rantai ketergantung kita terhadap pangan impor, terutama beras dari Vietnam, Thailand, Filipina, India dan AS. Sejauh ini didengungkan bahwa impor beras merupakan konsekuensi dari kesenjangan antara kebutuhan konsumsi nasional.
Sayangnya, kedua janji tersebut hingga kini tidak terwujud dan menyisakan kegetiran di kalangan petani dan kelompok miskin. Padahal, redistribusi lahan merupakan pamungkas untuk memerangi kemiskinan sekaligus mendongkrak tingkat kesejahteraan petani. Begitu pula swasembada pangan merupakan ukuran pulihnya peran Negara dalam menghadirkan kesejahteraan sosial. Seperti diperkirakan banyak orang, janji tersebut sengaja diembuskan SBY untuk membalutkan citra dirinya sebagai pemimpin berhati mulia yang sensitif dan peduli terhadap penderitaan kaum miskin.
Terlalu mewah rasanya kalau kita berharap SBY akan menjadikan Morales sebagai idola dan inspirasi penting dalam melaksanakan reforma agraria. Sebaliknya, SBY melalui Badan Pertanahan Nasional yang digawangi Joyo Winoto, Ph.D justru gesit melahirkan regulasi yang berpotensi membunuh petani dan kaum miskin.
Pertama, PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman yang dikhususkan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada pengusaha, untuk mengembangkan industri pangan berskala besar atau food estate. Di samping memicu lahirnya monopoli kepemilikan lahan oleh pemodal PP ini, juga mempertegas keberpihakan pemerintahan SBY terhadap pasar tanah yang semakin liberal yang sesungguhnya ditolak oleh UUPA tahun 1960. PP ini juga mengkondisikan masyarakat bukan lagi sebagai kekuatan produktif, melainkan sekadar konsumen pasif terhadap kebijakan-kebijakan impor pangan.
Kedua, RUU Pertanahan. Inti dari RUU ini adalah demi kepentingan umum, maka hambatan-hambatan dalam perolehan tanah harus dihilangkan. RUU ini memang ditujukan untuk memuluskan investasi di negeri ini yang oleh pemerintah diproyeksikan sebagai skenario penting untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan sekaligus memompa devisa.
Dari situ terlihat bahwa SBY-Boediono mengabaikan reforma agraria karena tidak memiliki visi dan agenda yang jelas.
“Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak
dari Revolusi Indonesia.” (Soekarno, Djalannja Revolusi Kita, 1960)
Selengkapnya...
Marhaen dan Proletar
oleh: Ir. Soekarno
Di dalam konferensi di kota Mataram baru-baru ini, Partindo telah mengambil putusan tentang Marhaen dan Marhaenisme, yang poin-poinnya antara lain sebagai berikut:
1. Marhaenisme, yaitu Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi.
2. Marhaen yaitu kaum Proletar Indonesia, kaum Tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.
3. Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar, oleh karena perkataan proletar sudah termaktub di dalam perkataan Marhaen, dan oleh karena perkataan proletar itu bisa juga diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub di dalamnya.
4. Karena Partindo berkeyakinan, bahwa di dalam perjuangan, kaum melarat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya (bagian-bagiannya), maka Partindo memakai perkataan Marhaen itu.
5. Di dalam perjuangan Marhaen itu maka Partindo berkeyakinan bahwa kaum Proletar mengambil bagian yang besar sekali.
6. Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan Marhaen.
7. Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu cara perjuangan yang revolusioner.
8. Jadi Marhaenisme adalah : cara perjuangan dan azas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme.
9. Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan Marhaenisme.
* * *
Sembilan kalimat dari putusan ini sebenarnya sudah cukup terang menerangkan apa artinya Marhaen dan Marhaenisme. Memang perkataan-perkataannya di sengaja perkataan-perkataan yang populer, sehingga siapa saja yang membacanya, dengan segera mengerti apa maksud-maksudnya. Namun, -ada satu kalimat yang sangat sekali perlu diterangkan lebih luas, karena memang ssangat sekali pentingnya. Kalimat itu ialah kalimat yang kelima. Ia berbunyi: “Di dalam perjuangan Marhaen itu, maka Partindo berkeyakinan, bahwa kaum Proletar mengambil bagian yang besar sekali.”
Satu kalimat ini saja sudahlah membuktikan, bahwa cara perjuanngan yang dimaksudkan ialah cara perjuangan yang tidak ngelamun, cara perjuangan yang dimaksudkan ialah cara perjuangan yang “menurut kenyataan”, -cara perjuangan yang modern. Sebab, apa yang dikatakan di situ? Yang dikatakan disitu ialah, bahwa didalam perjuangan Marhaen, kaum Proletar mengambil bagian yang besar sekali.
Ya, disini dibikin perbedaan paham yang tajam sekali antara Marhaen dan Proletar. Memang di dalam kalimat nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 daripada putusan itu adalah diterangkan perbedaan paham itu: bahwa Marhaen bukanlah kaum Proletar (kaum buruh) saja, tetapi ialah kaum Proletar dan kaum Tani melarat Indonesia yang lain-lain, -misalnya kaum dagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum grobag, kaum nelayan, dan kaum lain-lain. Dan kemodernannya dan kerasionilannya kalimat nomor 5 itu ialah, bahwa di dalam perjuanngan bersama daripada kaum Proletar dan kaum Tani dan kaum melarat lain-lain itu, kaum Proletarlah mengambil bagian yang besar sekali: Marhaen seumumnya sama berjuang, Marhaen seumumnya sama merebut hidup, Marhaen seumumnya sama berikhtiar mendatangkan masyarakat yang menyelamatkan Marhaen seumumnya pula –namun kaum Proletar yang mengambil bagian yang besar sekali.
Ini, paham ”Proletar mengambil bagian yang besar sekali”-, inilah yang saya sebutkan modern, inilah yang bernama rasional. Sebab kaum Proletarlah yang kini lebih hidup di dalam ideologi modern, kaum Proletarlah yang sebagai klasse lebih langsung terkenal oleh kapitalisme, kaum Proletarlah yang lebih “mengerti” akan segala-galanya kemodernan Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Mereka lebih “selaras dengan jaman”, mereka lebih “nyata pemikirannya,” mereka lebih “konkret”, dan…Mereka lebih besar harga perlawanannya, lebih besar gevechtswaarde-nya dari kaum yang lain-lain. Kaum tani adalah umumnya masih hidup dengan satu kaki di dalam ideologi feodalisme, hidup di dalam angan-angan mistik yang melayang-layang diatas awang-awang, tidak begitu “selaras jaman” dan “nyata pikiran” sebagai kaum Proletar yang hidup di dalam kegemparan percampur gaulan abad keduapuluh. Mereka masih banyak mengagung-agungkan ningratisme, percaya pada seorang “Ratu Adil” atau “Heru Cokro” yang nanti akan terjelma dari kalangan membawa kenikmatan surga dunia yang penuh dengan rezeki dan keadailan, ngandel akan “kekuatan-kekuatan rahasia” yang bisa “memujakan” datangnya pergaulan hidup baru dengan termenung di dalam gua.
Mereka di dalam segala-galanya masih terbelakang, masih “kolot”, masih “kuno”. Mereka memang sepantasnya begitu: mereka punya pergaulan hidup adalah pergaulan hidup “kuno”. Mereka punya cara produksi adalah cara produksi dari jaman Medang Kamulan dan Majapahit, mereka punya beluku adalah belukunya Kawulo seribu lima ratus tahun yang lalu, mereka punya garu adalah sama tuanya dengan nama garu sendiri, mereka punya cara menanam padi, cara hidup, pertukar-tukaran hasil, pembahagian tanah, pendek seluruh kehidupan sosial ekonominya adalah masih berwarna kuno, -mereka punya ideologi pasti berwarna kuno pula!
Sebaliknya kaum Proletar sebagai klas adalah hasil langsung daripada kapitalisme dan imperialisme. Mereka adalah kenal akan pabrik, kenal akan mesin, kenal akan listrik, kenal akan cara produksi kapitalisme, kenal akan kemodernannya abad keduapuluh. Mereka ada pula lebih langsung menggenggam mati hidupnya kapitalisme di dalam mereka punya tangan, lebih direct (langsung, ed.) mempunyai gevechtswaarde anti kapitalisme. Oleh karena itu, adalah rasionil jika mereka yang di dalam perjuangan anti kapitalisme dan imperialisme itu berjalan di muka, jika mereka yang menjadi pandu, jika mereka yang menjadi “voorlooper”, -jika mereka yang menjadi “pelopor”. Memang! Sejak adanya soal “Agrarfrage” alias “soal kaum tani”, sejak adanya soal ikutnya si tani di dalam perjuangan melawan stelsel (sistem, ed.) kapitalisme yang juga tak sedikit menyengsarakan si tani itu, maka Marx sudah berkata bahwa di dalam perjuangan tani dan buruh ini, kaum buruh lah yang harus menjadi “revolutionaire voorhode” alias “barisan muka yang revolusioner”: kaum tani harus dijadikan kawannya kaum buruh, dipersatukan dan dirukunkan dengan kaum buruh, dibela dalam perjuangan anti kapitalisme agar jangan nanti menjadi begundalnya kaum kapitalisme itu, -tetapi di dalam perjuangan bersama ini kaum buruhlah yang “menjadi pemanggul panji-panji Revolusi Sosial”. Sebab, memang merekalah yang, menurut Marx, sebagai klasse ada suatu “social noodwendigheid” (suatu keharusan dalam sejarah, ed.), dan memang kemeangan ideologi merkalah yang nanti ada suatu “historische noodwendigheid”, -suatu keharusan riwayat, suatu kemustian di dalam riwayat.
Welnu, jikalau benar ajaran Marx ini, maka benar pula kalimat nomor 5 daripada sembilan kalimat diatas tadi, yang mengatakan bahwa di dalam perjuangan Marhaen, kaum Buruh mempunyai bagian yang besar sekali.
Tetapi orang bisa membantah bahwa keadaan di Eropa tak sama dengan keadaan di Indonesia? Bahwa disana kapitalisme terutama sekali kapitalisme kepabrikan, sedang disini ia adalah terutama sekali kapitalisme pertanian? Bahwa disana kapitalisme bersifat zulvere industrie, sedang disini ia buat 75% bersifat onderneming (perkebunan, ed.) karet, “onderneming” teh, onderneming tembakau, onderneming karet, onderneming kina, dan lain sebagainya? Bahwa disana hasil kapitalisme itu ialah terutama sekali kaum Proletar 100%, sedang disini ia terutama sekali ia menghasilkan kaum tani melarat yang papa dan sengsara? Bahwa disana memang benar mati hidup kapitalisme itu ada di dalam genggaman kaum Proletar, tetapi di sini ia buat sebagian besaar ada di dalam genggaman kaum tani? Bahwa dus sepantasnya disana kaum Proletar yang menjadi “pembawa panji-panji,” tetapi disini belum tentu harus begitu juga?
Ya,… benar kapitalisme disini adalah 75% industril kapitalisme pertanian, benar mati hidupnya kapitalisme disini itu buat sebagian besar ada di dalam genggamannya kaum tani, tetapi hal ini tidak merubah kebenaran pendirian, bahwa kaum buruhlah yang harus menjadi “pembawa panji-panji”. Lihatlah sebagai tamzil sepak teryangnya suatu tentara militer: yang menghancurkan tentaranya musuh adalah tenaga daripada seluruh tentara itu, tetapi toh ada satu barisan daripadanya yang ditaruh dimuka, berjalan dimuka, berkelahi mati-matian dimuka, -mempengaruhi dan menjalankan kenekatan dan keberaniannya seluruh tentara itu: barisan ini adalah barisannya barisan pelopor. Nah, tentara kita adalah benar tentaranya Marhaen, tentaranya klas Marhaen, tentara yang banyak mengambil tenaganya kaum tani, tetapi barisan pelopor kita adalah barisannya kaum buruh, barisannya kaum Proletar.
Oleh karena itu, pergerakan kaum Marhaen tidak akan menang, jika tidak sebagai bagian daripada pergerakan Marhaen itu diadakan barisan “buruh dan sekerja” yang kokoh dan berani. Camkanlah ajaran ini, kerjakanlah ajaran ini! Bangunkanlah barisan “buruh dan sekerja” itu, bangkitkanlah semangat dan keinsyafan, susunkanlah semua tenaganya! Pergerakan politik Marhaen umum adalah perlu, -tetapi sarekat buruh dan sekerja adalah juga perlu, amat perlu, teramat perlu, maha perlu dengan tiada hingganya!
Fikiran Ra’jat 1933
Catatan: Sociale Noodwendigheid: Suatu keharusan di dalam masyarakat.
Selengkapnya...
soekarno dan Konsepsi Persatuan Nasional

Sebuah News Latter INSTITUTE SOEKARNO Edisi I Maret 2011
Membicarakan konsep front persatuan, tidak lengkap rasanya jika tidak menyebutkan nama Bung karno dan gagasan-gagasan politiknya. Ia memegang teguh keyakinan politiknya sejak awal hingga akhir, termasuk keyakinannya soal persatuan nasional yang dinamainya Nasakom, akronim dari nasionalis, agama, dan komunis.
Ada banyak yang mengatakan, pemikiran Bung Karno mengenai Nasakom adalah yang paling orisinil dan acceptable di Indonesia. Sedangkan tak sedikitpula yang mencibir, bahwa persatuan nasional nasakom hanya konsep belaka dan akan berantakan jika dipraktekkan.
Kondisi Yang Melahirkan Gagasan Persatuan
Bung Karno menginjak masa kematangan dalam pergerakan untuk kemerdekaan nasional dengan melalui dua fase penting. Pertama, ketika dia tinggal di Surabaya, yaitu rumah Tjokroaminoto, seorang tokoh pergerakan nasional kenalan bapaknya. Rumah Tjokroaminoto merupakan “universitas politik” bagi Bung Karno, dimana ia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan dan menyerap teori-teori politik mereka.
Kedua, ketika Bung Karno melanjutkan sekolahnya di HBS Bandung, tempat dimana ia mendengarkan kuliah-kuliah dari sosialis-demokrat dan demokrat radikal Belanda. Di Bandung, Bung Karno menemukan semangat lain, bukan hanya karena mendengar ceramah-ceramah orang-orang sosialis demokrat macam J.E. Stokvis dan C. Hartogh, tetapi juga karena mendapat siraman radikalisme dari tokoh-tokoh pergerakan Indische Partij, seperti Tjipto Mangkunkusumo dan Douwes Dekker.
Kedua pengalaman itu sangat mempengaruhi gagasan-gagasan politik Bung Karno muda. Di satu sisi, dia sangat kagum dengan guru dan sekaligus mertuanya, Tjokroaminoto, tetapi kurang puas dengan langkah moderatnya. Sedangkan, pada sisi yang lain, dia semakin menyerap teori-teori baru (nasionalisme radikal dan sosialisme) dan memantapkan diri untuk terbenam dalam perjuangan anti-kolonialisme dan pembebasan rakyat.
Namun, pada tahun 1921, Bung Karno mulai menyaksikan dinamika yang sangat cepat di kalangan pergerakan; saling kritik, perpecahan, dan persatuan. Ada beberapa hal yang menandai situasi gerakan pada kurun waktu 1921 hingga 1926 (lahirnya tulisan Bung Karno: Marxisme, nasionalisme, dan islamisme). Pertama, semakin menguatnya pengaruh gerakan rakyat yang menolak untuk mengemis kemajuan kepada pihak kolonialis Belanda. Partai-partai ini, terutama sekali PKI dan Indische Partij, telah memaklumkan sikap non-koperasi terhadap pemerintahan kolonial. Bung Karno dalam sebuah pidato menggebu-gebu di tahun 1923, mengatakan: “….Sudah tiba saatnya untuk tidak lagi mengemis-ngemis, tetapi adalah menuntut kepada tuan-tuan kaum Imperialis.”
Seiring dengan periode surutnya gerakan mengemis-ngemis itu, maka pamor tokoh-tokoh semacam Tjokroaminoto dan Dr. Soetomo pun semakin merosot di mata kaum pergerakan dan rakyat.
Kedua, Bung Karno menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saling serang di kalangan pergerakan pembebasan nasional. Dalam tahun 1921, di dalam Sarekat Islam (SI), organisasi politik terbesar saat itu, telah terjadi perpecahan yang tak terhindarkan. Para pemimpin sayap kanan (SI putih) telah berhasil memaksa keluar pengikut-pengikutnya yang kiri (SI-merah)—yang sangat dipengaruhi oleh ISDV/PKI.
Pemuda Bung Karno juga menyaksikan bagaimana gurunya, Tjokroaminoto, diserang secara pribadi oleh Haji Misbach, tokoh haji merah yang berfikiran radikal dan anti-kolonial. Dalam kongres PKI itu, pemuda Bung Karno berdiri dan meminta Haji Misbach untuk meminta maaf.
Ketiga, Bung Karno menyaksikan kesuksesan setidaknya 17 organisasi mendirikan front persatuan yang diberi nama ‘Konsentrasi Radikal’, yang menggabukan organisasi, diantaranya, Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, Pasundan dan Perkumpulan Sosial Demokratis Indonesia.
Konsep Persatuan: Nasionalis, Islamis, Dan Marxis
Pada tahun 1926 Bung Karno mengeluarkan tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”, dimana ia menegaskan bahwa persatuanlah yang membawa kita ke arah “kebesaran dan kemerdekaan”.
Dalam tulisan itu, yang didalamnya disertai penjelasan yang sangat mendalam, Bung Karno menegaskan bahwa tiga aliran dalam politik Indonesia, yaitu nasionalis, agama, dan marxis, bisa bersatu untuk mencapai Indonesia merdeka.
“Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” demikian ditulis Bung Karno untuk menyakinkan keharusan front persatuan tiga kekuatan itu.
Dengan meminjam kata-kata Gandhi dan pengalamannya, Bung Karno telah menunjukkan bahwa kaum nasionalis bisa bersatu dengan kaum marxis dan pan-islamisme.
Bung Karno membedakan antara nasionalis sejati, yaitu nasionalis cintanya pada tanah-air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, dengan nasionalis chauvinis. Menurut pendapatnya, nasionalis sejati akan terbuka untuk bekerjasama dengan golongan politik lain yang memiliki tujuan sama.
Demikian pula terhadap islam, Bung Karno telah membedakan antara islam kolot dan islam sejati. “Selama kaum Islamis memusuhi faham-faham Nasionalisme yang luas budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum islamis tidak berdiri di atas Sirothol Mustaqim,” tulis Bung Karno.
Ditariknya pendekatan mengenai kesamaan antara islam dan marxisme, yaitu sama-sama bersifat sosialistis, dan letakkannya musuh bersama bagi keduanya; kapitalisme (paham riba).
Sementara terhadap kaum Marxis, Bung Karno telah mengambil taktik perjuangan kaum marxis yang baru, yaitu “tidak menolak pekerjaan-bersama-sama dengan Nasionalis dan Islamis di Asia”. Untuk menyakinkan kaum marxis, Bung Karno mengambil contoh: Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Nasionalis di negeri Tiongkok; dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis di negeri Afganistan.
Sesuai dengan keadaan Indonesia
Konsep persatuan diantara tiga kekuatan itu tidaklah jatuh dari langit, ataupun dari imajinasi biasa dari Bung Karno, melainkan dipetik dari kenyataan real dari keadaan Indonesia.
Bung Karno adalah salah seorang dari berbagai tokoh gerakan pembebasan nasional yang tidak menginjakkan kakinya di luar negeri, namun menyerap ilmu pergerakannya dari tokoh-tokoh terkemuka dunia pergerakan, seperti Tjokroaminoto, Tjipto Mangungkusumo, dan lain-lain.
Pengetahuannya mengenai marxisme didapatkan dari kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah kaum sosialis Belanda, dan paling banyak didapatkan dari berbagai literatur marxis yang dibacanya. Tetapi Bung Karno bukan seorang dogmatis, ia selalu berhasil meletakkan teori itu dalam syarat-syarat keadaan Indonesia dan dipergunakan untuk mencapai satu tujuan; Indonesia merdeka!
Demkian pula saat mengeluarkan konsep persatuan tiga kekuatan itu, Bung Karno telah mengambilnya dari kenyataan politik di Indonesia. Bagaiaman Bung Karno bisa membangun konsepsi persatuannya:
Pertama, Bung Karno adalah orang yang paling tekun dalam mempelajari berbagai aliran politik dalam gerakan nasional Indonesia. Dalam penyelidikan dan pengamatannya secara langsung, ketiga aliran itulah yang mewakili perjuangan melawan kolonialisme dan mewakili pengaruh luas di kalangan rakyat.
Bung Karno pernah menjadi anggota Sarekat Islam, meskipun tidak pernah terdaftar sebagai pengurus. Dia juga sering menemani Tjokroaminoto dalam menghadiri rapat-rapat akbar (vergadering) dan pertemuan-pertemuan.
Selain itu, ketika beraktivitas di Bandung, Bung Karno juga sangat dekat dengan tokoh nasionalis radikal, khususnya Tjipto Mangungkusumo, yang oleh belanda dikenal dikenal sebagai ”elemen paling berbahaya dalam gerakan rakyat di jawa.
Dari segi pemikiran, Bung Karno sangat dipengaruhi oleh nasionalis-nasionalis progressif, terutama Gandhi dan Sun Yat Sen. Dia juga bersentuhan dengan pemikiran nasionalis-nasionalis lain macam Mazzini, Cavour, dan Garibaldi.
Terhadap gerakan komunis, Bung Karno sangat tekun mempelajari marxisme dan menyebut dirinya sebagai Marxis. Semasa di rumah Tjokroaminoto, Bung Karno telah berkenalan dengan Snevleet, Baars, dan orang-orang Indonesia: Semaun, Musso, Tan Malaka, dan Alimin. Bahkan Bung Karno mengakui bahwa Marhaenisme, hasil temuannya sendiri, adalah marxisme yang dicocokkan dan dilaksanakan menurut keadaan Indonesia.
Kedua, Bung Karno, seperti juga kaum marxis pada umumnya, mengakui adanya kontradiksi tak terdamaikan antara kolonialisme/imperialisme dengan rakyat Indonesia, atau dalam bahasa Bung Karno: pertentangan sana dan sini; sana mau kesana, sini mau ke sini.
Dengan begitu, tidak benar juga kalau dikatakan front persatuan ala Bung Karno ini terlalu eklektis, sebab pembedaan sini dan sana itu sudah merupakan sebuah pembedaan yang jelas, gamblang.
Bung Karno sangat menyakini, bahwa jika ketiga kekuatan ini dapat disatukan dalam sebuah persatuan, maka dia menjadi gabungan kekuatan yang maha dahsyat. Karena, menurut perhitungan Bung Karno, gabungan kekuatan ini meliputi 90% paling sedikit daripada seluruh rakyat Indonesia.
Lapangan Praktek
Pada bulan September 1927, berpidato di hadapan peserta kongres Partai Sarekat Indonesia, Bung Karno telah mengusulkan untuk mendirikan semacam federasi diantara organisasi-organisasi pergerakan nasional.
Ide yang dilemparkan Bung Karno mendapat sambutan luas, dan kepada Bung Karno diserahi tugas untuk merancang konsep persatuannya. Dan, pada desember 1927, enam organisasi politik telah bersepakat mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Namun, Bung Karno berhasil menyatukan perbedan-perbedaan diantara organisasi terkait taktik, khususnya soal koperasi dan non-koperasi, dengan mengatasnamakan tujuan kemerdekaan. Akan tetapi, sebagai konsekuensi logisnya, Bung Karno gagal membawa federasi ini menjadi radikal.
Beberapa front persatuan sesudahnya, seperti Gabungan Aksi Politik Indonesia (GAPI), dimana Partindo tergabung di dalamnya, sedikit-banyaknya sesuai dengan konsep persatuan ala Bung Karno.
Lebih jauh lagi, rumusan persatuan tiga kekuatan ini akan sangat nampak pula dalam pidato Bung Karno mengenai dasar negara di depan BPUPKI, 1 Juni 1945, yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan Pancasila adalah rumusan dari tiga kekuatan; nasionalis, agamais, dan marxis. Bung Karno
mengatakan, pancasila itu dapat diperas menjadi tiga, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-nasionalisme, dan Sosio-demokrasi. Ketiga perasan pancasila tersebut, lanjut Bung Karno, masih dapat diperas lagi menjadi satu, atau sering disebut Ekasila, yaitu: Gotong Royong.
Belakangan, Bung Karno mempersamakan antara pancasila, Gotong-royong, dan Nasakom (nasionalis, Agama, dan Komunis). “Nasakom adalah perasan dari pancasila, dus nasakom adalah sebenarnya juga gotong royong, sebab gotong royong adalah de totale perasan dari pancasila, maka perasan daripada Nasakom adalah gotong royong pula,” demikian kata Bung Karno pada pembukaan kursus kilat kader Nasakom, 1 Juni 1965.
Pada tahun 1959, Soekarno telah memprakarsai pembentukan Front Nasional, yang tujuannya adalah menuntaskan revolusi nasional dan dibentuknya sebuah masyarakat adil dan makmur. Soekarno, yang telah berhasil menyakinkan PKI, berusaha menghidupkan kembali kolaborasi antara kaum nasionalis, agamais, dan marxis untuk menghadapi imperialisme.
PKI sendiri sangat menyambut uluran tangan Bung Karno untuk bersama-sama melawan imperialisme. Dan, di akhir tahun 1960-an, sebagaimana dicatat oleh Rex Mortimer, PKI telah secara terbuka menegaskan untuk mensubordinasikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional.
Sebetulnya Front Nasional dirancang untuk memobilisasi seluruh kekuatan rakyat guna melawan imperialisme. Dan, untuk mencapai tujuan-tujuan itu, Soekarno menganjurkan agar Front Nasional dibangun hingga ke dusun-dusun. Sayang sekali, niat ini tidak sepenuhnya berjalan dan lebih banyak disabotase.
Di penghujung 1965, ketika sebuah kudeta merangkak berusaha menggusur dirinya dari kekuasaan, Soekarno menolak pertumpahan darah dan memilih untuk terus mengedepankan persatuan nasional. Pada pidato 17 Agustus 1966, Bung Karno menyerukan agar tetap memperkuat persatuan tiga kekuatan, yaitu Nasakom. Pun, ketika demonstrasi mahasiswa kanan menuntut Bung Karno agar segera membubarkan PKI dan ormas-ormas komunis, Ia telah menolaknya. Dan, dengan suara yang lebih tegas, bahwa Pancasila tidak anti Nas (nasionalis), tidak anti A (agama), dan tidak anti Kom (komunis)
Selengkapnya...
Imoerialisme Tidak Hanya Musuh Libya, Melainkan Musuh Semua Bangsa
oleh: Randy Syahrizal
Imperialisme-raksasa inilah yang harus kita lawan dengan keberaniannya kesatria yang melindungi haknya! Ir. Soekarno “Mencapai Indonesia Merdeka”
Serangan NATO terhadap Libya, yang sempat dikhawatirkan Hugo Chavez dan Fidel Castro, akhirnya benar terjadi. Serangan in...i di legitimasi oleh keputusan Dewan Keamanan PBB tentang Zona Larangan Terbang (No Fly Zone), Sabtu malam (18/3) waktu setempat, militer Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat mulai memborbardir kota Tripoli dan sekitar Benghazi lewat pesawat tempur, serta kapal-kapal perang di laut Mediterania. Lebih dari seratus rudal Tomahawk telah diluncurkan menuju ‘sasaran’. Hanya dalam beberapa jam, dilaporkan puluhan warga sipil tewas dan lebih dari 150 orang terluka, termasuk anak-anak. (Editorial Berdikari Online 21 Maret 2011)
Imperialisme selalu mencari-cari cara dalam menguasai sumber daya (pertambangan), perluasan pasar dan penundukan rezim sosialis (anti imperialisme) untuk kepentingan ekonomisnya. Imperialisme selalu mencari-cari alasan atas nama perlindungan warga sipil dari kediktatoran rezim yang anti Imperialisme, seperti saat Imperialisme AS menginvasi Irak dan menggantung Saddam Husein, begitu juga seperti upaya kudeta yang gagal saat mencoba menggulingkan Hugo Chavez (Presiden Venezuela). Situasi di Libya adalah sebuah upaya kembali penundukkan/penghancuran musuh-musuh idiologis Kapitalisme, dengan memanfaatkan situasi kemelut di Timur Tengah yang sedang mengalami kemelut politik (Situasi pasang revolusioner). Dalam situasi seperti ini, kediktatoran menjadi isu sentral dalam pertarungan politik. Amerika Serikat dan sekutunya memanfaatkan gejolak ini untuk merampok kekayaan alam negeri-negeri dunia ketiga, yang dalam hal ini adalah tindakan intervensi militer ke Libya.
Serangan tentara NATO yang diikuti oleh keterlibatan militer AS, Inggris dan Prancis adalah serangan yang direstui oleh Dewan Keamanan PBB dengan dalih menjaga kemanan di Libya tentang Zona Larangan Terbang (No Fly Zone). Serangan tersebut berawal dari kabar/pemberitaan yang belum jelas kebenarannya mengenai serangan pesawat jet tempur yang dilancarkan Qaddafi kepada demonstran sipil tak bersenjata yang menginginkan Qaddafi mundur. Hal ini disikapi PBB dengan mengutus NATO untuk menjaga Zona Larangan Terbang. Namun apa yang terjadi..? yang terjadi bukanlah tindakan pengamanan melainkan serangan membabi buta ke kota Tripoli dengan memborbardir kota Tripoli dan sekitar Benghazi lewat pesawat tempur, serta kapal-kapal perang di laut Mediterania. Lebih dari seratus rudal Tomahawk telah diluncurkan menuju ‘sasaran’. Hanya dalam beberapa jam, dilaporkan puluhan warga sipil tewas dan lebih dari 150 orang terluka, termasuk anak-anak.
Alih-alih dengan dalih demi kemanan masyarakat sipil, tindakan keamanan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB (NATO) yang juga melibatkan tentara AS, Prancis dan Inggris malah menyerang kemanusiaan di Libya. Menjadi jelas dan pantas tentunya pidato Muammar Qaddafi didepan sidang Dewan Keamanan PBB, “bahwa PBB Gagal menjaga perdamaian dunia, bahkan Dewan PBB adalah Dewan Teroris.”
Misi Perampokan yang dikemas dengan Misi Kemanusiaan
Sederhana saja jawabannya. Sewaktu AS dan sekutunya menginvasi Irak, kepentingan apa sejatinya dibalik penyingkiran Saddam Husein..? kemudian, ada apa dibalik kepentingan menggulingkan Hugo Chaves, memperkuat provokasi Korea Selatan dalam sengketanya dengan Korea Utara..? Merecoki Iran dll..? semata-mata hanya untuk menguasai bahan baku utama industri-industri besar imperialisme, semata-mata hanya untuk membuka dan meluaskan pasar, menjajah bangsa-bangsa agar tenaganya tetap murah, dan memonopoli kekayaan alam dunia dibawah bendera korporasi modal imperialisme neoliberal.
Maksud jahat ini lah yang kemudian dikemas dengan sebutan “misi pengamanan masyarakat sipil”, atau “misi demokratisasi” atau “misi hak asasi manusia” atau “misi menangkap penjahat perang” dan atau “memerangi terorisme.” Maksud jahat ini lambat laun membuka mata dunia bahwa kepentingan keserakahan adalah sejatinya maksud dibalik serangan yang membunuh banyak warga sipil tak berdosa, dan kepentingan itu bernama “Perampokan Kekayaan Alam”. Dalam hal ini Libya adalah Negara yang memiliki kekayaan atas 46,4 miliar barel cadangan.
Eksploitasi rasa kemanusiaan yang menyelubungi maksud ekonomi-politik imperialis telah berlangsung sejak era perang dingin, dan banyak menuai hasil. Oleh karena itu, kiranya penting bagi kekuatan progresif manapun untuk memperhatikan fakta “jebakan humanisme” ini sebagai pertimbangan dalam menentukan sikap politik. Tidak berarti harus membunuh rasa kemanusiaan dalam diri setiap orang, tapi selalu penting untuk menempatkan ekonomi-politik sebagai motif utama dalam sistem kapitalisme imperialistik yang menguasai dunia kini. Berpijak dari sini, kita mengutuk keras serangan militer Imperialis terhadap Libya, dan mendukung penyelesaian masalah internal bangsa Libya lewat cara-cara damai dan demokratis.
Lalu Bagaimanakah Sebaiknya Sikap Kita..?
Pemerintahan Boneka Imperialisme SBY-Budiono bersikap Netral dalam kasus ini. Ini adalah pilihan seorang pemimpin pengecut. Harusnya sebagai bangsa Indonesia yang juga pernah mengalami masa-masa porak poranda oleh Imperialisme, SBY mengutuk tindakan Dewan Keamanan PBB dan negeri-negeri Imperialis pengacau seperti AS, Inggris dan Prancis. Sikap netral pemerintahan SBY-Budiono semakin menguatkan pembuktian bahwa kita sedang dipimpin oleh anak-anak asuh Imperialisme.
Sebagai rakyat Indonesia, kita wajib meningkatkan kewaspadaan dan memperbanyak pengetahuan ekonomi dan politik untuk membentengi diri dan terlebih membentengi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari keserakahan Imperialisme yang hari ini sedang berjalan dan direstui oleh pemerintahan boneka. Sebagai rakyat yang sadar dan termaju, yakni kaum pergerakan harus menyatukan kekuatan, melipatgandakan kekuatan-kekuatan serta unsur-unsur yang berlawanan dengan Imperialisme Neoliberal, dengan satu kekuatan massa luas yang terorganisir program untuk menghempang jalannya neoliberalisme di tanah air.
Sebagai rakyat Indonesia yang memusuhi Imperialisme, kita patut memberi dukungan terhadap saudara-saudara kita yang hari ini jiwanya terancam oleh Imperialisme, oleh AS yang notabene adalah Terorisme yang paling nyata.
Tindakan nyata kita hari ini adalah menyadari diri tentang bahanya Imperialisme sebagai musuh bangsa-bangsa, hal ini hanya dapat kita pahami dan kita jalankan program perlawanan kepada imperialisme dengan jalan Persatuan Nasional Seluas-Luasnya, dengan menggandeng seluruh unsur-unsur yang dirugikan oleh Imperialisme Neoliberal, dan mengarahkan serangan langsung ke jantung kekuasaannya didalam negeri, yakni menyerang posisi dan sikap SBY-Budiono yang pro Neolib. Maka slogan kita untuk ini adalah “Hancurkan Imperialisme Neoliberal dan kaki tangannya, Rebut (Kembali) Kedaulatan Nasional”
Selengkapnya...
Kabinet Pajangan
Ada kemungkinan reshuffle kabinet tidak akan memuaskan. Sejumlah menteri yang dianggap bermasalah tidak diganti, melainkan hanya berganti posisi. Selain itu, menteri-menteri yang tidak maksimal menjalankan tugasnya, bahkan tidak kapabel, hanya dijawab dengan menambah wakil menteri.
Di mata publik, menteri-menteri bermasalah mestinya diganti. Sejumlah nama yang sudah tersandung berbagai kasus korupsi, ataupun kinerjanya dikritik luas oleh masyarakat, mestinya tidak diberi tempat dalam formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Akan tetapi, karena sebuah kompromi politik, SBY hanya menukar posisi menteri-menteri bermasalah itu.
Bahkan reshuffle kabinet membawa masalah baru: SBY telah membengkakkan birokrasi dengan menunjuk 19 wakil menteri. Akan terjadi penggemukan birokrasi di kementerian dan sekaligus pembekakan biaya. Padahal, jika kinerja kementerian dianggap kurang berjalan bagus, ada baiknya SBY mencari calon menteri yang pas.
Hal itu menjelaskan kepada kami beberapa hal. Pertama, SBY menjalankan reshuffle tidak sesuai dengan tuntutan publik, yaitu perbaikan kinerja menteri, melainkan sebagai jalur kompromi politik dengan berbagai kekuatan politik.
Dengan menempuh kompromi politik, SBY terlihat memprioritaskan “keamanan kekuasannnya” ketimbang optimalisasi pembangunan dan program kerjanya pemerintahannya. Artinya, reshuffle tidak ada hubungannya dengan antisipasi berbagai persoalan pembangunan dan persoalan rakyat.
Kedua, kabinet yang dibentuk SBY bukanlah kabinet kerja (zaken kabinet), melainkan kabinet pajangan. Para menteri ditunjuk bukan berdasarkan kapasitas dan keahliannya, melainkan untuk memuaskan aspirasi koalisi politik. Akibatnya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, banyak menteri yang hanya pajangan dan tidak bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan.
Ini makin diperjelas dengan penunjukan wakil menteri. Padahal, jika menteri itu memang memiliki kapasitas dan keahlian, maka tentu ia harus mampu menggerakkan organisasinya (kementerian dan departemen) dari pusat hingga dan daerah.
Seharusnya seorang menteri sudah bisa bekerja dengan bantuan para pejabat eselon I yang menduduki posisi direktur jenderal atau sekretaris jenderal kementerian. Akan tetapi, selama ini hal itu tidak pernah berjalan dengan baik. Dalam banyak kasus, pejabat-pejabat tersebut justru tidak difungsikan dengan baik oleh sang menteri, bahkan seringkali diamputasi fungsinya dengan penunjukan staff khusus, jubir dan sebagainya.
Ketiga, SBY seolah menjadi kepala pemerintahan yang “tersandera” oleh kekuatan-kekuatan politik di sekitarnya. Padahal, sebagai pemegang mandat dari rakyat melalui pemilihan langsung, SBY mestinya punya kekuatan untuk mengendalikan koalisi agar sejalan dengan kepentingan bangsa. Bukan sebaliknya.
Padahal, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden. Tidak ada satu kekuatan pun, bahkan mitra koalisi, yang semestinya bisa menghalangi seorang presiden dalam menyusun sebuah kabinet yang benar-benar bisa bekerja dengan baik dan membantu presiden menjalankan program kerjanya.
Kelima, Dengan pola reshuffle yang tak ubahnya “sharing kekuasaan dengan mitra koalisi”, SBY justru nampak memberi ‘celah’ kepada parpol-parpol itu untuk menjadikan kementerian sebagai arena mengumpulkan logistik.
Sikap parpol untuk kekeuh mempertahankan orang-orangnya di kementerian tentu juga dalam kerangka menjaga ‘sumber logistik’. Sehingga, kalaupun ada reshuffle, maka parpol-parpol itu akan berusaha agar orangnya tidak diganti tetapi bertukar posisi.
Kami sejak awal memang tidak percaya bahwa reshuffle kabinet akan mengatasi persoalan bangsa saat ini. Sebab, sejak awal kami sudah menyatakan bahwa pokok persoalan ada pada kepimpinan nasional: kepemimpinan SBY-Budiono gagal memperjuangkan kepentingan nasional dan seluruh rakyat.
Selengkapnya...
Ketahanan Pangan dan Spekulasi Pasar
Pada bulan Juni lalu, Menteri pertanian negara G-20 berkumpul di Paris, Perancis. Mereka membahas masalah yang cukup rumit: keamanan pangan dan harga yang terus meroket. Salah satu persoalan yang jadi pokok pembahasan adalah soal pengaruh aksi-aksi spekulatif di pasar komoditas terhadap harga pangan dunia.
Perdebatan ini sudah berkecamuk sejak tahun 2008, saat kenaikan harga pangan dunia memicu kerusuhan dan pemberontakan di sejumlah negara. Saat itu, mereka memperdebatkan membanjirnya uang di pasar komoditas global sejak tahun 2003.
Pada tahun 2008, berdasarkan catatan PBB, lonjakan harga pangan menyebabkan ratusan juta orang terjerumus dalam kemiskinan. Sementara kenaikan harga pangan tahun ini (2011) menyebabkan 44 juta terseret arus kemiskinan. Lalu, menurut sumber yang sama, kenaikan harga pangan pada tahun 2009 menyebabkan satu milyar orang, atau seper-enam, penduduk dunia, terus diintai oleh kelaparan.
Para pejabat PBB sendiri langsung menuding aksi spekulasi di pasar sebagai penyebab melonjaknya harga pangan berkali-kali lipat. Jean Ziegler, salah seorang pejabat PBB saat itu, menunjuk hidung sejumlah perusahaan ekuitas telah mengambil banyak keuntungan dari “kelabilan” harga pangan dunia.
Selain itu, seperti dilaporkan majalah Independent Inggris, korporasi agrobisnis global juga turut meraup keuntungan sangat besar dalam situasi itu. Sebut saja: Monsanto, salah satu pemain terkuat di agrobinis, dilaporkan menerima kenaikan keuntungan tiga kali lipat sejak tahun 2007. Sementara keuntungan Cargill, korporasi raksasa milik Amerika Serikat lainnya, tiba-tiba melonjak 86% pada periode yang sama.
Harga pangan dunia sekarang banyak ditentukan oleh segelintir orang di Chicago, Amerika Serikat. Di sebuah gedung bernama Chicago Board of Trade (CBOT), bursa berjangka tertua didunia yang berdiri sejak 1848, harga komoditi pertanian di seluruh dunia banyak ditentukan.
Padahal, orang-orang disana bukanlah petani, bukan pula pejabat yang terlibat dalam merumuskan kebijakan pertanian, melainkan para pengusaha dan spekulator yang menentukan harga berdasarkan prediksi musim, bencana, gagal panen, dan lain sebagainya.
Apa bahanya bagi Indonesia?
Situasi ini jelas sangat berbahaya bagi Indonesia. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, pasar pangan di Indonesia sudah terkoneksi dengan pasar pangan global. Saat ini, gara-gara pemerintah sangat tunduk pada resep neoliberal, hampir semua kebutuhan pangan di dalam negeri didapatkan melalui impor.
Kita sekarang benar-benar sudah menjadi negara importir pangan: antara tahun 1998-2001 kita menjadi negara importir beras terbesar di dunia; dan kini setiap tahun kita impor gula 40 persen dari kebutuhan nasional; impor sekitar 25 persen konsumsi nasional daging sapi; impor satu juta ton garam yang merupakan 50 persen dari kebutuhan nasional; dan impor 70 persen kebutuhan susu.
Situasi itu juga telah membawa konsekuensi lebih buruk: sektor pertanian di dalam negeri sudah hancur lebur. Pemerintah juga terlihat “sengaja” mengabaikan sektor pertanian, demi menyambut proposal korporasi-korporasi pangan global. Total impor pangan kita sudah mencapai Rp 45 triliun.
Kita benar-benar berhadapan dengan situasi sulit di masa depan: kita semakin bergantung kepada impor pangan untuk memberi makan 230 juta rakyat kita, sementara harga pangan global ditentukan “seenaknya” oleh segelintir tangan dan melalui spekulasi. Ini sama saja dengan menyerahkan leher kita untuk dibunuh.
Selengkapnya...
Freeport dan Rekolonialisme
Kehadiran PT. Freeport di Papua bersamaan waktunya dengan berdiri tegaknya sebuah rejim yang berusaha mengembalikan kolonialisme di Indonesia. Pada tahun 1967, setelah Bung Karno dan pendukungnya berhasil dilumpuhkan, rejim Soeharto sudah mulai intensif menjalin hubungan dengan negeri-negeri imperialis dan mengundang kehadiran mereka di Indonesia.
Melalui sebuah pertemuan di Jenewa, Swiss, dengan perwakilan kapitalis terbesar dan paling berkuasa di dunia, rejim Soeharto mulai menggelar karpet untuk menyambut masuknya kembali kapitalis asing menjajah Indonesia. Diantara perusahaan asing yang segera mendapat undangan, antara lain: PT. Freeport, General Motor, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemen, Goodyear, The International Paper Corporation, dll.
Apa yang dilakukan Soeharto sangat berlawanan dengan semangat revolusi Agustus yang berkobar sejak 17 Agustus 1945. Pada masa itu, revolusi yang digerakkan oleh massa berusaha mengambil-alih semua perusahaan milik asing, khususnya belanda, sebagai cara melikuidasi ekonomi kolonial.
Semangat revolusi agustus itu berlanjut hingga pasca Konferensi Meja Bunda (KMB). Sebuah gerakan nasionalisasi yang lebih besar terjadi pada tahun 1957, dimana 90% perusahaan perkebunan beralih ke tangan Indonesia, 60% perdagangan luar negeri beralih ke Indonesia, dan sekitar 240 pabrik, bank, pertambangan, perkapalan juga jatuh ke tangan Indonesia.
Pemerintahan Bung Karno, yang berdiri di atas semangat revolusi Agustus, sangat mendukung aksi nasionalisasi itu. Pemerintah saat itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Selain itu, usaha untuk melikuidasi ekonomi kolonial juga dilakukan dengan menerbitkan UU penanaman modal yang sangat membatasi modal asing.
Tetapi semua itu berbalik 100% ketika Soeharto berkuasa. Rejim ini mengesahkan UU penanaman modal asing yang baru, yang sangat memberi kesempatan kepada kapital asing untuk menguras kekayaan alam Indonesia. Salah satunya adalah PT. Freeport, perusahaan milik imperialis AS yang mengusai produksi emas dan tembaga dunia.
Menurut catatan Surjono H. Sutjahjo, seorang pengajar di Institut Teknologi Bandung, sejak tahun 1967 hingga sekarang kegiatan pertambangan Freeport di Papua sudah menghasilkan sedikitnya 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika dihitung dalam bentuk uang, maka nilainya bisa mencapai ratusan ribu billion.
Apa yang dilakukan PT. Freeport tidak berbeda jauh dengan cara-cara kolonialisme ratusan tahun yang lalu. Freeport telah mengeruk kekayaan alam kita dan membayar murah para tenaga kerja kita. Itu adalah dua ciri-ciri neo-kolonialisme, seperti pernah diucapkan oleh Bung Karno saat menyampaikan pidato pembelaan berjudul “Indonesia Menggugat” di hadapan pengadilan kolonial.
Kehadiran PT. Freeport di Indonesia menyebabkan—meminjam istilah Bung Karno—“banjir harta yang keluar Indonesia makin membesar, sedangkan pengeringan Indonesia malahan makin menghebat.” Freeport telah menjadi salah satu pipa dari para kolonialis untuk mengeruk “kemakmuran” dari bumi Indonesia.
Anehnya, dan ini sangat memalukan, bahwa proses perampokan kekayaan alam oleh Freeport justru dijaga atau digardai oleh TNI/Polri. Ini merupakan sesuatu yang sangat kontradiktif: TNI dan Polri yang seharusnya menjadi alat penjaga kedaulatan bangsa Indonesia, termasuk menjaga kekayaan alam, justru menjadi penjaga kepentingan modal asing atau imperialis di Indonesia.
Tetapi kita segera memahami hal itu, bahwa penempatan TNI/Polri untuk mengamankan Freeport di papua tidak terlepas dari watak pemerintahan nasional Indonesia saat ini yang menempatkan diri sebagai boneka atau antek penjajahan asing.
Selengkapnya...
unduh Booklet PRD
Bagi kawan-kawan yang ingin mengunduh Booklet Pasal 33 UUD 1945, silahkan klik link ini http://prd.or.id/berita/unduh-booklet-gerakan-pasal-33.html Selengkapnya...
Search
Pengunjung
Kategori
- Berdikari (14)
- Internasional (4)
- Kabar Juang (3)
- Kabar Rakyat (4)
- Organisasi (1)
- Politik (8)
- sastra (1)
- Soekarnoisme (6)
- Statement (5)
- Tokoh (4)
Jaringan
Mengenai Saya
- Randy Syahrizal
- mempunyai minat menulis sejak kuliah di Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra USU tahun 2003. Pernah menulis di beberapa media lokal (Sumatera Utara) dan Media Online Nasional. Blog pribadi saya : http://ceritadarimedan.blogspot.com