Tan Teng Kie :
Kritik Peranakan Tionghoa dalam
”Syair Jalanan Kreta Api”
Oleh : Randy Syahrizal*
Saya membaca karya Tan
Teng Kie dalam Buku ”Kesusastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia)
yang merupakan buku kompilasi dari pengarang-pengarang peranakan Tionghoa
diakhir abad ke 19. Di Jilid pertama buku ini, pada permulaan saya sudah
disajikan syair tanpa keterangan nama penulis yang bercerita tentang kedatangan
Raja Siam (Thailand) pada tahun 1870 ke Batavia, yang disambut oleh Tuan
Residen Batavia. Yang menarik justru dugaan penerbit atas syair ini sebagai
buah karangan Tan Teng Kie, mengingat gaya penulisannya yang mirip dengan
Dalam syair itu dilukiskan
bahwa Tuan Residen Batavia menjalin persahabatan dengan Raja Siam. Karena
persahabatan itulah Tuan Residen membuat penyambutan yang meriah di Batavia,
mengarak Raja keliling kota dan disambut hormat oleh barisan serdadu kolonial
dengan penghormatan militer, juga pasukan berkuda, barisan preman, barisan
Islam dan barisan keturunan Tionghoa.
Saat membaca Syair Jalanan
Kreta Api, saya ikut pula menggeleng-gelengkan kepala dan kagum luar biasa atas
keberanian penulisnya untuk mewakili curahan hati rakyat kecil dengan bahasa
yang bisa dimengerti oleh rakyat pribumi. Dengan tulisannya itu, peranakan
Tionghoa telah membuktikan keberaniannya memelopori bahasa Melayu dalam tulis
menulis, terlebih lagi syairnya ini mengandung protes keras terhadap
Pemerintahan Kolonial Belanda.
Karena aktifitas
sehari-hari Tan Teng Kie sebagai pedagang, saya diajak mengingat kembali
definisi ”Orang Dagang” yang oleh Minke[1][1] di artikan sebagai orang yang
berpengetahuan luas tentang kebutuhan hidup, usaha dan hubungannya. Perdagangan
membikin orang terbebas dari pangkat-pangkat, tak membeda-bedakan sesama
manusia, apakah dia pembesar atau bawahan, bahkan budak pun. Pedagang
berpikiran cepat, mereka menghidupkan yang beku dan menggiatkan yang lumpuh
(Jejak Langkah: hal. 520). Kaum dagang adalah golongan yang tidak
menggantungkan hidupnya kepada pemerintahan kolonial (priyayi).
Pramoedya Ananta Toer,
dalam Roman ”Anak Semua Bangsa” menyebutkan bahwa bangsa Cina adalah bangsa
pengembara akibat kemiskinan ditanah airnya. Bangsa Cina secara bergelombang
sudah memasuki daratan Asia Tenggara sejak sebelum masehi. Di Hindia Belanda
(Indonesia) sendiri, golongan Tionghoa sudah sangat banyak dan terorganisir.
Belanda melalui VOC juga pernah berkonfrontasi dengan golongan ini pada Perang
Cina (1741-1743), dan perang yang berlangsung kurang lebih tiga tahun itu telah
menumbangkan kekuasaan VOC disepanjang pesisir utara Jawa. Dalam proses internalisasi
dengan masyarakat pribumi, orang-orang Tionghoa kemudian bercampur dengan
pribumi lewat perkawinan. Dan dari perkawinan inilah lahir angkatan baru, yakni
generasi Tionghoa Melayu.
Tan Teng Kie adalah
seorang indo peranakan Tionghoa (untuk membedakannya dengan pribumi
totok) yang hidup dimasa Kolonial Belanda dan tinggal di kota Batavia. Tak ada
tulisan dan dokumen apapun yang dapat memberikan keterangan riwayat hidupnya
menyangkut kelahiran dan masa kecilnya untuk melacak riwayat pendidikannya.
Dari buku ”Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia” hanya
didapatkan sedikit informasi saja mengenai kehidupan ekonominya, yakni dia adalah
seorang pengusaha yang memiliki toko di kota Batavia.
Syair pertama yang
diterbitkan atas namanya sendiri adalah ”Sya’ir Jalanan Kreta Api” yang terbit
di Batavia tahun 1890. Syair ini bercerita tentang pembuatan jalan kereta api pertama
dari Batavia ke Karawang dengan tujuan mengangkut kayu balok, pasir dan batu
Koral. Saya berpendapat bahwa syair ini adalah syair berbahasa Melayu pertama
yang paling berani dijamannya, karena melukiskan secara nyata penderitaan
kuli-kuli yang bekerja pagi hingga malam untuk menyelesaikan pembuatan jalan
kereta api jurusan Batavia – Karawang.
Pendapat diatas tentunya masih sebuah
hipotesa. Pendapat itu tentunya didukung oleh fakta sejarah bahwa penerbitan
surat kabar pribumi pertama berbahasa Melayu
(Medan Priyayi) yang dirintis oleh RM. Tirto Adhi Suryo baru dimulai
diawal abad ke 20. Pramoedya dalam Bumi Manusia dan Anak Semua bangsa
menggambarkan kepada kita bahwa Minke (RM. Tirto Adhi Suryo) sebagai tokoh
pelopor pers pribumi pada awal abad kedua puluh masih menulis dalam bahasa
Belanda, dan seperti pribumi terdidik lainnya yang masih beranggapan bahwa
Belanda (Eropa) adalah guru besar peradaban. Pribumi terdidik ini malah memilih
menulis untuk surat kabar – surat kabar milik Belanda dengan bahasa Belanda.
Peranakan Tionghoa lebih
dahulu membuat organisasi modern dan berserikat sebelum pribumi memulainya,
adalah Tiong Hoa Hwee Koan yang disahkan oleh pemerintahan Kolonial
Hindia Belanda pada tahun 1900 di Batavia. Dan diakhir abad ke 19, Tionghoa
sudah lahir sebagai pelopor dalam penulisan berbahasa Melayu pada surat-surat
kabarnya sendiri.
Saat saya membaca ”Sya’ir
Jalanan Kreta Api” banyak kalimat yang membuat saya bingung. Bahasa yang
dipakai oleh peranakan Tionghoa sebelum kemerdekaan Indonesia merupakan
campuran bahasa Melayu dengan bahasa Tionghoa, umumnya dengan dialek daerah
Fujian atau Hokkian (Myra Sidharta: Kata pengantar Jilid I Kesastraan Melayu
Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia).
Pada bait-bait pertama Syair
Jalanan Kreta Api, Tan Teng Kie melukiskan kisah penggusuran rumah disepanjang
jalan yang akan dibangun perlintasan jalan kereta api, dengan biaya ganti rugi
yang sudah ditentukan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Beginilah
bunyi bait-bait itu didalam syairnya:
Banyak puhun di
tebangin
Ongkos
Maskapij semuwa bayarin
Rumah
orang pada di buka’in
Kepada
juraganlah di serahin
Banyak
kelanggar rumah kampungan
Tuwan
tanah Tan Kang Ie punya bilangan
Eretannya
beda banyak kurangan
Ada
jambatan aken sebrangan
Maskapij
bayarin orang kampungnya
Apa
yang sudah kerusakannya
Keluwar
ongkos dengan sepatutnya
Yang
mana kena di ukurnya
Tan Teng Kie juga
melukiskan penderitaan para pekerja yang didatangkan dari Banten. Koeli dari
Banten memang terkenal dengan kebiasaan bekerjanya dalam jam kerja yang sangat
lama dan bersedia menerima upah murah. Tan juga menuliskan bait yang
menggambarkan ketidakadilan yang dialami pekerja, terutama masalah waktu kerja
yang sangat lama dari pagi hingga malam hari dengan upah yang rendah. Tan juga
mempersoalkan kesehatan para koeli, yang hanya sedikit waktu tersisa untuk
beristirahat. Baginya masalah kurangnya waktu istirahat dengan beban kerja yang
amat berat adalah cara mendekatkan diri pada kematian.
Kuli kerja sesungguh
hati
Siyang
dan malam tiyada berhenti
Kerja
cape ta’ takut mati
Supaya
dapat ringgit yang puti
Dia juga melukiskan
penderitaan yang dialami pekerja akibat perlakuan kasar dan juga kecelakaan
kerja yang tidak mendapat pertanggungjawaban dari para mandor. Dia juga
menggambarkan perasaan pekerja yang sangat takut akan hardikan mandornya.
Berikut ini adalah kutipan dari bait-bait yang melukiskan kejadian itu.
Yang jadi Chef[2][2]
tuwan Merkestijn
Pantas
dilihat seperti kaptein
Bagus
aturannya bagaimana asisten
Pekerja’annya
bajik dengan telaten
Romannya
cakap tinggi besar
Badannya
gemuk serta kasar
Aturannya
beres seperti husar[3][3]
Suwatu
pekerja’an tiada tersasar
Lalu baitnya tentang kecelakaan kerja:
Kolar[4][4]
pasir digerobakin juga
Banyak
kuli tiyada keduga[5][5]
Kulon
wetan mandor menjaga
Aken
uruk solokan[6][6]
gelaga
Kuli
kerja’in rawa itu
Uruk
tanah pasir dan batu
Ada
yang mati kulinya satu
Kelanggar
salat si setan hantu
Relnya
jatoh ketindes jari
Hamba
melihat sampe mengeri
Putus
duwa yang dipikiri
Salah
badannya diya sendiri
Si
kuli jatuh dari jambatan
Seperti
juga dijorokin setan
Temannya
buru berselabutan
Diangkat
lantas tarik ke daratan
Serenta dinaeken itu
orangnya
Dipreksa
sudah patah kakinya
Diprentah
lantas oleh mandornya
Disuruh
gotong pulang kerumahnya
Se’orang
kuli asalnya Cianjur
Ketimpa
balas sikutnya ancur
Badannya
apes tambahan lacur
Ambilin
ayer lantas dikucur
Begitulah bait-bait yang
mengandung kritikan atas penindasan yang dilakukan pemerintahan kolonial Hindia
Belanda terhadap rakyat pribumi. Dan jika membaca keseluruhan syair ini,
tampaklah dengan jelas bahwa kritikan tersebut tidak hanya tertuju kepada
Kolonial Belanda semata, tapi juga diarahkan kepada golongan tuan tanah
Tionghoa yang bersekutu dengan Belanda.
Sayang sekali tidak banyak
referensi yang menyajikan informasi mengenai riwayat hidup Tan Teng Kie yang
mengisahkan latar belakang pendidikan, keluarga, pergaulan, dan aktifitas
sosialnya. Namun dari profil Lie Kim Hok yang menulis Kitab Eja A.B.C[7][7] (1884) yang menuntun cara mengeja
kata-kata bahasa Melayu, saya menduga bahwa Tan Teng Kie yang jika dilacak dari
tahun terbit tulisannya adalah generasi yang sama dengan Lie Kim Hok, dan mungkin
juga sebagai salah satu dari para pendiri Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), yang
salah satu pendirinya adalah Lie Kim Hok. Sangat mungkin kritik yang digunakan
oleh Tan Teng Kie juga berasal dari ajaran Konfusius (seperti yang diamalkan
oleh organisasi THHK) yang juga mengajarkan kemanusiaan dan kebajikan sesama.
*Penulis adalah Kader PRD Sumut
[7][7] Dalam tulisan kata pengantar yang ditulis
oleh Myra Sidharta, kitab yang ditulis Lie Kim Hok ini adalah pelopor Bahasa
Melayu Tionghoa.

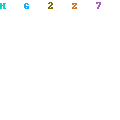

0 Comments Received
Leave A Reply